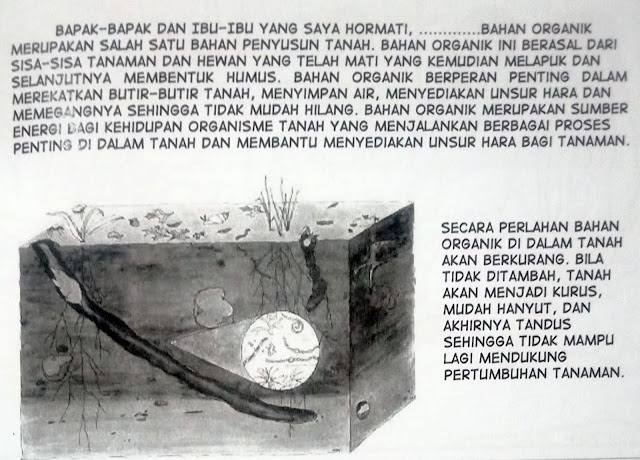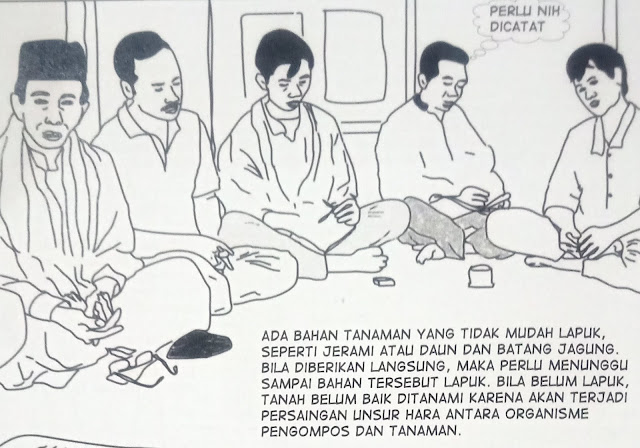Titik Kritis Pelaksanaan Survey KSA 30 Sep 2024 7:57 PM (6 months ago)

Hingga saat ini
pengumpulan luas panen padi maupun palawija masih menggunakan metode
konvensional dengan menggunakan dokumen statistik pertanian (SP). Pengumpulan
data luas panen tersebut masih didasarkan pada hasil pandangan mata (eye
estimate) petugas pengumpul data. Meskipun secara praktek, metode tersebut
mudah diterapkan tetapi masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi data dan
waktu pengumpulan data yang cukup lama.
Saat ini BPS mencoba menggunakan tekonologi aplikasi yang mengintegrasikan data
spasial dan data lapangan melalui Kerangka Sampel Area (KSA).
Survei KSA itu merupakan salah satu tugas dari BPS untuk
mendapatkan data mengenai luas panen tanaman pangan padi dan jagung. Survei KSA
ini juga untuk mengetahui perkembangan fase tanaman pangan padi dan jagung,
serta sebagai rujukan dasar untuk sampel ubinan padi.
Berbeda dengan survei-survei lain yang pernah dilakukan
Badan Pusat Statistik (BPS), survei tanaman pangan terintegrasi dengan metode
kerangka sampel area (KSA) muncul dengan pendataan yang modern. KSA
memanfaatkan smartphone berbasis android dan menggunakan aplikasi
KSA yang dikembangkan oleh BPPT untuk pengumpulan datanya.
Survei KSA di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2017
untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta, dan pada
tahun 2018 ini dilaksanakan di seluruh provinsi.
Pelaksanaan Survei KSA diawali dengan pelatihan petugas , Pelatihan
tersebut diadakan untuk melatih petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang
sama terkait konsep, tata cara pendataan dan cara menggunakan aplikasi KSA.
Setelah pelatihan di kelas, diadakan try out di daerah
persawahan agar petugas tidak hanya membayangkan pekerjaan yang akan dilakukan
nantinya, tetapi tahu betul pekerjaan petugas nantinya.
Pendataan survei KSA dilakukan setiap bulan, mulai Januari hingga
Desember. Pendataan dilakukan setiap 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan
sesuai beban tugas yang telah diberikan. Setiap petugas memiliki beban tugas
berkisar 3 – 8 segmen, dan disetiap segmen petugas harus mengunjungi dan
melaporkan hasil pengamatan untuk 9 titik amat yang telah
ditentukan. Bentuk laporannya adalah pengiriman data nilai pengamatan dan foto
hasil pengamatan melalui aplikasi KSA.
Dalam kegiatan “KSA” dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik
pengamatan dalam sampel segmen berupa bujur sangkar. Luas kerangka sampel
area (segmen) ditetapkan sebesar 300 m x 300 m agar dapat mengakomodir
banyaknya segmen dan sebarannya untuk memperoleh estimasi hingga level
kecamatan. Satu segmen terdiri dari sembilan subsegmen yang berukuran 100 m x
100 m dan memiliki titik tengah sebagai tempat titik pengamatan fase tumbuh
padi. Dalam melakukan pengamatan petugas lapangan menggunakan handphone
dengan sistem operasi android yang didukung fitur kamera dan GPS dengan
aplikasi KSA yang harus diinstal di dalamnya. Melalui aplikasi KSA ini petugas
melakukan perekaman dan pengiriman data hasil pengamatan masing-masing segmen
di lapangan.
Implementasi KSA dimulai dengan pembangunan kerangka
sampling dengan memanfaatkan beberapa data spasial, yaitu peta administrasi,
peta sawah, peta tutupan lahan, dan peta topografi. Kerangka sampel dibangun
dengan meng-overlay peta-peta tersebut secara bersamaan. Kerangka sampel
kemudian dikelompokkan menjadi empat strata sebagai berikut:
• Strata-0 (S-0) yang berisi poligon dari lahan yang tidak
dapat ditanami, seperti hutan, perkebunan, kolam, badan air, dan pemukiman.
Strata ini akan dikeluarkan dari pemilihan sampel.
• Strata-1 (S-1) memuat poligon sawah beririgasi, baik
dibudidayakan setahun sekali, dua kali atau lebih. Segmen dalam strata ini akan
dipilih sebagai sampel.
• Strata-2 (S-2) berisi poligon sawah non-irigasi atau tadah
hujan. Segmen dalam strata ini juga akan dipilih sebagai sampel.
• Strata-3 (S-3) berisi poligon yang diduga sawah, yang
dalam praktiknya sebenarnya adalah poligon lahan kering.
Setelah kerangka sampel area distratakan, kerangka sampel
kemudian dibagi menjadi grid dan sub-grid berukuran 6 km x 6 km dan 300 m x 300
m. Sampling acak kemudian diterapkan untuk mendapatkan sampel segmen. Sampel
segmen terpilih dilengkapi dengan informasi georeferensi dan informasi ID (kode
provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kode pengacakan) yang kemudian diamati
secara periodik (bulanan) oleh surveyor.
Pengamatan lapangan Survei KSA dapat dianggap sebagai studi
panel karena sampel segmen yang sama akan diamati setiap bulan tanpa
penggantian sampel. Dalam melakukan pengamatan lapangan, surveyor menggunakan
smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi Android, yang secara khusus
dikembangkan untuk KSA. Surveyor mengamati fase pertumbuhan dan mengambil
gambar di titik pusat semua sub-segmen dalam segmen yang dipilih. Ada sembilan
sub-segmen di setiap segmen berukuran 100 m x 100 m untuk diamati oleh seorang
surveyor. Informasi fase pertumbuhan dan gambar yang diperoleh dari
masing-masing sub-segmen kemudian dikirim ke pusat pengolahan data (server)
secara online. Prosedur ini dapat meminimalisasi subjektivitas dalam
mengidentifikasi fase pertumbuhan tanaman padi. Hasil akhir adalah estimasi
luas tanaman padi sesuai dengan fase pertumbuhan, yaitu persiapan lahan,
vegetatif, generatif, dan panen. Ilustrasi fase tumbuh tanaman padi yang yang
diamati petugas lapangan. Selain fase tumbuh, petugas juga mengumpulkan hasil
amatan lainnya, yaitu puso/rusak, bukan sawah, dan sawah yang tidak ditanami
padi.
Titik Kritis Pelaksanaan Survey KSA
Beberapa aspek yang menjadi titik lemah dalam pelaksanaan
Survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS adalah :
a)
Sulitnya menjangkau lokasi tertentu. Hal
ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti: Lokasi berada di hutan
yang lebat, Lokasi berada di tengah hutan dan harus melewati sungai, Lokasi
sulit diakses.
b)
Selain itu dimungkinkan sampel KSA berada di luar
batas administrasi sehingga menimbulkan potensi bias dalam perhitungan luas
panen suatu daerah.
c) Potensi
ketidaksesuaian antara Lokasi sampel KSA berdasarkan kriteria polygon S1,S2 dan
S3 dengan kondisi actual dilapangan. Hal ini menyebabkan titik Lokasi sampel KSA
yang berada dalam suatu daerah yang tidak ada lahan sawahnya.
Untuk mengatasi hal ini, BPS
dapat mengusulkan penggantian sampel pada lokasi-lokasi yang sulit
dijangkau. Penggantian sampel dapat dilakukan jika dalam satu segmen
terdapat lebih dari lima subsegmen yang menunjukkan kenampakan lahan bukan
sawah. Selain itu, penggantian sampel juga dapat dilakukan
jika ada lebih dari satu subsegmen yang tidak dapat diakses.
Untuk mengusulkan penggantian
sampel, petugas dapat melampirkan bukti foto subsegmen dan mengisi form usulan
penggantian sampel segmen.
Penulis. Sept.2024
Referensi
Memperbaiki Data Pangan Indonesia
Lewat Metode Kerangka Sampel Area. (Kadir Ruslan) Center for Indonesian Policy
Studies. Juli 2019
MISTERI PENURUNAN PRODUKTIVITAS PADI 27 Sep 2024 3:28 AM (7 months ago)

Data perberasan merupakan data yang paling banyak mendapatkan atensi. Mengingat beras merupakan
komoditas vital bagi Bangsa Indonesia, mengingat beras merupakan bahan pangan utama bagi 270 juta Masyarakat Indonesia. Namun kerap kali persoalan beras terjadi manakala dihadapkan kepada tantangan ketahanan produksi. Yang mana ketahanan produksi beras merupakan factor utama untuk menuju swasembada pangan yang diharapkan.
Salah satu problem dalam kalkulasi produksi beras adalah persoalan peningkatan
produktivitas padi. Seringkali aspek produktivitas menjadi bahan perdebatan
antara BPS selaku otoritas yang menerbitkan data resmi produksi beras dan
Kementerian Pertanian RI yang menggawangi persoalan pertanian khususnya perberasan.
Masalah produktivitas menjadi suatu hal
penting yang sulit untuk ditingkatkan dalam Pembangunan ketahanan pangan
nasional. Produktivitas produktivitas padi nasional sering mengalami fluktuasi
bahkan relative stagnan. Padahal baik teknologi budidaya, maupun pasca panen telah
diupayakan sedemikian rupa dengan gelontoran anggaran yang mencapai triyunan
rupiah.
Lalu apakah yang menjadi sumber persoalan dalam masalah kenaikan
produktivitas beras nasional. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas.com ( 3
Juli 2020), Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan
bahwa Luas panen padi th. 2019 = 10,68 juta hektar (turun 6,15 %
dibanding th 2018 = 11,28 juta hektar). Produksi padi th. 2019 = 54,60 juta ton
GKG (turun 7,76 % dibanding th 2018 = 59,18 juta ton GKG). Produksi beras
th. 2019 = 31,31 juta ton (turun 7,75 % dibanding th 2018 = 33,94 juta ton)
Lebih lanjut Bustanul Arifin menearangkan penyebab utama turunnya
produksi padi : Konversi lahan sawah yang signifikan terutama disentra
produksi padi seperti pantai utara jawa (jawa barat,tengah, dan timur).
Disamping itu Penurunan produktivitas padi
dapat terjadi pada 3 dimensi yaitu :
1.Substansi teoritis
Penurunan provitas padi boleh jadi disebabkan
oleh faktor kapasitas produksi pertanian Indonesia yang memang telah
menurun atau mendatar (levelling off). Provitas padi Indonesia 2019 sebesar 5,2
ton/ha sebenarnya lebih tinggi dari Thailand 3,1 ton/ha,Myanmar 3,8 ton/ha,
Filipina 4 ton/ha, dan Malaysia 4,1 ton/ha. Akan tetapi lebih rendah dari
Vietnam 5,8 ton/ha, Jepang 6,6 ton/ha, dan China 7 ton/ha.
Artinya secara teori Indonesia masih
memiliki kesempatan untuk meningkatkan provitas dan kapasitas produksi dengan
perubahan teknologi yang lebih unggul.
2. Analitis
metodologis
Penurunan provitas padi bisa saja terjadi
karena luas baku sawah yang terlalu besar, sehingga luas panen padi juga besar.
Hal ini mengacu kepada data luas baku sawah tahun 2019 sebesar 7,46
juta hektar. Selain itu pelaporan data padi yang menggunakan metode KSA dalam
mencatat data fase pertumbuhan, belum diimbangi dengan akurasi pelaporan dalam
sampel data produksi yang masih bias.
3. Empiris
kebijakan
Pada periode 2018-2019 pemerintah masih gencar dengan UPSUS PAJALE,
hampir semua jajaran birokrasi pertanian seluruh Indonesia ditargetkan untuk
meningkatkan LTT Padi, jagung dan kedelai. Peningkatan LTT tanpa perbaikan
sistem produksi budidaya yang baik (GAP) jelas menurunkan provitas.
Ditengah persoalan peningakatan produktivotas
padi Bustanul Arifin memberikan altenatif solusi pemecahannya diantaranya ; Kombinasi peningkatan kapasitas produksi
dengan, perubahan teknologi, perbaikan akurasi sampel pelaporan data LP dan
produksi padi, dan integrasi manajemen usaha tani serta kebijakan pertanian
yang mendukung. Dengan demikian persoalan peningakatan produktivitas padi dapat
diselesaikan secara bertahap dan jangka panjang.
Dikutip dari
https://kompas.id/baca/opini/2020/07/03/misteri-penurunan-produktivitas-padi/
PERUBAHAN PARADIGMA PERTANIAN AGRIBISNIS MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN (TINJAUAN SECARA FILSAFAT ILMU DI INDONESIA) Bagian IV 16 Sep 2024 11:53 PM (7 months ago)

Konsep Dasar dan Penjabaran Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
1. Keterbatasan
Pertumbuhan (Limit to Growth)
Ada dua
kelompok besar yang menaruh perhatian
pada masalah pembangunan ekonomi
(economic development) yaitu
kelompok pesimistis dan optimistis. Kelompok yang pesimistis mendasarkan pemikiran pada hukum Entropy yang
menghasilkan pandangan limit to growth, sedangkan
kelompok yang kedua bersandar pada paradigma dissipative structure dari
Ilya Progogeni yang menganggap bahwa pertumbuhan tidak terbatas.
Kelompok yang pertama
menyarankan perlunya
dilakukan perubahan paradigma ekonomi yang lama sebagai
suatu sistem berdiri sendiri, digantikan dengan pandangan bahwa sistem ekonomi
merupakan bagian dari subsistem biofisik dan menyarankan perlunya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) merupakan
implementasi dari
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980’an sebagai respon
terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi
tinggi yang terbukti telah
menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun
kualitas lingkungan hidup. Konsep
pertama dirumuskan dalam Bruntland Report yang merupakan hasil kongres Komisi Dunia
Mengenai Lingkungan dan Pembangunan
PBB: “Pembangunan berkelanjutan
ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan
saat ini tanpa mengurangi kemampuan
generasi mendatang untuk
mewujudkan kebutuhan mereka”
(WCED, 1987).
Bedasarkan definisi pembangunan berkelanjutan tersebut, Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai berikut : …… manajemen dan konservasi basis sumberdaya
alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan
guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya
kebutuhan manusia
generasi saat ini maupun mendatang. Pembangunan
pertanian berkelanjutan menkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun
hewan,
tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak
secara ekonomis, dan diterima
secara sosial (FAO, 1989).
Sejak akhir tahun 1980’an
kajian dan diskusi untuk merumuskan
konsep pembangunan bekelanjutan yang operasional dan diterima secara universal
terus berlanjut. Beberapa definisi
konsep berkelanjutan dan pembangunan
bekelanjutan, dan tentunya
masih ada banyak lagi yang
luput dari catatan tersebut.
Walau banyak variasi definisi pembangunan
berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan, yang diterima secara luas ialah yang
bertumpu pada tiga
pilar: ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe, 1993).
Dengan perkataan
lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada
tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi
(profit), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (people), keberlanjutan ekologi alam (planet), atau pilar Triple-P
Penerapan pertanian organik merupakan salah satu dari pendekatan dalam
pembangunan berkelanjutan, karena itu pengembangan pertanian organik tidak
terlepas dari program pembangunan pertanian secara keseluruhan. Dalam
pembangunan pertanian berkelanjutan bukan berarti penggunaan bahan kimiawi
pertanian (agrochemical) tidak diperbolehkan sama sekali, namun sampai batas
tertentu masih dimungkinkan. Hal ini juga dipakai dalam penerapan konsep
pengendalian hama terpadu (PHT) selama ini. Masalah pembangunan pertanian
berkelanjutan telah diintegrasikan dalam program pembangunan pertanian yang diterapkan
dewasa ini. Dalam Grand Strategi Pembangunan Pertanian disebutkan bahwa
pembangunan pertanian hasus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memadukan
antara aspek organisasi, kelembagaan, ekonomi, teknologi dan ekologis.
Pembangunan agribisnis dilakukan dengan memberdayakan dan melestarikan
keanekaragaman sumberdaya hayati, pengembangan produksi dengan tetap menjaga
pelestarian dan konservasi sumberdaya alam (hutan, tanah dan air), menumbuh
kembangkan kelembagaan lokal dan melegalkan hal ulayat masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumberdaya alam bagi kegiatan pertanian (communal resources
management), serta dengan meningkatkan nilai tambah dan manfaat hasil
pertanian.
Simpulan
Defenisi dari teori Agribisnis menurut Davis dan Goldberg (1957)adalah Agribusiness is the sum total of all operations involved in
the manufacture and distribution off-farm supplies, production activities on
the farm, and storage, processing and distribution off-farm, commodities and
items from them. Secara konsep agribisnis adalah suatu manajemen di bidang
usaha pertanian dari hulu ke hilir dengan orientasi profit, dengan beberapa
subsistem antara lain, ketersedian sarana prasarana pertanian, budidaya/usaha
tani (on farm), pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pemasaran hasil
pertanian, dan subsistem kelembagaan pendukung. Secara aplikasi di lapangan
belum semuanya berjalan sesuai konsep, sulitnya merubah pola pikir usaha
pertanian masih subsisten komoditi dengan segala kekurangan sistem kelembagaan
usaha tani pelaku utama dan kelembagaan pengambil kebijakan.
Manajemen dan konservasi basis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan menkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial (FAO, 1989). Secara konsep pembangunan pertanian berkelanjutan masih membutuhkan proses perubahan pola pikir, sikap dan keterampilan pelaku utama, pengambil kebijakan dan stakeholder karena kerusakan pembangunan pertanian itu sendiri yang dimulai dari revolusi hijau, agirbisnis orintasi profit tanpa memperhitungkan lingkungan sehingga secara aplikasi pertanian berkelanjutan adalah pelengkap dari pertanian agribisnis sebelumnya bahwa manajemen usaha tani dari hulu ke hilir dengan beberapa subsistem dengan orientasi profit tanpa melupakan lingkungan hayati sebagai media utama keberlangsungan sumber daya alam kita
DAFTAR PUSTAKA
Burk, Monroe, 1994. Ideology and Morality in Economic Theory, dalam Lewis, Alan and Kare-Erek Warneryd (ed). Ethics and Economic Affairs, Routledge, London – New York.
Davis dan Goldberg, 1957. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta : Erlangga. Davis, R. C. 1957. Industrial Organization and Management.
Downey and Erickson, 1989. Manajemen Agribisnis. Erlangga. Jakarta
Downey, David W dan John K.Trocke. 1981. Agribusiness Management.
McGraw-Hill, Inc. US of America
FAO, 1989. Utilization of Tropical Foods : Tropical Oil-Seeds. Roma: Food and
Agriculture Organization
of the United Nations. Halaman 51-54.
Kasrino dan Suryana, 1992. What is the Participatory Rural Appraisal. SIL International (www.sil.org, diakses 28 Mei 2012.
Munasinghe. M., 1993. Environmental Economics and Sustainable Development.
Rustiadi, Eman, dkk., 2009. Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan YOI.
WCED., 1987. Our Common Future (The Brundlandt Report). Oxford University Press
PERUBAHAN PARADIGMA PERTANIAN AGRIBISNIS MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN (TINJAUAN SECARA FILSAFAT ILMU DI INDONESIA) Bagian III 16 Sep 2024 11:49 PM (7 months ago)

Perubahan Paradigma Lama
Petani di Indonesia tidaklah homogen ditinjau dari karakteristiknya. Ada petani
yang dapat digolongkan sebagai petani komersial, di mana ia menghasilkan produk untuk sepenuhnya dijual ke pasar. Pada sisi yang lain, ada petani yang digolongkan sebagai petani yang subsisten ataupun serni-subsistcn, dimana tidak seluruh produk yang dihasilkannya untuk keperluan dijual ke pasar melainkan sebagiannya untuk keperluan konsumsi sendiri. Perilaku pengambilan keputusan kcdua golongan petani ini diperkirakan dapat saja berbeda, sehinugn reaksi pctani terhadap suatu kebijakan pcmerintah mungkin saja borbcda di antara pctani dengan karakteristik yang berbcda.
Bagi petani subsisten
ataupun semisubsistcn. keputusannya sebagai
rumahtangga mungkin
tidak
dapat
dipisahkau dengan
keputusan
petani sebagai produscn. Dengan demikian analisis sosial-ekonomi rumah tangga petani di Indonesia,
perlu terus dikembangkan. Tanpa
adanva pengetahuan yang tepat terhadap perilaku petani di Indonesia. Ini akan sulit
diharapkan kebijakan apapun
yang
ditujukan bagi petani dapat
mencapai tujuannya, Pembangunan agribisnis di Indonesia di masa
mcndatang menghadapi tantangan yang
lebih
kompleks dibandingkan masa lalu. Proses globalisasi dalam
perekonomian, yang
disertai dengan
kesadaran demokrasi yang
meningkat, membawa konsekuensi berbeda dalam praktek pembangunan maupun
dalam
praktek
bisnis. Tuntutan akan peningkatan efisiensi yang
disertai dengan
tuntutan pemerataan keadilan menjadikan konsep-konsep agribisnis yang telah dikumandangkan pada
masa
lalu
perlu terus diperbaharui.
Perusahaan-perusahaan agribisnis, yang umumnya bersentuhan langsung dengan usaha petani skala kecil, perlu mempertajam maupun mempraktekkan {food corporate govermsnce agar dapat sustain dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengembangan konsep agribisnis maupun konsep pembangunan agribisnis di masa datang perlu lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan aspek govermance dan responsibility dari pihak-pihak yang ada di dalamnya. petani, perusahaan, dan pemerintah.
Analisis Peradigma Baru Pertanian Berkelanjutan Secara Filsafat Ilmu
-
Ontologi (Teori/ Paradigma Baru)
Kini tidak
mudah lagi menyepakati apa yang dimaksud dengan pembangunan Pertanian
Berkelanjutan, karena berbagai peringatan dan “potensi penyimpangan” di masa
lalu kurang mendapat perhatian. Pembangunan pertanian yang di atas kertas
mendapat prioritas sejak Repelita I
kebijakan dan strateginya dengan mudah dilanggar, dan program-program
“industrialisasi” lebih didahulukan. Sumber utama kekeliruan adalah lebih
populernya model-model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan
yang lebih cepat meningkatkan produksi dan pendapatan (GDP dan GNP), meskipun
tanpa disertai pemerataan dan keadilan sosial.
Seharusnya
kita tidak lupa peristiwa Malari Januari 1974 yang memprotes terjadinya
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial padahal Repelita I pada saat itu
baru berjalan 4,5 tahun, dan pertanian telah tumbuh rata-rata 5% per tahun.
Pemerintah Indonesia yang waktu itu bertekad memulai dan meningkatkan
program-program pemerataan “termanjakan” oleh minyak yang dengan sangat mudah
membelokkan dana-dana yang melimpah untuk “membantu” pengusaha-pengusaha swasta
yang leluasa membangun segala macam industri subsistitusi impor dan kemudian
industri promosi ekspor, kebanyakan dengan bekerjasama dengan investor asing,
khususnya dari Jepang.
Demikian
sekali lagi telah terjadi ketidakseimbangan pembangunan antara industri dan
pertanian, yang anehnya dianggap wajar, karena “model pembangunan yang dianggap
benar adalah yang mampu meningkatkan sumbangan sektor industri dan “menurunkan”
sumbangan sektor pertanian.
Inilah
suasana awal kelahiran dan mulai populernya ajaran “agribusiness” (agribisnis)
yang menggantikan agriculture (pertanian). Jika kita ingin mengadakan pembaruan
menuju Pertanian Berkelanjutan justru harus ada kesediaan meninjau kembali
konsep dan pengertian sistem dan usaha agribisnis. Saya tidak sependapat
agribisnis dimengerti sebagai “pertanian dalam arti luas” atau bahkan istilah
pertanian sudah tidak lagi dianggap relevan dan perlu diganti agribisnis.
Jika
konsekuen Kementerian Pertanian
juga perlu diubah menjadi Kementerian Agribisnis
atau Institut Pertanian diganti menjadi Insitut Agribisnis. Kami menolak
kecenderungan yang demikian yang di kalangan Fakultas-fakultas Ekonomi kita
juga sudah muncul keinginan mengganti nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Memang di Amerika sudah banyak School of Business, dan
Department of Economics hanya merupakan satu departement saja dalam School of
Business. Kami berpendapat ini sudah kebablasan. Seharusnya kita di Indonesia
tidak menjiplak begitu saja apa yang terjadi di Amerika jika kita tahu dan
patut menduga hal itu tidak cocok bagi tatanan nilai dan budaya petani dan
pertanian kita.
-
Epistemologi
(Metode/Mencari Kebenaran)
Mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang
dikeluarkan oleh
angenberg, maka keberhasilan pembangunan tentunya juga
harus dilihat dari capaian keempat dimensi
pembangunan berkelanjutan, sehingga akan
terlihat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tidak cukup jika pembangunan hanya terkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, tetapi dengan merusak
lingkungan. Dalam jangka panjang
kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian, karena boleh jadi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan lebih besar dari manfaat ekonomi yang diperoleh.
Begitu pula dengan pembangunan
yang
mengabaikan pembangunan kelembagaan
sehingga memunculkan
senjangan ekonomi
dan sosial. Kesenjangan sering kali menjadi
alasan
jadinya konflik bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim seperti separatisme. onflik seperti ini tentu akan memberikan dampak negatif
bagi pembangunan di
asa yang akan
datang.
Fenomena kesenjangan pendapatan dan kerusakan lingkungan akan lebih
pantau bila ukuran
pembangunan
yang
dipergunakan
juga
sensitif
terhadap uran kesenjangan
dan kualitas
lingkungan.
Indikator pembangunan rkelanjutan yang
berkembang selama ini di Indonesia belum mencakup empat mensi pembangunan berkelanjutan secara utuh.
Penghitungan Produk
Domestik uto (PDB)
hijau hanya melibatkan dimensi ekonomi dan lingkungan. Penelitian
ntang genuine saving hanya menyentuh dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.
kuran pembangunan berkelanjutan berupa indeks komposit
pernah pula digagas
eh beberapa institusi
dan
peneliti. Namun indeks komposit ini
juga
masih elibatkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimensi kelembagaan tidak munculkan sebagai dimensi tersendiri,
namun secara implisit tergabung
pada
mensi sosial. Karena indikator kelembagaan hanya bagian kecil dari dimensi sial, maka bobot kelembagaan dalam indeks komposit
menjadi sangat kecil, dahal permasalahan
kesenjangan yang menjadi
salah satu
indikator lembagaan
cukup
menonjol di Indonesia.
Pembangunan berkelanjutan,
yang
memunculkan
dimensi
kelembagaan
bagai dimensi tersendiri,
dipandang sangat tepat
untuk
kondisi
Indonesia. ondisi ini diharapkan berdampak pada
meningkatnya perhatian pada dimensi
lembagaan, tanpa mengabaikan dimensi yang
lain. Sebagai dimensi tersendiri
lembagaan akan memiliki bobot
yang lebih
besar dalam mengukur capaian mbangunan. Untuk itu, penyusunan indeks komposit yang memasukkan empat
mensi pembangunan berkelanjutan
(ekonomi,
sosial, lingkungan
dan lembagaan) akan menjadi bagian penting
dari pembangunan berkelanjutan pada mumnya, dan
khususnya untuk pembangunan
kelembagaan.
Selain menjabarkan pembangunan berkelanjutan ke dalam empat dimensi,
angenberg juga mengidentifikasi empat modal pembangunan. Keempat modal mbangunan tersebut adalah
man-made capital,
human
capital, natural pitaldansocial capital. Keseimbangan
penggunaan keempat
modal
tersebut
akan mendorong
terciptanya pembangunan
berkelanjutan.
Hingga
saat ini,
rhatian terhadap tiga modal yang pertama lebih dominan dibandingkan dengan
odal yang terakhir.
Padahal di sisi lain, modal sosial diduga
dapat mereduksi rmasalahan pembangunan
yang telah
disebutkan
sebelumnya.
Modal
sosial
harapkan akan mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dengan
norma saling membantu.
Modal sosial juga
diduga mampu
mencegah
lingkungan dengan adanya kearifan lokal. Modal sosial juga menjadi ama
untuk dapat mewujudkan kelembagaan yang kuat. Sebagai salah satu
dalam pembangunan,
sudah
sepatutnya modal
sosial mendapatkan
n yang seimbang
dengan modal yang lain.
-
Aksiologi (Kesimpulan Yang Didapatkan)
Sistem
ekonomi yang mengacu pada Pancasila yaitu Sistem Ekonomi Pancasila adalah
sistem ekonomi pasar yang memihak pada upaya-upaya pewujudan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun pertanian berkelanjutan sudah dapat
mencakup upaya-upaya mewujudkan keadilan namun pedoman-pedoman moralistik,
manusiawi, nasionalisme, dan demokrasi/ ’kerakyatan’ secara utuh tidak mudah
memadukannya dalam pengertian berkelanjutan.
Asas
Pancasila yang utuh memadukan ke-5 sila Pancasila lebih tegas mengarahkan
kebijakan yang memihak pada pengembangan pertanian rakyat, perkebunan rakyat,
peternakan rakyat, atau perikanan rakyat. Pertanian yang mengacu atau
berperspektif Pancasila pasti memihak pada kebijakan yang mengarah secara
kongkrit pada program-program pengurangan kemiskinan di pertanian dan
peningkatan kesejahteraan petani.
Misalnya
dalam kasus distribusi raskin (beras untuk penduduk miskin), orientasi ekonomi
Pancasila pasti tidak mengijinkan pengiriman raskin ke daerah-daerah sentra
produksi padi karena pasti menekan harga jual gabah/padi petani. Demikian pula
dalam kebijakan pengembangan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang kini sudah
dicabut, orientasi ekonomi Pancasila tidak akan membiarkan terjadinya
persaingan sengit di antara petani tebu dalam menjual tebunya ke pabrik, dan
sebaliknya pemerintah seharusnya tidak membiarkan pabrik-pabrik gula bertindak
sebagai monopsonis (pembeli tunggal) yang menekan petani tebu dalam menampung
tebu yang dijual oleh petani tebu rakyat.
Tinjauan
aspek sosial-ekonomi pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
yang kami sampaikan di sini berbeda atau mungkin berseberangan dengan kerangka
pikir yang mengarahkan semua topik pada pengembangan sistem dan usaha
agribisnis. Kami berpendapat istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan
pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan perdesaan (rural development)
yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa,
termasuk di antaranya petani.
Fokus yang
berlebihan pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian kita pada
petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap,
petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Apakah
mereka ini semua sudah tidak ada lagi di pertanian dan perdesaan kita? Masih
banyak sekali, dan merekalah penduduk miskin di perdesaan kita yang membutuhkan
perhatian dan pemihakan para pakar terutama pakar-pakar pertanian dan ekonomi
pertanian. Pakar-pakar agribisnis rupanya lebih memikirkan bisnis pertanian,
yaitu segala sesuatu yang harus dihitung untung-ruginya, efisiensinya, dan sama
sekali tidak memikirkan keadilannya dan moralnya. Pembangunan pertanian
Indonesia harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya
mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang
beruntung di perdesaan.
bersambung ........................
PERUBAHAN PARADIGMA PERTANIAN AGRIBISNIS MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN (TINJAUAN SECARA FILSAFAT ILMU DI INDONESIA) Bagian II 16 Sep 2024 7:33 PM (7 months ago)

Paradigma Pertanian Agribisnis
Mula-mula ilmu ekonomi (Neoklasik) dikritik pedas karena telah berubah menjadi ideologi (Burk.
dalam Lewis dan Warneryd, 1994: 312-334), bahkan semacam agama (Nelson: 2001). Kemudian pertanian dijadikan bisnis, sehingga utuk mengikuti perkembangan zaman konsep agriculture (budaya bertani) dianggap perlu diubah menjadi agribusiness (bisnis pertanian). Perubahan dari agriculture menjadi agribisnis berarti segala usaha produksi pertanian ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sendiri termasuk pertanian gurem atau subsisten sekalipun. Penggunaan sarana produksi apapun adalah untuk menghasilkan “produksi”, termasuk penggunaan tenaga kerja keluarga, dan semua harus dihitung dan dikombinasikan dengan teliti untuk mencapai efisiensi tertinggi.
Sepintas paradigma agribisnis memang
menjanjikan perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi para petani. Namun
jika kita kaji lebih mendalam, maka perlu ada beberapa koreksi mendasar
terhadap paradigma yang menjadi arah kebijakan tersebut.
Sebuah paradigma semestinya lahir dari akumulasi
pemikiran yang berkembang di suatu wilayah dan kelompok tertentu. Jadi sudah
sewajarnya jika kita mempertanyakan, apakah pengembangan paradigma agribisnis
adalah hasil dari konsepsi dan persepsi para petani kita?. Lebih lanjut dapat
kita kaji kembali apakah sudah ada riset/penelitian mendalam, yang melibatkan
partisipasi petani, berkaitan dengan pola/sistem pertanian di wilayah mereka?.
Hal ini sangat penting karena jangan-jangan paradigma agrisbisnis hanyalah
dikembangkan secara topdown dari pusat, yang tidak sesuai dengan visi
desentralisasi sistem lokal, atau lebih berbahaya lagi hanya mengadopsi
paradigma dari luar (barat). Lebih tepat apabila pemerintah berupaya untuk
membantu menemukenali segala permasalahan yang dihadapi petani dan bersama-sama
mereka mengusahakan jalan keluarnya, dengan memposisikan diri sebagai kekuatan
pelindung petani. Selama ini masalah yang muncul adalah anjloknya harga
komoditi, kenaikan harga pupuk, dan persaingan tidak sehat, yang lebih
disebabkan oleh kekeliruan atau tidak bekerjanya kebijakan atau peraturan
(hukum) yang dibuat oleh pemerintah.
Identifikasi Pertanian Agribisnis secara Filsafat Ilmu
- Ontologi (Teori Lama/Paradigma Lama Kita)
Davis dan Goldberg (1957) mendefinisikan agribisnis sebagai berikut:
Agribusiness is
the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution
off-farm supplies, production activities on the farm, and storage, processing
and distribution off-farm, commodities and items from them.
Definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud agribisnis mencakup
keseluruhan kegiatan mulai dari memproduksi dan distribusi input sampai dengan
distribusi hasil pertanian. Perhatikan bahwa on farm, atau
usahatani, sebagai kegiatan yang sering disebut secara umum sebagai pertanian,
hanya merupakan salah satu bagian dari agribisnis. Jika halnya demikian,
agribisnis harus melihat pertanian secara menyeluruh, bukan hanya melihat
kegiatan menghasilkan produk-produk pertanian di tingkat usahatani.
Pembangunan agribisnis yang dimaksud
adalah pembangunan
agribisnis sebagai satu kcsatuan sistcm secara sirnultan dan harmonis.
Pembangunan agribisnis dcngan
demikian mencakup pembangunan subsistem agribisnis hulu, yaitu kegiatan
ckonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian
seperti industri bcnih atau
bibit,
industri agrokimia, dan
industri agrootomotif: pembangunan subsistem
agribisnis usahatani atau
primer
(on-farm),
yaitu kegiatan ekonomi
yang menggunakan sarana
produksi pertanian untuk
menghasilkan
komoditas pertanian primer;
subsektor agribisnis hilir yaitu
kegiatan
ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer
menjadi
produk
produk olahannya, baik sebagai produk antara
maupun
produk
akhir,
beserta kegiatan pemasaran atau
perdagangannya: subsektor agribisnis pendukung, yaitu
kegiatan yang
menghasilkan atau menyediakan jasa
yang
dibutuhkan oleh
subsistem-subsistem
agribisnis lainnya, misalnya perbankan, transportasi, penelitian dan
pengembangan, kebijakan pemerintah, maupun penyuluhan
dan jasa
konsultan.
Pembangunan agribisnis sebagai
suatu
sistem
merupakan cara baru untuk memandang pembangunan
pertanian maupun pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai
masalah pembangunan. Seperti peningkatan pendapatan, pembukaan kesempatan
kerja, pemerataan pembangunan dan pendapatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, masalah kelestarian lingkungan dan
lain-lainnya dapat dipecahkan melalui pembangunan sistem agribisnis. Dengan
demikian strategi industrialisasi melalui pembangunan sistem agribisnis akan
sesuai jiwa trilogi pembangunan.
- - Epistemologi (Metode/Mencari Kebenaran)
Adanya backward linkages dan forward linkages sektor
pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari
sektor-sektor lainya. Peranan sektor pertanian menjadi lebih besar jika dinilai
dalam konteks adanya keterkaitan ke belakang dan ke depan tersebut. Jika sektor
pertanian tidak berkembang dengan baik, maka tidak akan ada kebutuhan terhadap
pupuk, obat-obatan, dan peralatan pertanian. Hubungan ini yang disebut
keterkaitan ke belakang (backward lingkages) dari sektor pertanian.
Keterkaitan antara pertanian dengan pengolahan hasil, disebut sebagai
keterkaitan ke depan (forward linkages).
Agribisnis memandang sektor pertanian secara utuh, bukan hanya sektor
primer tetapi mulai dari kegiatan pertanian yang menyediakan input sampai
dengan kegiatan pertanian dalam pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan jasa
penunjang pertanian (agriservices). Dengan cara pandang seperti ini maka
kontribusi sektor pertanian dalam pengertian agribisnis menjadi sangat besar.
Di waktu yang akan datang, peran sektor pertanian dalam pengertian agribisnis
menjadi semakin besar. Perubahan cara pandang di atas mempunyai konsekuensi
bahwa pertanian bukan sebagai way of life atau gaya hidup.
Pertanian merupakan bagian dari kegiatan bisnis besar yang mempunyai prospek
yang baik. Pertanian merupakan kegiatan produktif menghasilkan produk pangan
dan serat dengan memanfaatkan sumber daya pertanian seperti tanah, air, hara tanah,
sinar matahari, dan lain-lain.
-
Aksiologi (Kesimpulan Yang
Didapatkan)
Pengertian agribisnis yang paling banyak dijadikan acuan selama ini adalah
pengertian agribisnis yang dikemukakan oleh John Davis dan Ray Goldberg (Davis
and Goldberg, 1957). Menurut Davis dan Golberg (1957), agribisnis dipandang
bukan hanya kegiatan produksi di usahatani (on-farm), tetapi termasuk
kegiatan yang di luar usahatani (off-farm) yang terkait. Pemahaman yang
sama juga dikemukakan oleh Downey and Erickson (1989), Downey and Trocke
(1981), bahwa agribisnis meliputi kegiatan di usahatani dan di luar usahatani
yang terkait dalam pengadaan input pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran
hasil.
Paradigma
Agribisnis yang Keliru
Asumsi utama
paradigma agribisnis bahwa semua tujuan aktivitas pertanian kita adalah profit
oriented sangat menyesatkan. Masih sangat banyak petani kita yang hidup secara
subsisten, dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka
sendiri. Mereka adalah petani-petani yang luas tanah dan sawahnya sangat kecil,
atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, jagung, ataupun
ketela. Mencari keuntungan adalah wajar dalam usaha pertanian, namun hal itu
tidak dapat dijadikan orientasi dalam setiap kegiatan usaha para petani.
Petani kita
pada umumnya lebih mengedepankan orientasi sosial-kemasyarakatan, yang
diwujudkan dengan tradisi gotong royong (sambatan/kerigan) dalam kegiatan
mereka. Seperti di awal tulisan, bertani bukan saja aktivitas ekonomi,
melainkan sudah menjadi budaya hidup yang sarat dengan nilai-nilai
sosial-budaya masyarakat lokal. Sehingga perencanaan terhadap perubahan
kegiatan pertanian harus pula mempertimbangkan konsep dan dampak perubahan
sosial-budaya yang akan terjadi.
Seperti
halnya industrialisasi yang tanpa didasari transformasi sosial terencana, telah
menghasilkan dekadensi nilai moral, degradasi lingkungan, berkembangnya paham
kapitalisme dan individualisme, ketimpangan ekonomi, dan marjinalisasi kaum
petani dan buruh. Hal ini yang nampaknya tidak terlalu dikedepankan dalam
pengembangan paradigma pendekatan sistem agribisnis..Tidak semua kegiatan
pertanian dalam skala petani kecil dapat dibisniskan, seperti yang dilakukan
oleh petani-petani (perusahaan) besar di luar negeri, yang memiliki tanah luas
dan sistem nilai/budaya berbeda yang lain sekali dengan Petani kita.
Konsep dan paradigma sistem
agribisnis tidak akan menjadi suatu kebenaran umum, karena akan selalu terkait
dengan paradigma dan nilai budaya petani lokal, yang memiliki kebenaran umum
tersendiri. Oleh karena itu pemikiran sistem agribisnis yang berdasarkan
prinsip positivisme sudah saatnya kita pertanyakan kembali. Paradigma
agribisnis tentu saja sarat dengan sistem nilai, budaya, dan ideologi dari
tempat asalnya yang patut kita kaji kesesuaiannya untuk diterapkan di negara
kita. Masyarakat petani kita memiliki seperangkat sistem nilai, falsafah, dan
pandangan terhadap kehidupan (ideologi) mereka sendiri, yang perlu digali dan
dianggap sebagai potensi besar di sektor pertanian. Sementara itu perubahan
orientasi dari peningkatan produksi ke oreientasi peningkatan pendapatan petani
belum cukup jika tanpa dilandasi pada orientasi kesejahteraan petani.
Peningkatan
pendapatan tanpa diikuti dengan kebijakan struktural pemerintah di dalam
pembuatan aturan/hukum, persaingan, distribusi, produksi dan konsumsi yang
melindungi petani tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan petani ke tingkat
yang lebih baik. Kisah suramnya nasib petani kita lebih banyak terjadi daripada
sekedar contoh keberhasilan perusahaan McDonald dalam memberi “order’ kelompok
petani di Jawa Barat. Industri gula dan usaha tani tebu serta usaha tani padi
kini “sangat sakit” dengan jumlah dan nilai impor yang makin meningkat. Kondisi
swasembada beras yang pernah tercapai tahun 1984 kini berbalik. Dan pemerintah
mulai sangat gusar karena tanah-tanah sawah yang subur makin cepat beralih
fungsi menjadi permukiman, lokasi pabrik, gedung-gedung sekolah, bahkan
lapangan golf.
Jika kesejahteraan petani menjadi
sasaran pembaruan kebijakan pembangunan pertanian, mengapa kata pertanian kini
tidak banyak disebut-sebut? Mengapa Departemen Pertanian rupanya kini lebih
banyak mengurus agribusiness dan tidak lagi mengurus agriculture. Padahal
seperti juga di Amerika departemennya masih tetap bernama Department of
Agriculture bukan Department of Agribusiness? Doktor-doktor Ekonomi Pertanian
lulusan Amerika tanpa ragu-ragu sering mengatakan bahwa farming is business.
Benarkah farming (bertani) adalah bisnis? Jawab atas pertanyaan ini dapat ya
(di Amerika) tetapi di Indonesia bisa tidak.
Dari sudut pandang kelembagaan, struktur agribisnis di Indonesia untuk hampir semua
kornoditas
masih tersekat·sekat. Struktur yang
tersekat-sekat ini tentunya
menjadi
penghambat utama pembangunan
agribisnis di Indonesia.
Struktur agribisnis yang tersekat-sekat ini dicirikan oleh
beberapa hal
sebagai berikut : Pertama, subsistem
agribisnis hulu (produksi dan perdagangan sarana produksi pertanian)
dan subsistem agribisnis hilir (pengoIahan hasil pertanian dan
perdagangannya) dikuasai oleh pengusaha menengah dan besar
yang bukan
petani. Petani sepenuhnya hanya bergerak pada
subsistem
agribisnis penghasil produk primer. Kedua, antar subsistem
agribisnis
tidak ada hubungan organisasi fungsional dan hanya
diikat
oleh
hubungan pasar produk antara yang
juga
tidak
sepenuhnya
kompetitif. Ketiga, adanya asosiasi pengusaha yang bersifat
horizontal dan cenderung berfungsi sebagai kartel. Berbagai asosiasi
pengusaha ini dapat ditemui
pada
subsistem agribisnis hulu maupun
subsistem agribisnis hilir. Keempat,
agribisnis dilayani oleh paling
sedikit lima departcmen teknis (Pertanian, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi, Koperasi dan PPK). Berbagai departemen ini tentunya memiliki visi
ataupun
mandat yang berlainan, sehingga berbagai kebijakan
yang
ditujukan pada agribisnis belum tentu integratif dan selaras
satu dengan
lainnya
dipandang dari sudut agribisnis
sebagai
suatu sistem.
Struktur agribisnis yang
tersekat-sekat tersebut akan
menyulitkan
upaya pembangunan pertanian yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Porsi ekonomi petani yang
terbatas pada subsistent agribisnis usahatani rnenjadikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya relatif
keeil. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk
itu, yaitu: (a)
Dalam
sistem
agribisnis, nilai tambah yang terbesar berada
pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis
hilir. (b)
Petani berada
di an tara dua kekuatan eksploitasi ekonomi, yaitu
pada
pasar
sarana produksi petani monopsonistik. Petani dalarn menghadapi kedua pasar
tersebut selalu dalam posisi yang kalah. Keadaan
yang demikian ini me
nyebabkan upaynupava peningkatan produktivitas ditingkat petani
tidak secara otomatis berarti peningkatan pendapatan. Manfaat pengernbangan teknologi baru,
pengembangan infrastruktur pedesaan, subsidi
harga produksi, dan
subsidi melalui pcrkreditan yang
ditujukan untuk mcningkatkan produktivitas usahatani relatif sedikit manfaatnya pada petani.
Permasalahan struktural yang
dihadapi agribisnis tersebut juga berakibat pada
lernahnya daya
saing
agribisnis,
Struktur agribisnis
yang tersekatsekat dapat menciptakan masalah transrnisi dan masalah marjin
ganda. Masalah transmisi ini terjadi
dalarn berbagai bentuk, sepcrti rnisalnya transmisi harga
yang
tidak
sirnetris.
informasi perubahan preferensi konsumen yang
tidak
dapat
sampai dengan baik
ke arah
subsistem hulunya, serta
adanya
inkonsistensi mutu produk
sejak dari
hulu sampai
ke hilir dalam
sistem
agribisnis.
Lebih jauh lagi,
struktur yang
tersekat-sekat menjadikan inovasi berjalan lambat disetiap subsistem agribisnis. Sedangkan marjin ganda di agribisnis terjadi
melalui praktek
penetapan harga
yang
jauh
di atas harga pada
kondisi
kompetitifnya di setiap subsistem yang tersekat·sekat tersebut. Dampak nyata
dari
marjin
ganda
ini adalah harga pokok penjualan produk
akhir
agribisnis menjadi relatif tinggi, sehingga daya
saingnya menjadi rendah, Masalah transmisi dan masalah marjin ganda juga berdampak buruk
bagi investasi dibidang agribisnis, karena masalah tersebut dapat
menyebabkan naiknya resiko usaha.
Penataan
dan
pengembangan struktur agribisnis nasional perlu diarahkan pada dua sasaran
pokok, yaitu: Pertama, mengembangkan struktur agribisnis yang
terintegrasi secara
vertikal mengikuti aliran
produk, Struktur agribisnis yang
terintegrasi secara
vertikal ini memungkinkan subsistem agribisnis dari
hulu
sampai
hilir
dikelola dengs" efisien dan
saling mendukung satu
subsistem dengan subsistem lainnya. Intcrgrasi vertikal akan
memudahkan penerapan
sistem manajemen yang ditujukan pada
peningkatan daya saing
dan peningkatan kualitas. Kedua, mengembangkan organisasi bisnis pctani agar
mampu
mcmperoleh nilai tambah yang ada di subsistcm
hulu maupun
hilir
dari sistem ngribisnis. Secara individu petani akan sulit merebut nilai tambah
tcrsebut.
Keberhasilan pembangunan agribisnis di Indonesia ditentukan juga oleh
arah kebijakan ekonomi
makro. Pembangunan yang diarahkan pada industriahsasi yang t.iriak memiliki basis
sumbcrdaya yang kuat, seperti md ustri subst.itusi impor, sering
melahirkan kebijakan
kebijakan mnkro yang
mengharnbat perkembangan agribisnis.
Berbagai kebijakan ekonomi makro
diarahkan untuk
menopang industrtalisasi yang
kem
ud ian secara
langsung atau
tak
langsung
menyebabkan distorsi harga
yang
menghambat perkernbangan
agribisnis.
Kebijakan nilai tukar
Rupiah
yang secara
artifisial dibuat
kuat,
yaitu
sebelum Indonesia mengalarni krisis
moneter, merupakan salah
satu contoh bagaimana kebijakan ekonomi makro
dapat
menghambat
agribisnis. Nilai
tukar Rupiah yang dibuat kuat akan menguntungkan
industri-industri yang menggunakan bahan
baku
dari
irnpor
untuk
dipasarkan di pasar domestik. Sebaliknya bagi industri atau
sektor
yang menggunakan bahan
baku domestik dan diarahkan untuk
pasar
ekspor, kuatnya nilai
tukar
mata
uang
dapat
menyebabkan daya saingnya melemah, Agribisnis pada
dasarnya menggunakan bahan
baku yang berasal dari
dalam
negeri
dan
banyak
produknya yang dimaksudkan juga untuk
melayani pasar
internasional, sehingga nilai
tukar Rupiah yang
secara artifisial dibuat kuat
merugikan
pembangunan agribisnis,
Kebijakan tarn
yang tinggi untuk memberikan proteksi pada industri
yang bersifat substitusi impor ternyata memberikan dampak juga pada perkembangan agribisnis. Proteksi yang
berlebihan yang
diberikan
pada industri-industri tertentu dapat
menyebabkan distorsi dalam
alokasi sumberdaya. Industri-industri yang memperoleh proteksi
menjadi tampak lebih
menarik di mata
investor, sedangkan industri
yang termasuk ke dalam
agribisnis dianggap kurang
menguntungkan,
dan juga berusaha di bidang agribisnis dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi. Akibatnya, sumberdaya kemudian lebih banyak
mengahr
ke industri-industri yang memperoleh proteksi dan
bidang
usaha
agribisnis yang memiliki basis
kuat
sebaliknya mengalami kesulitan
memperoleh modal
untuk investasi ataupun usaha. Kebijakan industrialisasi
berspektrum luas
ataupun industrialisasi substitusi irnpor
yang selarna
ini diterapkan
menimbulkan struktur insentif yang diskrim inasi
yang merugikan pernbangunan agribisnis dan
pertanian pe nghasil produk
primer.
Kebijakan ckonomi makro
yang
diarahkan untuk menopang industrialisasi yang dilakukan tcrnyata tidak
saja herdampak negatif
bagi porkembangan agribisnis, melainkan
juga
berdampak pada menguatnya ketimpangan pembangunan perkotaan dan
pedcsaan. Berbagai infrastruktur yang
dibangun lcbih
diarahkan untuk menopang strategi industr-ialisnsi yang
ditujukan untuk
substitusi impor. ludustri-industri ini um um nya
bcrlokasi di perkotaan atau daerah sekitar perkotaan. Berbagai sarana dan
prasarana transportasi dan
telekomunikasi dibangun untuk
memperlancar dan memporrnudah jalannya bisnis industri ini.
Akibatnya, perkembangan fasilitas publik
di perkotaan jauh melarnpaui ya ng
dibangun untuk daerah pedcsaan.
Kebijakan industrialisasi yang bersifat spektrum luas
maupun industri substitusi impor umumnya bertumpu pada upah
tenaga
kerja yang murah. Upah
tcnaga kerja
ini
sering dikaitkan dengan kebutuhan hid up
minimum. Dengan
demikian agar upah
dapat
tetap rendah, maka
harga-harga berbagai kebutuhan pokok (pangan) harus dijaga tetap rendah. Keadaan ini tentu
membuat
pembangunan yang dilakukan semakin bias ke perkotaan dan mendiskriminasi pedesaan dan agribisnis.
....Bersambung...
PERUBAHAN PARADIGMA PERTANIAN AGRIBISNIS MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN (TINJAUAN SECARA FILSAFAT ILMU DI INDONESIA) Bagian I 16 Sep 2024 7:26 PM (7 months ago)

Seiring perkembangan dan kemajuan ilmu dalam pembangunan pertanian mengalami beberapa
proses kemajuan. Filsafat ilmu dalam pertanian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, hewan, dan ikan serta lingkungannya agar memberikan hasil secara maksimal. Berdasarkan spesifikasinya ilmu pertanian dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu ilmu tanaman yang mempelajari khusus tanaman, ilmu peternakan yang mempelajari khusus ternak, dan ilmu perikanan yang mempelajari khusus ikan dan hewan air. Pertanian dimulai pada saat manusia mulai mengamati perilaku tanaman, hewan, dan ikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.
Paradigma pertanian subsisten yang awalnya hanya
merupakan pertanian yang dilaksanakan dengan pendekatan komoditas (Kasrino dan
Suryana, 1992). Pendekatan ini dicirikan oleh pelaksanaan pembangunan
berdasarkan pengembangan komoditas secara sendiri-sendiri (parsial )
dan berorentasi pada peningkatan produksi. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa pembangunan
sektor pertanian selama ini memberikan hasil yang sangat menakjubkan,
terutama dalam memacu pertumbuhan produksi yang dibuktikan dengan tercapainya
swasembada beras. Keberhasilan program peningkatan produksi pertanian
terutama beras, kelapa sawit, kakao,udang, ayam buras dan
pedaging serta telur antara lain disebabkan oleh: keadaan pasar berbagai
komoditas tersebut dalam situasi exees
demond, dukungan paket teknologi maju, sumber daya alam yang
tersedia, sumber dana tersedia dengantingkat bunga disubsidi dan dana untuk
investasi prasarana dan sarana ekonomi oleh pemerintah dan komitmen
pemerintah.
Namun pendekatan komoditi untuk
masa yang akan datang kurang memadai lagi, karena adanya indikasi:
kejenuhan atau keterbatasan pengembangan pasar (permintaan), keterbatasan ketersediaan
sumber pertanian, dan investasi dan mulaimelandainya kenaikan produktivitas.
Oleh karena itu diperlukan reorentasi pembangunan pertanian dimasa
mendatang. Hal ini diperkuat lagi dengan pelaksanaan desentralisasi dan
pemerataan pembangunan berkelanjutan yang lebih dimatangkan.
Berdasarkan uraian di atas, komoditas sudah tidak lagi cocok
diterapkan dalam pembangunan pertanian selama ini, hal ini merupakan konsekuensi logis masuknya globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan
international yang sangat ketat dan bebas. Perekonomian nasional akan
semakin diregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan hargadan berbagai
prestasi lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang
efisienmerupakan pijakan utana bagi kelangsungan hidup usahatani. Sehubungan
dengan itu partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan kunci
keberhasilan pembangunanpertanian. Disamping itu usahatani dan petani
semakin tergantung dengan usaha lainnyamaupun dengan berbagai kegiatan ekonomi
lainnya. Dengan kata lain persaingan dengan berbagai komoditas terhadap
penggunaan sumberdaya pertanian akan semakin tinggi.
Pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi
untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu,
pertanian/agrikultur adalah sebuah cara hidup (way of life atau livehood)
bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai
sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani, sebagai pelaku
sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus,
melainkan juga sebagai homo socius dan homo religius.
Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya
lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan
budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian.
Paradigma agribisnis yang dikembangkan oleh Davies dan Goldberg, yang berdasar
pada lima premis dasar agribisnis.
Pertama, adalah suatu kebenaran umum bahwa semua usaha pertanian
berorientasi laba (profit oriented), termasuk di Indonesia. Kedua,
pertanian adalah komponen rantai dalam sistem komoditi, sehingga kinerjanya
ditentukan oleh kinerja sistem komoditi secara keseluruhan. Ketiga, pendekatan
sistem agribisnis adalah formulasi kebijakan sektor pertanian yang logis, dan
harus dianggap sebagai alasan ilmiah yang positif, bukan ideologis dan
normatif. Keempat, Sistem agribisnis secara intrinsik netral terhadap semua
skala usaha, dan kelima, pendekatan sistem agribisnis khususnya ditujukan untuk
negara sedang berkembang. Rumusan inilah yang nampaknya digunakan sebagai
konsep pembangunan pertanian dari Departemen Pertanian, yang dituangkan dalam
visi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan
usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan
terdesentralisasi.
Sejarah
Perkembangan Pertanian
Berdasarkan sejarah perkembangannya pertanian dapat
diklasifikasikan menjadi 4 golongan yaitu :
1.
Pemburu dan pengumpul. Manusia pertama hidup di daerah hutan tropik di
sekitar laut Cina Selatan yaitu bangsa Alitik (prapaleolitik) yang merupakan
kelompok manusia pengumpul makanan dan berburu serta menangkap ikan. Sebagai
contohnya adalah suku Semang, suku Kubu dan Sakad di Semenanjung Malaya, Sukum
Andaman dan Aeta di Filiphina, suku Toala di Sulawesi, suku Punan di Kalimantan
dan suku Tasadai di Mindanau Selatan. Manusia pengumpul dan pemburu bersifat
nomadik (berpindah-pindah) tetapi tidaklah mengembara tanpa tujuan di dalam
hutan. Setiap kelompok mempunyai wilayah tertentu antara 20-25 Km2 . Mereka
bertempat tinggal di goa-goa atau tebing batu. Mereka juga telah banyak
mengetahui jenis-jenis tanaman dan habitatnya serta kegunaannya. Pengetahuan
untuk menghilangkan racun dari bahan makanan dan cara mengawetkannya juga sudah
mereka kuasai. Sebagai contoh biji sebelum dimakan direndam dalam air kemudian
dimasukkan ke dalam bambu dan dibenamkan ke dlaam tanah selama sebulan lebih.
2.
Pertanian Primitif .Ketika manusia pengumpul dan berburu mulai berusaha
menjaga bahan makanan maka mulai terjadi suatu mata rantai antara periode
pengumpul dan berburu dengan pertanian primitif. Orang-orang Semang yang suka
makan buah durian akan tinggal di dekat pohon durian untuk mencegah monyet dan
binatang-binatang lain menghabiskan buah durian. Mereka juga menanam kembali
batang dan sulur umbi liar yang umbinya telah mereka ambil, sehingga dapat
tumbuh kembali. Tindakan ini adalah satu langkah menuju pertanian primitif. Setelah
berabad-abad lamanya wanita mendapatkan pengetahuan yang baik tentang kehidupan
tumbuh-tumbuhan. Edward Han dan beberapa sarjana lainnya menganggap wanita
adalah penemu cara penanaman dan penghasil bahan makanan yang pertama. Han
menamai pertanian primitif sebagai Hackbau (Hoe
Culture atau Hoe Tillage = pertanian pacul atau pertanian bajak). Dia
menganggap pacul adalah alat kerja wanita, sedangkan bajak alat kerja pria. Teori
Han yang pertama menyatakan wanita adalah yang pertama memulai penanaman
mungkin dapat diterima tetapi pendapatnya tentang perbedaan antara pertanian
primitif dan pertanian yang lebih maju berdasarkan alat kerja yang digunakan
apalagi dihubungkan dengan jenis kelamin tidaklah dapat diterima meskipun di
beberapa daerah atau negara banyak wanita yang bekerja sebagai petani.
Perbedaan yang fundamental antara pertanian primtif dengan pertanian yang lebih
maju adalah dalam hal penggunaan lahan. Petani-petani primitif, bertani secara
berpindah-pindah. Sebidang tanah ditanami sekali sampai 2 kali kemudian
ditinggalkan dan mereka mencari tanah baru untuk ditanami dan seterusnya.
Sehingga sistem pertanian ini disebut huma atau ladang berpindah.
3.
PertanianTradisional
Pada pertanian tradisional orang menerima keadaan tanah, curah hujan, dan
varietas tanaman sebagaimana adanya dan sebagaimana yang diberikan alam.
Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya sekedarnya sampai tingkat tertentu
seperti pengairan, penyiangan, dan melindungi tanaman dari gangguan binatang
liar dengan cara yang diturunkan oleh nenek moyangnya.
Peternakan merupakan penjinakan hewan-hewan liar untuk digunakan tenaga dan
hasilnya. Sedangkan perikanan merupakan hasil penangkapan dan pemeliharaan
secara sederhana serta tergantung pada kondisi alam.
4.
Pertanian Progresif (Modern). Manusia mengguanakan otaknya untuk
meningkatkan penguasaannya terhadap semua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman
dan hewan. Usaha pertanian merupakan usaha yang efisien, masalah-masalah
pertanian dihadapi secara ilmiah melalui penelitian-penelitian, fasilitas-fasilitas
irigasi dan drainase dibangun dan dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang
maksimum, pemuliaan tanaman dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul yang
berproduksi tinggi, respon terhadap pemupukan, tahan terhadap serangan hama dan
penyakit serta masak lebih cepat. Susunan makanan ternak disiapkan secara
ilmiah dan dikembangkan metode berbagai macam input dilakukan secara ilmiah dan
didorong motivasi ekonomi untuk mendapatkan hasil dan pendapatan yang lebih
besar. Hasil pertanian dalam bentuk bulk (lumbung) diolah untuk mendapatkan
harga yang lebih tinggi. Cara pengawetan hasil pertanian dikembangkan untuk
menghindarkan kerusakan dan mendapatkan nilai yang tinggi.
Konversi Gabah Menjadi Beras BPS 2018 3 Sep 2024 11:50 PM (7 months ago)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya penyediaan pangan yang memadai
merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan manusia yang berkualitas.
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, bahwa ketahanan
pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Prioritas
nasional ketahanan pangan tersebut diuraikan menjadi program prioritas
peningkatan produksi pangan, serta program prioritas pembangunan sarana dan
prasarana pertanian. Salah satu kegiatan dalam program prioritas pembangunan
sarana dan prasarana pertanian adalah kegiatan perbaikan data statistik pangan.
Ketersediaan data statistik pangan yang berkualitas sebagai
rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi sangat menentukan
karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.
Statistik produksi padi, salah satu statistik pangan paling strategis dan
penting, diperoleh dari data luas panen dikali dengan data produktivitas
dikalikan dengan angka konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling
(GKG).
Selain data produksi padi, data yang diperlukan pemerintah
dalam perumusan kebijakan pangan adalah produksi dalam bentuk beras.
Penghitungan produksi beras dilakukan dengan menggunakan angka konversi GKG ke
beras.
Pengeringan gabah merupakan salah satu kegiatan pascapanen
yang penting. Proses ini merupakan proses penurunan kadar air gabah hasil panen
atau disebut Gabah Kering Panen (GKP) menjadi kualitas Gabah Kering Giling
(GKG). Di samping itu, proses pengeringan juga dilakukan untuk mengurangi kadar
hampa dan kotoran yang terdapat dalam gabah hasil panen (GKP). Umumnya, standar
kadar air kualitas GKP adalah sekitar 25 persen, dan kadar air kualitas GKG
sekitar 14 persen (Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015).
Pengurangan kadar air dalam bijian seperti gabah dilakukan
dengan cara penguapan air dari dalam gabah. Proses ini meliputi penguapan air
dari permukaan biji dan perpindahan massa air dari dalam gabah ke permukaan
secara difusi.
Pengeringan gabah hasil panen diperlukan untuk mengurangi
kadar air sehingga memenuhi standar baik untuk disimpan ataupun untuk digiling
menjadi beras. Selama proses pengeringan dilakukan akan terjadi penurunan berat
gabah karena pengurangan kadar air dalam gabah dan juga kemungkinan terjadinya
kehilangan gabah secara fisik (susut pengeringan) seperti tercecer atau dimakan
ternak/ungags.
Penggilingan adalah proses pengolahan Gabah Kering Giling
(GKG) menjadi beras. Angka konversi GKG ke beras merupakan persentase berat
beras hasil penggilingan terhadap berat gabah (GKG) yang digiling. Pengukuran
angka konversi GKG ke beras dilakukan di penggilingan padi yang dikelola oleh
masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum.
Konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling
(GKG)
Angka konversi dari GKP ke GKG dinyatakan dalam satuan
persen. Angka ini menunjukkan persentase banyaknya GKG (Gabah Kering Giling)
yang diperoleh setelah melalui proses pengeringan GKP (Gabah Kering Panen).
Angka konversi pengeringan gabah dari GKP ke GKG hasil Survei Konversi Gabah ke
Beras tahun 2018 secara nasional sebesar 83,38 persen. Jika dibandingkan
dengan tahun 2005-2007 (86,02 persen), terjadi penurunan sebesar 2,64 poin.
Gambar. Perkembangan Angka Konversi GKP ke GKG (Persen),
2005- 2007, 2012, dan 2018
Konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras
Nilai rendemen merupakan angka konversi dari GKG ke beras.
Semakin tinggi nilai rendemen menunjukkan bahwa semakin sedikit GKG yang
mengalami penyusutanSecara nasional, angka konversi GKG ke beras berdasarkan
hasil Survei Konversi Gabah ke Beras Tahun 2018 adalah sebesar 64,02 persen.
Angka ini meningkat sebesar 1,17 persen dibanding hasil survei tahun 2012, dan
meningkat sebesar 1,28 persen dibanding hasil survei tahun 2005-2007.
Gambar. Perkembangan Angka Konversi GKG ke Beras berdasarkan
Hasil Survei Tahun 2005-2007, 2012, dan 2018
Secara terperinci berikut konversi GKP, ke GKG dan GKG ke
Beras secara Nasional berdasarkan hasil survey BPS tahun 2018.
|
No |
Uraian |
Jumlah % |
Faktor Pengurang |
|
1 |
Jumlah GKP |
100% |
|
|
2 |
Konversi GKP
ke GKG |
83,38% |
(Susut Kadar
Air) |
|
3 |
Konversi GKG
ke GKG untuk Diolah |
92,70% (dari
Angka 2) |
(Susut dan
Penggunaan lain) |
|
|
- Penggunaan
Benih |
0,90% |
|
|
|
- Tercecer
|
5,40% |
|
|
|
- Pakan
ternak |
0.44% |
|
|
|
- Bahan
industri |
0,56% |
|
|
4 |
Konversi GKG
ke GKG untuk Diolah Ke Beras |
62,02% (dari
Angka 3) |
|
|
5 |
Konversi Beras
untuk Beras Siap Konsumsi |
96,67% (dari
Angka 4) |
(Susut dan
Penggunaan lain) |
|
|
- Tercecer
|
2,50% |
|
|
|
- Pakan
ternak |
0.17% |
|
|
|
- Bahan
industri |
0,66% |
|
Sumber data : SKGB 2018 Konversi Gabah Ke Beras BPS 2018.
PELANGGARAN INDIKASI GEOGRAFIS BERAS PANDANWANGI CIANJUR DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM 3 Sep 2024 6:16 PM (7 months ago)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri adalah kekayaan yang tidak berwujud yang berasal dari hasil olah pikir dan kreativitas manusia.
Tidak kalah
penting dengan kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan, kekayaan
intelektual dengan kepemilikan bersama oleh kelompok masyarakat menjadi aset
yang sangat berharga untuk memajukan perekonomian bangsa. Kekayaan ini dimiliki
oleh masyarakat umum dan bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal
meliputi indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan
ekspresi budaya tradisional. Kekayaan intelektual komunal mengupayakan
kemanfaatan dan kepentingan bagi banyak orang. Keuntungan kolektif inilah yang
menjadi ciri khas. Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya bangsa Indonesia
yang sangat kaya ragam menjadi potensi yang sangat besar akan kekayaan
intelektual yang bersifat komunal.
Sebagai salah
satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kondisi geografis
yang beragam, adat istiadat berwarna, serta sumber daya budaya, termasuk
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang kaya. Kondisi
geografis dan keragaman adat dan budaya menjadi potensi penting dalam proses
produksi berkarakter khas.
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka
6 (selanjutnya disebut UU Merek dan
Indikasi Geografis), Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor
tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang
dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang
digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang
dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama
tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut.
Indikasi
geografis digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu dan
memiliki kualitas terkait dengan asal dimana barang tersebut berasal. Secara
umum, indikasi geografis merupakan nama produk yang diikuti nama wilayah atau
tempat asal
Indonesia
menerapkan sistem penghindaran passing off dalam regulasi indikasi
geografisnya. Indonesia mengintegrasikan secara inklusif pengaturan indikasi
geografis dengan sistem merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, terdapat peraturan sebelumnya yang
juga terkait dengan pengaturan indikasi geografis yaitu Undang-Undang Nomor 15
tahun 2001 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Dapat dikatakan bahwa pelanggara atas
indikasi geografis masuk dalam ranah hukum perdata. Sehingga apabila terjadi
Tindakan atau pelanggaran atas hal tersebut dapat dimintakan ganti rugi atau
kompensasi. Pasal ini kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat.
Indikasi
Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal
barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak
yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila
penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah
asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan
demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi
Geografis.
Perlindungan
Indikasi Geografis menyasar berbagai tujuan, selain memberi proteksi terhadap
potensi khas daerah dari peniruan atau penggunaan secara melawan hukum, juga
dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat
penghasilnya, sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen karena adanya
jaminan kualitas produk. Pada sisi konsumen, terdapat jaminan keaslian produk
melalui label Indikasi Geografis yang ditempelkan pada produk sebagai penanda
bahwa produk tersebut asli. Indikasi Geografis
mencerminkan keterhubungan antara produk dan wilayah, yang jika dilindungi oleh
undang-undang mencegah penyalahgunaan atau peniruan nama terdaftar dan menjamin
konsumen bahwa produk tersebut asli.
Hak Indikasi
Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan
sebuah hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Indikasi Geografis yang
terdaftar. Hak eksklusif
ini berasal dari Negara dan diberikan selama reputasi, kualitas, dan
karakteristik khas Indikasi Geografis masih melekat. Disebut eksklusif karena
secara limitatif hanya melekat pada kelompok masyarakat atau pihak yang
berkepentingan (interested parties) sebagai perwakilan masyarakat daerah
Indikasi Geografis dan hanya kelompok tersebut yang berhak untuk memperoleh
semua kemanfaatan ekonomi dari Hak Indikasi Geografis tersebut. Hak eksklusif
yang dimiliki oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis meliputi pemanfaatan,
penggunaan, serta upaya hukum terhadap pelanggar Indikasi Geografis oleh pihak
yang tidak berhak memanfaatkan. Pemberian label Indikasi Geografis diharapkan
dapat menghindarkan dan melindungi produsen maupun konsumen terhadap pemalsuan
suatu produk, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Indikasi
Geografis memiliki kedudukan strategis karena menjadi potensi modal dasar bagi
pembangunan nasional. Indikasi Geografis adalah indikator kualitas karena
menjadi tanda daerah asal barang atau produk kepada konsumen. Perlindungan
Indikasi Geografis memberikan manfaat yang sangat besar, berupa:
1) Memberi proteksi terhadap produk dan
produsen Indikasi Geografis dari kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda
Indikasi Geografis
2) Menerangkan identifikasi produk dan
berperan sebagai standar produksi dan proses bagi para pemangku kepentingan
Indikasi Geografis
3) Mencegah adanya persaingan usaha
tidak sehat dan melindungi konsumen dari penggunaan reputasi Indikasi Geografis
secara salah
4) Meningkatkan pendapatan ekonomi
pelaku usaha
5) Memberikan informasi tentang jenis,
kualitas, dan asal produk yang dibeli kepada konsumen
6) Menjadi sarana promosi dan kesempatan
meraih reputasi yang lebih baik
7) Meningkatkan posisi tawar untuk
berkompetisi pada pasar nasional maupun internasional
8) Mengangkat reputasi kawasan Indikasi
Geografis melalui pengembangan agrowisata
Saat ini,
berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdapat 162
Indikasi Geografis Terdaftar. Setidaknya sebanyak 15 Indikasi Geografis berasal
dari luar negeri. Sebanyak Produk Indikasi Geografis berasal dari Jawa
Barat diantaranya ;
1) Kopi Robusta Java Bogor,
2) Kopi Arabika Java Preanger Sukabumi,
3) Teh Java Preanger Bandung,
4) Beras Pandanwangi Cianjur,
5) Kopi Robusta Java Sanggabuana
Karawang,
6) Ubi Cilembu Sumedang,
7) Tembakau Hitam Sumedang,
8) Tembakau Mole Sumedang,
9) Sawo Sukatali Sumedang.
Meskipun
telah terdapat pengaturan, kasus-kasus pelanggaraan Indikasi Geografis yang
berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen bermunculan. Diperlukan upaya
perlindungan hukum yang dapat melindungi kepentingan hak pemegang Indikasi
Geografis maupun konsumen.
Perlindungan
Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan
atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan
perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan
manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan
Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan
kualitas produk. Oleh karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat
perlindungan hukum yang memadai.
Pelanggaran
atas Indikasi Geografis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Merek dan
Indikasi Geografis dapat berupa:
a) pemakaian Indikasi Geografis, baik
secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak
memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
b) pemakaian suatu tanda Indikasi
Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau
produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
1) menunjukkan bahwa barang dan/atau
produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang
dilindungi oleh Indikasi Geografis;
2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian
tersebut; atau
3) mendapatkan keuntungan atas reputasi
Indikasi Geografis
c) pemakaian Indikasi Geografis yang
dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
d) pemakaian Indikasi Geografis oleh
bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
e) peniruan atau penyalahgunaan yang
dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau
kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
1) pembungkus atau kemasan;
2) keterangan dalam iklan;
3) keterangan dalam dokumen mengenai
barang dan/atau produk tersebut; atau
4) informasi yang dapat menyesatkan
mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
f)
tindakan
lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang
dan/atau produk tersebut
Salah satu
contoh adalah Beras Cianjur yang diberi merek Beras Pandanwangi Cianjur. Beras Cianjur sudah dikenal oleh banyak orang
di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan citarasanya yang
khas. Beras Cianjur memperoleh tempat dihati konsumen sebagai beras yang
bermutu baik. Diantara berbagai jenis beras Cianjur, yang paling terkenal
adalah Beras Pandanwangi hasil dari tanaman padi varietas Pandanwangi.
Pandanwangi merupakan varietas padi unggul lokal kabupaten Cianjur yang
termasuk jenis padi bulu.
Keunggulan
Beras Pandanwangi Cianjur adalah rasanya yang enak, pulen dan beroma khas
pandan. Untuk menghasilkan Beras Pandanwangi Cianjur yang bercitarasa khas,
padi varietas Pandanwangi hanya dapat ditanam di tujuh kecamatan di kabupaten
Cianjur, yaitu Warungkondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Cibeber, dan
Campaka. Apabila varietas padi Pandanwangi ditanam diluar ketujuh kecamatan
tersebut atau di daerah lain, maka kekhasan berasnya akan hilang terutama
tekstur pulen dan aroma pandannya. Produksi Beras Pandanwangi Cianjur yang
terbatas, tetapi banyak diminati konsumen, berdampak pada perilaku perdagangan
yang tidak sehat. Banyak pedagang beras menyebut berasnya sebagai Beras
Pandanwangi Cianjur tetapi sebenanrnya beras tersebut bukanlah Beras Pandanwangi
Cianjur, melainkan beras hasil pencampuran/ pengoplosan dengan Beras
Pandanwangi Cianjur, atau bahkan bukan Beras Pandanwangi Cianjur.
Beras
Pandanwangi Cianjur yang palsu banyak beredar dipasaran, baik pasaran nasional
maupun internasional. Hal tersebut sangat merugikan petani padi Pandanwangi
Cianjur. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum agar tercipta
perdagangan yang sehat dan berkeadilan.
Pendaftaran
Beras Pandanwangi Cianjur untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis
bertujuan untuk dapat menciptakan perdagangan beras yang sehat, memberikan
perlindungan kepada produsen dan konsumen, dan pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan petani padi Pandanwangi Cianjur. Beras Pandanwangi Cianjur
merupakan Produk Indikasi Geografis yang telah mendapatkan Sertifikat Indikasi
Geografis Beras Pandanwangi Cianjur dengan nomor ID G 000000034. Bahkan diperjualbelikan juga di tanpa menyebut
Indikasi Geografis yang dilindungi tersebut.
Beras
Pandanwangi merupakan beras yang sangat terkenal di Indonesia yang berasal dari
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat karena nasinya yang beraroma pandan, enak rasanya
dan pulen teksturnya. Benih Pandanwangi ditetapkan sebagai benih
varietas lokal Kabupaten Cianjur melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
163/Kpts/LB.240/3/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Kepedulian Pemerintah
Kabupaten Cianjur terhadap Padi Pandangwangi telah diwujudkan dengan terbitnya
Perda No. 19 Tahun 2012 tentang pelestarian dan
perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur.
Beras Pandanwangi telah terdaftar Indikasi
Geografis nomor ID
G 000000034. pada tanggal 16 September 2018 melalui
Masyarakat Pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai Masyarakat
Pemegang Hak IG (MPIG) Merek dan
Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan
usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.
Konsumen Beras Pandanwangi adalah masyarakat menengah ke atas karena harga yang mahal.
Harga yang mahal ini, memunculkan oknum pedagang memanipulasi beras pendanwangi supaya dapat menjual dengan harga lebih murah. Hal ini menurunkan
motivasi petani padi pandanwangi murni untuk tetap menanam padi varietas
pandanwangi. Selain itu jumlah petani pembudidaya padi pandanwangi dan luas
pertanaman kian tahun semakin menurun.
Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa permasalahan yang terkait
dengan produk Indikasi Geografis Beras Pandanwangi
Cianjur perlu dilakukan studi mendalam
untuk mengetahui sejuahmana peran MPIG dan pemerintah daerah Cianjur dalam menjaga
kualitas produk IG pasca terdaftar .
Bahan Pustaka
1) Gusti Ayu Putu Eka Agustina, Taufik
Yahya. Perlindungan
Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan. Hagoluan Law Review. Volume 1 Nomor 2 Nopember 2022
2) Yoan Nursari Simanjuntak. Pelanggaran Indikasi Geografis
ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen. Perspektif Hukum. Fakultas Hukum,
Universitas Surabaya. Vol
23 Issue 1: 58-81.
3)
Tatty A. Ramli, dan Yeti Sumiyati. Penyuluhan tentang
perlindungan hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat
sebagai wujud sumbangsih perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). FH UNISBA. Jurnal Hukum dan Pembangunan Talum le-4J. 0.3
Mi-September 2012
4)
M. Rendi Aridhayandi. Focus Group Discussion mengenai pemahaman perubahan aturan hukum
indikasi geografis bagi Masyarakat Pelestarian
Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sebagai Masyarakat Pemegang Hak Indikasi
Gegrafis terdaftar. JOURNAL OF EMPOWERMENT. UNPAR Bandung . Desember 2017.
5) Masyarakat Pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur
(MP3C). Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras
Pandanwangi Cianjur. Cianjur. Juli 2015
https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing
Ilmu-ilmu Pertanian Sebagai Ilmu Empirik 26 Sep 2023 5:26 PM (last year)

Dalam usaha bercocoktanam serta pemeliharaan hewan, manusia mengumpulkan berbagai pengalaman.
Salah satu pengalaman pertama manusia mengenai bercocoktanam yang tercatat dalam sejarah ialah mengenai ditemukannya pengetahuan tentang perkembangbiakan pohon kurma yang terjadi secara seksual. Pada zaman peradaban Babilonia telah diketahui bahwa satu pohon kurma tidak dapat berkembangbiak tanpa adanya pohon kurma lain yang berlainan jenis kelaminnya. Bagaimana caranya mereka mengetahui hal itu? Mungkin sekali dari pengalaman para petani menyingkirkan semua pohon kurma yang mandul dan tidak menghasilkan kurma, karena dianggap mubazir untuk dipelihara. Ternyata setelah semua pohon itu di¬singkirkan, pohon lainnya pun tidak mampu berproduksi, karena pohon yang tadinya menghasilkan kurma itu adalah pohon betina dan pohon yang disingkirkan itu adalah pohon jantan. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah terjadi pada zaman Babilonia (Ronan, 1982).
Tampaklah bahwa pengetahuan
muncul karena penga¬laman. Bahwa dalam pengembangan pengetahuan pengalaman itu
diperlukan untuk mendukung atau menolak kebenaran suatu pendapat tercatat dalam
sejarah dalam bentuk suatu hadis yang sahih (Muslim, Kitab 43 Bab 38, Hadis
140-141):
Melihat orang-orang yang sedang
menyerbuki bunga kurma, Nabi bertanya: “Apa yang sedang kamu perbuat?” Setelah
diberi¬tahu apa yang mereka kerjakan, Nabi berkata lagi: “Barangkali lebih baik
jika tidak kamu lakukan itu.” Setelah ternyata kemu¬dian buah kurma itu
berguguran dan Nabi diberitahu, Nabi berkata: “Aku hanya seorang manusia. Jika
perintahku mengenai agama, ikutilah. Kalau yang kuperintahkan mengenai sesuatu
itu dari pendapatku sendiri, aku hanya seorang manusia juga.”
Dalam peristiwa yang sama tetapi
sedikit berbeda redaksi-nya, Nabi berkata (Ibn Majah IV:1259, Hadis 5830-5832):
“Kamu lebih mengetahui soal duniamu.”
Hikmah yang dapat diperoleh dari
kedua hadis ini ialah bahwa pendapat seseorang itu gugur kalau kenyataan yang
diamati tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Dari pola berpikir ini muncullah
ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman atau empirisme (Yunani: empeira –
pengalaman). Ilmu pengetahuan empirik ini pada mulanya adalah buah pikiran Ibnu
Khaldun dan kemudian diserap menjadi milik orang Eropa dalam Zaman Kebangkitan
Eropa serta dikembangkan menjadi tulang punggung sains modern oleh Francis
Bacon.
Dalam bidang kegiatan pertanian
juga banyak sekali pengetahuan yang telah dikumpulkan berdasarkan pengalaman
dalam perjalanan sejarah. Pengalaman-pengalaman itu kemudian dihimpun menjadi
sekumpulan ilmu terapan yang dinamakan ilmu-ilmu pertanian. Salah suatu ciri ilmu
terapan ialah bahwa semua yang terdapat dalam ilmu itu akhirnya dapat
diterangkan dengan menggunakan ilmu dasar. Dalam hal ilmu-ilmu pertanian, semua
peristiwa yang menyangkut pengetahuan tentang alam dapat diterangkan oleh
biologi, dan semua peristiwa biologi dapat diterangkan oleh ilmu kimia yang
akhirnya dapat pula diterangkan dengan menggunakan ilmu fisika. Dalam hal ilmu
pertanian yang berkaitan dengan perilaku manusia, semuanya dapat diterangkan
oleh ilmu ekonomi dan ilmu sosial.
Apa yang dimaksudkan dengan
ilmu-ilmu pertanian itu. Agar barangsiapa yang ingin mempelajarinya dapat
memperoleh suatu gambaran menyeluruh mengenai ilmu-ilmu tersebut. Karena
ilmu-ilmu tersebut menyangkut permasalahan yang luas dan saling berhubungan,
tidak mungkin bagi orang yang ingin mempelajarinya untuk memahami semua
aspek-aspeknya. Pada akhirnya ia harus mengambil keputusan bagian ilmu-ilmu
pertanian yang mana yang akan dijadikannya menjadi keahliannya. Selain itu pula
mungkin sekali yang menjadi minatnya akhirnya bukanlah ilmu-ilmu pertaniannya
sendiri melainkan ilmu-ilmu dasar yang mendukung pengembangan ilmu-ilmu
pertanian itu sebagai ilmu terapan.
Usaha pertanian pada dasarnya
bersandar pada kegiatan menyadap energi surya agar menjadi energi kimia melalui
peristiwa fotosintesis. Hasil fotosintesis ini kemudian menjadi bagian tumbuhan
dan hewan yang dapat dijadikan manusia sebagai bahan makanan, bahan sandang dan
papan, sumber energi, dan bahan baku industri. Untuk dapat menghasilkan
bahan-bahan organik itu tumbuhan dan hewan harus dapat hidup di dalam suatu
lingkungan yang terdiri atas tanah, air, dan udara pada suatu iklim yang
sesuai. Karena itu ilmu-ilmu pertanian mencakup ilmu tanah, ilmu tataair, dan
ilmu cuaca dan iklim yang tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu lingkungan
kehidupan dan budidaya.
Tumbuhan yang dipelihara manusia
dengan sengaja agar dapat memberikan manfaat kita namakan tanaman, sedangkan
hewan yang dipelihara untuk hal yang sama kita sebut ternak. Setelah lingkungan
kehidupan dan budidaya yang sesuai untuk tanaman dan ternak tersedia, segala
usaha pertanian belum dapat berjalan dengan baik tanpa adanya ilmu-ilmu yang
memecahkan persoalan pembudi-dayaannya. Ilmu-ilmu yang termasuk dalam kelompok
budi-daya ini ialah ilmu budidaya tanaman atau agronomi, hortikultura yang menyangkut
budi-daya sayuran, buah-buahan, dan tanaman-hias, budidaya hutan, ilmu
budi-daya ternak, ilmu budidaya perairan, proteksi tanaman, kedokteran hewan,
keteknikan kelautan dan keteknikan pertanian.
Sebagian hasil usaha pertanian
digunakan langsung sebagai makanan manusia atau pangan dan makanan ternak atau
pakan. Penggunaannya sudah tentu haruslah dengan menganut azas manfaat. Karena
itu dipandang dari segi kepentingan manusia harus diketahui cara menyajikan
makanan yang baik dari segi kebersihan, kesehatan, dan dayabeli masyarakat.
Itulah sebabnya ilmu-ilmu pertanian juga mencakup ilmu gizi masyarakat dan
sumberdaya keluarga, sedangkan untuk permasalahan pakan diperlukan juga suatu
ilmu yang berkenaan dengan hal itu dan disebut ilmu makanan ternak atau ilmu
pakan. Hasil usaha pertanian itu sebagian juga tidak digunakan secara langsung
tetapi diubah bentuknya sehingga lebih tahan lama atau lebih mudah dicerna.
Untuk hal itu ilmu-ilmu pertanian juga mencakup teknologi pangan dan gizi,
serta bioteknologi. Bioteknologi ini dapat dipelajari sebagai bagian teknologi
pangan dan gizi atau juga sebagai bagian dari biologi, yaitu di dalam
mikrobiologi.
Penggerak usaha pertanian adalah manusia. Karena itu kelancaran usaha pertanian sangat bergantung pada sikap dan perilaku manusia penggeraknya. Perilaku dan sikap manusia ini ditentukan oleh sikapnya dalam mencari nafkah bagi kehidupannya yang dibahas dalam ilmu ekonomi pertanian. Selain itu sikap hidup ini juga tergantung sekali pada caranya bermasyarakat. Oleh karena itu ilmu-ilmu pertanian juga mencakup sosiologi pedesaan. Permasalahan penting yang mencakup sikap hidup manusia penggerak usaha pertanian ini adalah juga bagaimana caranya mereka itu dapat dengan segera memahami perkembangan baru dalam berbagai teknik budi-daya dan pemasaran. Untuk itu ilmu komunikasi pertanian adalah faktor kunci yang penting yang menjembatani hasil penelitian pertanian dengan pengusaha pertanian sebagai manusia penggerak usaha pertanian.
Sumber : Pengantar Ke Ilmu-ilmu Pertanian, Andi Hakim Nasution 2009.
Alih Fungsi Lahan Sawah, Salah Siapa…..? 4 May 2023 7:07 PM (last year)

Adalah sebuah realitas jika dari tahun ke-tahun jumlah penduduk akan semakin meningkat. Dengan trend laju pertambahan penduduk yang meningkat, maka peningkatan ketersediaan pangan adalah suatu kebutuhan.
Robert
Thomas Malthus (1766-1834) dalam bukunya yang paling terkenal Principle
of Population (1798) mengungkapkan bahwa
"Laju pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan laju
pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung". Artinya laju pertumbuhan
penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan pangan.
Dalam perspektif
Ketahanan Pangan, jika kebutuhan pangan penduduk meningkat, maka konsekuensi
kecukupan produksi pangan (khususnya pangan pokok) adalah sebuah kepastian yang harus ditempuh. Bagaimana
pun juga tidak bisa dipungkiri bahwa produksi pangan yang dihasilkan akan
sangat tergantung terhadap daya dukung lahan pertanian. Baik secara kualitas (tingkat
kesuburan) maupun secara kuantitas (luasan) ketersediaan lahan pertanian
menjadi determinan utama dalam usaha menyediakan pangan pokok manusia.
Diantara
sekian banyak hal dalam penataan ketahanan pangan, salah satu persoalan yang
masih menjadi pusat perhatian kebijakan nasional dewasa ini yaitu persoalan alih fungsi lahan pertanian
khususnya Alih Fungsi Lahan Sawah (AFLS).
Kondisi
umum tentang alih fungsi lahan sawah ini mudah untuk dicermati, yakni sejauhmana
dan seberapa banyak kasus atau peristiwa dimana lahan sawah produktif berubah fungsinya
menjadi lahan non pertanian. Apakah itu untuk fasilitas umum, permukiman,
perkantoran, industri, atau untuk hal lainnya di luar fungsi utama lahan sawah sebagai
“mesin” penghasil pangan,
Semudah
itulah kita memahami sebuah kenyataan tentang apa yang disebut dengan AFLS. Sebuah
konsekuensi yang harus diterima bahwa ada relasi kuat antara pertumbuhan
penduduk dengan segala aktivitasnya terhadap tekanan pemanfaatan sumberdaya
alam khususnya lahan pertanian.
Berangkat
dari asumsi diatas, kita meyakini bahwa kondisi alih fungsi lahan pertanian
khususnya AFLS adalah sebuah keniscayaan, atau dengan kata lain keniscyaan yang
berujung pada sebuah “keadaan yang memaksa”.
Kalau
kita dekati dari pola AFLS yang terjadi saat ini, maka akan ditemukan dua pola,
yaitu AFLS yang bersifat sistematis dan bersifat sporadis. Alih fungsi yang
bersifat sistematis terjadi dalam skala luasan yang besar (puluhan bahkan
ratusan hektar), dan lazimnya dilaksanakan oleh korporasi. Alih fungsi lahan
sawah untuk pembangunan kawasan industri, perkotaan, kawasan pemukiman (real
estate), jalan raya, komplek perkantoran, dan sebagainya mengakibatkan
terbentuknya pola alih fungsi yang sistematis. Lahan sawah yang beralih fungsi
pada umumnya mencakup suatu hamparan yang cukup luas dan terkonsolidasi.
Di sisi lain, AFLS yang dilakukan sendiri oleh
pemilik lahan sawah umumnya bersifat sporadis. Luas lahan sawah yang
terkonversi kecil-kecil dan terpencar. Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara
langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain sebelumnya
diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah.
Setidaknya
ada empat hal yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya alih fungsi
lahan pertanian (AFLS ) yaitu ;
1. Faktor
Kependudukan.
Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan
permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya.
Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan
tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat,
seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi, dan
sarana lainnya. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian yang memerlukan
lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk
sawah.
Hal ini dapat dimengerti, meningat lokasinya dipilih
sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di
perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang
sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran
pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta
telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya,
listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya.
Selain itu, terdapat keberadaan “sawah kejepit” yakni
sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih
menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut
mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi
lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.
2. Faktor
ekonomi,
Tingginya land
rent value yang diperoleh aktivitas
sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk
berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil
pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan
keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan
keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya),
seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan
pertaniannya.
3. Faktor
sosial budaya,
Terjadi antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan
terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala
ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Degradasi
lingkungan,
Dampak perubahan iklim seperti kemarau panjang yang
menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan
pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama
tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta
pencemaran air irigasi; rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan
terjadinya instrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang berpotensi meracuni
tanaman padi.
Alih
fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang
serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan
masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralih fungsi
tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi dan sangat
tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi
teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan
kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju.
Proses
alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait
dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus
ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk pembangunan
kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk pemenuhan
kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau untuk
lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan).
Proses
alih fungsi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika motivasi untuk
mengubah fungsi terkait dengan degradasi fungsi lahan sawah, misalnya akibat
kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tersebut tidak dapat difungsikan lagi
sebagai lahan sawah.
Secara
empiris, instrumen kebijakan yang selama ini menjadi andalan dalam pengendalian
alih fungsi lahan sawah adalah aturan pelaksanaan yang terkait dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi proses penyusunan RTRW yang pada umumnya
cukup alot ternyata juga belum menghasilkan petunjuk teknis yang benar-benar
operasional.
Berbagai
upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah telah banyak dilakukan.
Beragam studi yang ditujukan untuk memahami proses terjadinya alih fungsi,
faktor penyebab, tipologi alih fungsi, maupun estimasi dampak negatifnya telah
banyak pula dilakukan.
Beberapa
rekomendasi telah dihasilkan dan sejumlah kebijakan telah dirumuskan. Setidaknya
telah ada lebih dari 12 produk hukum tingkat
pusat, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi
Presiden, Peraturan Menteri ataupun Keputusan Bersama tingkat Menteri. Akan
tetapi sampai saat ini berbagai kebijakan tersebut belum berhasil mencapai
sasaran. Efektivitasnya masih terkendala oleh belum terwujudnya konsistensi
dalam perencanaan, serta lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan.
Kita tentu
ingat bagaimana retorika Ir.Soekarno (1952) memberikan akronim untuk istilah petani
sebagai Penyangga Tatanan Negara Indonesia.
Arti dari kepanjangan petani sebagai penyangga tatanan Negara Indonesia ini
memang dinilai pas dan cocok dengan profesi petani. Peran mereka memang
seperti penyangga, dimana tanpa mereka rakyat Indonesia tentu akan mengalami
krisis pangan. Hal ini tentu akan mengganggu tatanan negara Indonesia.
Lalu bagaimana
dan siapa yang akan memikirkan nasib sang penyangga negara tatkala dihadapkan
dengan situasi keadaan yang memaksa seperti ini…?
Cianjur,
5 Mei 2023
Penulis
Cianjur Gelar Acara Panen Padi Nusantara 1 Juta Hektar 14 Mar 2023 12:00 AM (2 years ago)
.jpg)
Padi masih merupakan komoditi andalan Kabupaten Cianjur, seabagai salah satu sentra produksi gabah di Provinsi Jawa Barat kontribusi produksi gabah Cianjur memang menjadi layak untuk di perhitungkan.
Produksi gabah
kering giling antara Januari – Februari 2023 Cianjur telah menghasilkan 246.069
ton, dengan jumlah luas tanam mencapai 22.401 ha.
Dengan pendekatan
pengelolaan tanaman padi terpadu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan
produksi secara optimal.
Dengan pencanangan
Kegiatan Panen Padi Nusantara 1 juta hektar yang dilaksanakan secara serempak
di seluruh Indonesia. Untuk Cianjur kegiatan tersebut di pusatkan di Poktan Tani
Mekar Desa Cibarengkok Kecamatan Bojongpicung Cianjur.
Acara yang
dilaksanakan pada Hari Kamis 9 Maret 2023 di helat dengan acara panen padi
seluas 240 hektar di Desa Bojongpicung dengan luas lahan sawah di kecamatan
Bojongpicung seluas 2661 hektar.
Hasil plot
ubinan terhadap lahan sawah yang dipanen menunjukan hasil produksi GKP kurang
lebih 6 ton per hektar. Hasil ini belum maksimal. Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dan mendapat atensi dari pihak berwenang dalam hal ini BPP Bojongpicung
dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Cianjur.
Keluhan petani
khususnya berkaiatan dengan sstabilitas produksi ini terkait dengan ketersediaan
pupuk, pengendalian OPT, dan system pengolahan lahan yang berimbang masih menjadi
kendala.
Diharapkan ke
depannya persoalan teknis dan non teknis menyangkut peningkatan produksi dan
produktivitas padi di Kecamatan Bojongpicung dan Kabupaten Cianjur dapat berangsur
diatasi.
Penyusun.Bid.TP DTPHPKP Cjr.
14/03/23
Analisis Sebab dan Dampak Gempa Bumi Cianjur 5.6 Mangnitudo (21 Nopember 2022) 13 Feb 2023 1:22 AM (2 years ago)

Indonesia menempati zona tektonik
yang sangat aktif karena tiga lempeng besar dunia dan sembilan lempeng kecil
lainnya saling bertemu di wilayah Indonesia dan membentuk jalurjalur pertemuan
lempeng yang kompleks (Bird, 2003). Keberadaan interaksi antar lempeng lempeng
ini menempatkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap
gempa bumi (Milson et al., 1992). Permasalahan utama dari peristiwa peristiwa
gempa adalah sangat potensial mengakibatkan kerugian yang besar, merupakan
kejadian alam yang belum dapat diperhitungkan dan diperkirakan secara akurat
baik kapan dan dimana terjadinya serta magnitudenya dan gempa tidak dapat
dicegah. Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapat diperkirakan secara akurat,
usaha-usaha yang biasa dilakukan adalah menghindari wilayah dimana terdapat
patahan atau sesar, kemungkinan tsunami dan longsor, serta bangunan sipil harus
direncanakan dan dibangun tahan gempa.
Dalam beberapa tahun terakhir telah
tercatat berbagai aktivitas gempa besar di Indonesia, yaitu Gempa Aceh disertai
tsunami tahun 2004 (Mw = 9,2), Gempa Nias tahun 2005 (Mw = 8,7), Gempa Jogja
tahun 2006 (Mw = 6,3), Gempa Tasik tahun 2009 (Mw = 7,4) dan terakhir Gempa
Padang tahun 2009 (Mw = 7,6). Gempagempa tersebut telah menyebabkan ribuan
korban jiwa, keruntuhan dan kerusakan ribuan infrastruktur dan bangunan, serta
dana trilyunan rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan data dari BNPB (Badan
Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa dalam kurun waktu tahun 1828 – 2017 di
seluruh provinsi di Indonesia tercatat 515 kejadian gempabumi dimana jumlah
kejadian gempabumi yang paling tinggi yaitu pada tahun 2009 sebanyak 54
kejadian dan jumlah korban jiwa yaitu sebanyak 1286 orang, sedangkan jumlah
korban jiwa yang paling tinggi yaitu pada tahun 2006 sebanyak 5700 orang dengan
jumlah kejadian sebanyak 33 bencana gempabumi.
Kabupaten Cianjur merupakan salah
satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Menurut data BNPB
Kabupaten Cianjur pernah dilanda bencana gempa bumi pada tahun 2009
(http://dibi.bnpb.go.id/). Berdasarkan informasi tersebut kejadian gempabumi
yang melanda Kabupaten Cianjur mengakibatkan 28 orang meninggal, 42 hilang dan
21 orang luka-luka serta 10047 penduduk mengungsi. Kejadian gempabumi tersebut
telah merendam rumah penduduk, akses jalan serta areal lahan pertanian warga.
Gempa bumi terbaru yang melanda
Kabupaten Cianjur terjadi pada Tanggal
21 Nopember 2022, siang hari (13:21:10 WIB) dengan kekuatan Mw 5.6.
Berdasarkan data BMKG, hingga tanggal 22 November 2022 telah tercatat 140
gempa-gempa susulan (aftershocks) dengan magnitudo 1.2-4.2 dan kedalaman
rata-rata sekitar 10 km, dimana 5 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat
sekitar.
Gempabumi utama (mainshock) Mw 5.6 berdampak dan dirasakan di kota Cianjur dengan skala intensitas V-VI MMI (Modified Mercalli Insensity); Garut dan Sukabumi IV-V MMI; Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkasbitung, Bogor dan Bayah dengan skala intensitas III MMI; Tangerang Selatan, Jakarta dan Depok dengan skala intensitas II-III MMI.
Analisis Gempa Bumi Cianjur
Gempabumi yang terjadi di daerah
Cianjur ini termasuk jenis gempa tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake)
dengan tipe mainshock-aftershocks, yaitu gempabumi utama yang kemudian diikuti
oleh serangkaian gempabumi susulan (Mogi, 1963). Berdasarkan sebaran episenter
dan hiposenter hasil relokasi (Gambar 1), gempabumi ini sangat menarik, dimana
gempa utama (mainshock) berlokasi di arah utara Sesar Cimandiri segmen
Rajamandala, sementara gempa-gempa susulannya (aftershocks) berada di sebelah
Timur Laut relatif terhadap gempa utama.
Mekanisme fokus gempa utama Mw 5.6
ini menunjukkan sesar geser mengiri (sinistral strike-slip fault) pada arah
Barat Daya-Timur Laut yang mirip dengan dominasi pergerakan dari Sesar
Cimandiri segmen Rajamandala. Jika kita melihat sebaran episeter gempa-gempa
susulan hasil relokasi pada Gambar 1, cluster (kumpulan) gempabumi susulan
tersebut berarah Barat Daya-Timur Laut pada jarak sekitar 15 km sebelah utara
dari Sesar Cimandiri segmen Rajamandala.
Berdasarkan mekanisme fokus gempa
utama dan sebaran hiposenter hasil relokasi, kami membuat interpretasi sesar
penyebab gempa Mw 5.6 ini dan area sesarnya (garis putus-putus warna biru dan
kotak putus-putus warna biru pada Gambar 1 bagian bawah) yang merupakan sesar
geser mengiri dan memiliki dip ke arah Barat Laut. Untuk interpretasi lebih
lanjut diperlukan validasi dari lapangan dan data pendukung lainnya.
Gambar 1. Episenter dan hiposenter gempabumi Cianjur
hasil relokasi tanggal 21 November 2022. Bulatan merah menunjukkan episenter
gempa berdasarkan kedalaman. Garis warna merah adalah sesar aktif dari Irsyam
dkk. (2017). Mekanisme fokus gempa dari https://inatews.bmkg.go.id/. Garis
putus-putus warna biru pada gambar kiri bawah adalah interpretasi sesar
penyebab gempa Mw 5.6 dan kotak putus-putus warna biru pada gambar kanan bawah
adalah interpetasi area sesar berdasarkan sebaran gempa-gempa susulan.
Akibat dan Dampak Bencana
Pengkajian akibat merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia. Ketentuan mengenai unsur-unsur yang membangun komponen akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1. Komponen Akibat Bencana
|
Komponen |
Keterangan |
|
Kerusakan |
Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik
pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sehingga terganggu fungsinya
secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana.
Misalnya, kerusakan rumah, sekolah, pusat kesehatan, pabrik, tempat usaha,
tempat ibadah dan lain-lain dalam kategori tingkat kerusakan ringan, sedang
dan berat. |
|
Kerugian |
Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan
untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah,
masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu
bencana. Misalnya, potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah
selama periode waktu hingga aset dipulihkan. |
|
Gangguan Akses |
Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga dan
masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat suatu bencana.
Misalnya, rumah yang rusak atau hancur karena bencana mengakibatkan orang
kehilangan akses terhadap naungan sebagai kebutuhan dasar. Rusaknya rumah
sakit atau fasilitas layanan kesehatan mengakibatkan orang kehilangan akses
terhadap pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Kerusakan sarana
produksi pertanian membuat hilangnya akses keluarga petani terhadap hak atas
pekerjaan. |
|
Gangguan Fungsi |
Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan
pemerintahan akibat suatu bencana. Misalnya, rusaknya suatu gedung
pemerintahan mengakibatkan terhentinya fungsi-fungsi administrasi umum,
penyediaan keamanan, ketertiban hukum dan pelayanan-pelayanan dasar. Demikian
juga bila proses-proses kemasyarakatan dasar terganggu, seperti proses
musyawarah, pengambilan keputusan masyarakat, proses perlindungan masyarakat,
proses-proses sosial dan budaya. |
|
Meningkatnya Risiko |
Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas
individu, keluarga dan masyarakat sebagai akibat dari suatu bencana.
Misalnya, bencana mengakibatkan perburukan terhadap kondisi aset, kondisi kesehatan,
kondisi pendidikan dan kondisi kejiwaan sebuah keluarga, dengan demikian
kapasitas keluarga semakin menurun atau kerentanannya semakin meningkat bila
terjadi bencana berikutnya. |
Komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak bencana terhadap aspekaspek ekonomi-fiskal, sosial-budaya-politik, pembangunan manusia dan infrastrukturlingkungan secara agregat (total). Pengkajian dampak bencana merupakan pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Pengkajian dampak bencana berguna untuk memandu agar pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana memiliki orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Tabel 2. Komponen Dampak Bencana
|
Komponen |
Keterangan |
|
Ekonomi dan Fiskal |
Dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas ekonomi
masyarakat di tingkat kabupaten/kota setelah terjadi bencana yang
berimplikasi terhadap produksi domestik regional bruto. Kapasitas ekonomi
masyarakat tersebut meliputi tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat,
tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan
lain-lain. Penurunan terhadap investasi, impor serta ekspor juga dapat
diidentifikasi sebagai dampak bencana terhadap perekonomian. Dampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak bencana dalam jangka
pendek hingga menengah. Kapasitas keuangan pemerintah meliputi kapasitas
pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan bagi hasil
atas kekayaan negara yang dipisahkan. Penurunan kapasitas ini berimplikasi
pada menurunnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasinya. |
|
Sosial, Budaya dan Politik |
Dampak budaya adalah perubahan sistem nilai, etika dan
norma dalam masyarakat setelah bencana. Contoh dampak terhadap budaya adalah
menurunnya kegiatan-kegiatan kebudayaan, berubahnya standar nilai dalam
masyarakat dan lain-lain. Dampak budaya berimplikasi pada perubahan struktur
sosial dalam jangka menengah dan panjang. Perubahan ini mencakup perubahan
cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana.
Meningkatnya masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur
adanya dampak sosial akibat bencana. Misalnya meningkatnya konflik sosial, meningkatnya
kekerasan berbasis gender, meningkatnya jumlah pekerja anak dan meningkatnya
perceraian. Dampak politik adalah perubahan struktur kuasa dan perilaku
politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana. Contoh
dampak politik adalah bencana berimplikasi pada peningkatan konflik berbasis
politik karena perebutan sumber daya setelah bencana. Atau menurunnya
kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena
salah kelola dalam penanganan bencana. |
|
Pembangunan Manusia |
Dampak pembangunan manusia adalah dampak bencana terhadap
kualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang
diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan
Indeks Kemiskinan Multidimensional. Kualitas pembangunan manusia diatas dapat
diprediksi dari indikator-indikator jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah
perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki
akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lain-lain. |
|
Lingkungan |
Dampak terhadap lingkungan adalah penurunan kualitas
lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan membutuhkan
pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penurunan ini misalnya penurunan
ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran
sungai serta kepunahan spesiesspesies langka setelah bencana |
Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/Post Disaster Need
Asessment (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian
akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian
meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non
fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman,
infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.
Analisis dampak melibatkan tinjauan
keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat-akibat bencana dan implikasi
umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial,
budaya, politik dan tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan
biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi. PDNA bertujuan agar upaya-upaya pemulihan pascabencana
berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Semangat
ini tertuang pada ketiga komponen PDNA sebagai berikut. 1. Pengkajian akibat
bencana; 2. Pengkajian dampak bencana; dan 3. Pengkajian kebutuhan
pascabencana.
Komponen-komponen dalam PDNA diatas memiliki
kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan
pascabencana. Hubungan antar komponen-komponen dalam PDNA tampak pada diagram
dibawah ini:
Diagram 1. Alur Proses PDNA
Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam PDNA berorientasi
pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal , rehabilitasi dan rekonstruksi.
a) Kebutuhan pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak
yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk
pemulihkan fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa
kebutuhan fisik maupun non fisik. Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus
berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini
misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara,
pemulihan layanan pengobatan di PUSKESMAS dengan melibatkan dokter dan
paramedik di PUSKESMAS tersebut sehingga pemulihannya bisa lebih cepat termasuk
penyediaan layanan psiko-sosial.
b) Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan
pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada
wilayah pascabencana.
c) Kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali
semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat
Dengan demikian, komponen
pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan
risiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan
kebutuhan dalam PDNA.
Tabel 3. Komponen Perkiraan Kebutuhan
|
Komponen |
Keterangan |
|
Pembangunan |
Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan aset milik
pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana.
Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang
lebih tahan bencana sehingga pengurangan risiko bencana wajib menjadi
pertimbangan dalam memperkirakan kebutuhan pascabencana. |
|
Penggantian |
Kebutuhan penggantian bertujuan untuk mengganti kerugian
ekonomi yang dialami oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha
sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada
pemulihan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif,
efisien dan berkelanjutan. |
|
Penyediaan bantuan akses |
Kebutuhan penyediaan bantuan yang bertujuan untuk membantu
memulihkan akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap hakhak dasar
seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya,
pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam
rangka pemulihan sistem pelayanan dasar yang ada. |
|
Pemulihan fungsi |
Kebutuhan pemulihan fungsi merupakan kebutuhan yang
bertujuan untuk menjalankan kembali fungsi atau proses pemerintahan dan
kemasyarakatan. Fungsi pemerintahan misalnya memulihkan fungsi pemerintahan
desa yang terganggu akibat bencana atau memulihkan fungsi PUSKESMAS dalam
melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Pemulihan proses kemasyarakatan
misalnya pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan
organisasi berbasis masyarakat lainnya. |
|
Pengurangan risiko |
Kebutuhan pengurangan risiko meliputi kebutuhan mencegah
dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan
kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi
kemungkinan bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan
pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan
risiko akibat bencana. |
Berdasarkan infografis https://gis.bnpb.go.id/ penananganan bencana Gempa Bumi
Cianjur 5.6 Magnitudo, data cut off pada tanggal 21 Desember 2022 Pkl.
17.00 WIB, kondisi yang diakibatkan adalah :
Tabel 5.
Komponen Akibat dan Dampak Bencana
|
No |
Komponen |
Keterangan |
|
1 |
Korban Meninggal
Dunia |
338 Jiwa |
|
2 |
Korban Luka Dirawat |
2 Jiwa* (*di Cianjur) |
|
3 |
Korban Dalam Pencarian |
5 Jiwa |
|
4 |
Korban Pengungsi |
114.683 Jiwa |
|
5 |
Kerusakan |
59.574 Total Rumah
Rusak (Data
Sementara) 14.537 Rumah Rusak
Berat 17.097 Rumah Rusak
Sedang 27.940 Rumah Rusak
Ringan
Fasilitas
Pendidikan Rusak 701 Unit Kantor/Gedung
Rusak 18 Unit Fasilitas
Ibadah Rusak 281 Unit |
|
6 |
Lokasi Terdampak |
16 Kecamatan 180 Desa |
Sumber data Gempabumi Cianjur 2022 (bnpb.go.id)
1. Update data : Posko
Penanganan Bencana Gempabumi Cianjur
2. Skahemaps dan
epicentre gempabumi : BMKG
3. Titik Pengungsi :
Assessmen KPPPA, DPPKBP3A Kab. Cianjur, BNPB
4. Data citra UAV
(Drone) : Kolaborasi BNPB dan Fly for Humanity
5. Pendataan Rumah
Rusak : Rutena (KemenPUPR) dan BNPB
Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik maupun non fisik. Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu aspek pemenuhan kebutuhan pemulihan awal yang penting dan dianggap mendesak adalah pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras) bagi korban pengungsi.
Tabel 6. Data Pengungsi Terpilah
|
No |
Komponen |
Keterangan |
|
1 |
Jumlah
Pengungsi |
114.683 Jiwa
|
|
2 |
Jumlah Pengungsi
Laki Laki |
54.781 Jiwa |
|
3 |
Jumlah
Pengungsi Perempuan |
59.902 Jiwa |
|
4 |
Jumlah KK
Pengungsi |
41.166 KK |
|
5 |
Jumlah
Titik Pengungsi Mandiri |
119 titik |
|
6 |
Jumlah
Titik Pengungsi Terpusat |
375 titik |
|
7 |
Jumlah
Titik Pengungsian |
494 titik |
Tabel 6. Perkiraan Kebutuhan Pangan Pokok Beras
(Pemulihan Awal Bencana Gempa Bumi Cianjur)
|
No |
Komponen |
Keterangan |
|
1 |
Jumlah
Pengungsi |
114.683 Jiwa
|
|
2 |
Konsumsi
Rata Rata /jiwa/bln |
9,23 kg* |
|
3 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 1 bulan |
1.058,52 ton |
|
4 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 2 bulan |
2.117,04 ton |
|
5 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 3 bulan |
3.175,56 ton |
|
6 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 4 bulan |
4.234,08 ton |
|
7 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 5 bulan |
5.292,60 ton |
|
8 |
Kebutuhan
Pangan Pokok Beras / 6 bulan |
6.351,12 ton |
Keterangan * ; Hasil Susenas BPS Tahun 2021 Konsumsi beras 110,8 kg per kapita per tahun Kabupaten Cianjur
Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras) bagi korban pengungsi Bencana Gempa Bumi Cianjur diperlukan antara 1.058,52 ton sampai dengan 6.351,12 ton untuk jangka waktu pemulihan awal antara 1 bulan sampai dengan 6 bulan.
By.Admin
Sumber referensi
1) Gempabumi Cianjur 2022 (bnpb.go.id) https://gis.bnpb.go.id/2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) No.15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/Post Disaster Need Asessment (PDNA)
3) Sumardani Kusmajaya, dan Riskyana Wulandari, KAJIAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN CIANJUR, Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor, 2 Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 10, No. 1 Tahun 2019 Hal. 39-51.
4) Pepen Supendi* , Priyobudi, Jajat Jatnika, Dimas Sianipar, Yusuf Haidar Ali, Nova Heryandoko, Daryono, Suko Prayitno Adi, Dwikorita Karnawati, Suci Dwi Anugerah, Iman Fatchurochman, Ajat Sudrajat. Analisis Gempabumi Cianjur (Jawa Barat) Mw 5.6 Tanggal 21 November 2022. Kelompok Kerja Sesar Aktif dan Katalog Gempabumi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta 10720, Indonesia.
Contoh Media Penyuluhan Pertanian ; GAMBAR SINGKAP 31 Aug 2021 6:54 AM (3 years ago)

Gambar Singkap Dengan Judul
KOMPOS MANFAAT DAN CARA MEMBUATNYA
COVER DEPAN
BLPP CIHEA DARI MASA KE MASA 29 Aug 2021 7:21 AM (3 years ago)

KAWASAN Cihea, Kabupaten Cianjur, dikenal sebagai salah satu
sentra produksi padi di wilayah Jawa Harat. Pada lokasi ini terdapat sejumlah
balai lingkup pertanian, salah satunya adalah Balai Pelatihan Pertanian
(Bapeltan) Cihea, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
yang berada di kawasan Bojongpicung Cianjur.
Keberadaan kawasan Cihea-Bojongpicung tersebut sebenarnya
memiliki sejarah panjang karena sejak zaman kolonial belanda. Lokasi tersebut
diketahui dahulunya bernama Regeering Rijsthoeve Cihea yang menurut catatan
sejumlah surat kabar yang tersimpan di Koninklijke Bibliothbek Belanda dan
arsip BBPP Cihea, mulai berdiri tahun 1919.
Sisa-sisa kejayaan Regeering Rijsthoeve Cihea yang pada zamannya merupakan perusahaan pertanian padi milik pemerintah Hindia Belanda, masih terlihat sampai kini.Selain hamparan suwah yang masih luas,juga terdapat sejumlah aliran saluran irigasi yang cukup terawat dan menjadi pemandangan khas kawasan Cihea yang melintasi sampai Jalan Raya Ciranjang-Cianjur.
Berdasarkan arsip Koninklijke Bibliotheek Belanda pula
disebutkan Regeering Rijsthoeve Tjihea merupakan kawasan perusahaan pertanian
padi milik pemerintah Hindia Belanda. Dalam operasionalnya, Reguering
Rijsthoeve berfingsi sebagai penyuplai pasokan padi untuk willayah Jawa Barat.
Diberitakan Het
nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie terbitan 15 April
1920, sebagai administratur Regeering Rijsthoeve Tjihea yang pertama adalah
Reinders, yang dari namanya, Reinders adalah orang Jerman. Kawasan Regeering
Rijsthoeve Tjihea dilengkapi satu pabrik penggilingan gabah untuk kemudian
menghasilkan padi dan benih padi yang digunakan untuk
memasok kebutuhan di wilayah Jawa Barat.
De Indische Courant pada 4
Juli 1929 memberitakan, pada masa itu jumlah pemukiman di Cihea masih sedikit.
Bahkan, kemudian terjadi wabah penyakit malaria yang mengakibatkan banyak orang
tewas, terutama para pekerja di lingkungan Regeering Rijsthoeve Tjihea.
Kisah perjalanan Regeering Rijsthoeve Tjihea baru kembali diketahui
pihak Belanda saat berupaya kembali menguasai lokasi tersebut selepas
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pihak Belanda memandang keberadaan
Regeering Rijsthoeve Tjihea sebagai instalasi vital bagi pasokan padi dan benih
padi untuk Jawa Barat.
Diberitahukan, Nieuwe
courant terbitan 14 Agustus 1946, dengan mengutip Kantor
Berita Aneta dari Bandung, pihak Belanda kembali memasuki kawasan Regeering
Rijsthoeve Tjihea dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Dari luasan total 7.500
hektare, hanya sepertiganya yang ditanami padi tetapi mengalami kondisi
kekeringan besar karena saat itu pada Agustus sedang puncak kemarau.
Dalam kondisi tersebut, kata berita itu, Regeering Rijsthoeve
Tjihea mengalami serangan hama tikus tapi belum membahayakan. Sementara
jaringan irigasinya masih utuh dan masih berfungsi dengan baik.
Disebutkan, pihak Belanda segera melakukan perbaikan kawasan
Regeering Rijsthoeve Tjihea dalam target harus cepat selesai. Sejumlah penduduk
disepanjang jalur Padalarang dan Cianjur kemudian dikerahkan untuk mengolah
tanah agar segera dapat ditanami kembali oleh tanaman pangan.
ALGEMEEN Indisch
Dagblad pada 16 Mei 1947 memberitakan,
kawasan Cihea sebenarnya dikenal sebagai daerah sentra produksi beras yang
sehat dan kawasan pertanian yang subur. Namun kemudian kondisinya menjadi
merana saat pendudukan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1942-1945, lalu
kemudian segera dipulihkan oleh pihak Belanda.
Diceritakan, beberapa wartawan asal Amerika, Australia, Prancis,
dan Belanda membuat perjalanan dari Bandung ke Batavia. Mereka memberitakan,
ada salah satu daerah yang paling subur di Pulau Jawa, yaitu Cihea, sekitar 20
km dari arah timur Cianjur.
Para Wartawan tersebut menuliskan, merasa kagum dengan keindahan
alam daerah Cianjur, khusunya Cihea yang merupakan hamparan sawah yang luas.
Mereka membayangkan, kondisinya berbeda dengan tahun 1920-an, di mana kawasan
Cihea asalnya hanya lahan basah dan rawa yang dipenuhi nyamuk malaria yang
kemudian dihuni sekitar 3.000 orang Indonesia dalam kondisi buruk yang semuanya
terserang penyakit malaria.
Diberitahukan pula, oleh Pemerintah Hindia Belanda, kawasan
Cihea kemudian diubah menjadi kawasan pertanian produktif. Bahkan sejak tahun
1920, Cihea dijadikan lumbung pangan sejati untuk Pulau Jawa.
Diceritakan pula, pada tahun 1941 di Cihea kemudian terdapat
lebih dari 40.000 petani sehat yang menggarap lebih dari 5.200 hektare sawah
intensif. Produktifitas padi di Cihea pada masa itu adalah 6 ton/hektare pada
sawah irigasi. Bersamaan dengan masa itu pula wabah penyakit malaria mulai
menghilang di Cihea.
De Locomotief terbitan
16 Juni 1950 memberitakan, sehari sebelumnya ada kelompok tak dikenal dalam
jumlah besar menyerang kawasan Regeering Rijsthoeve Tjihea yang sudah berganti
nama menjadi Perusahaan Pertanian Cihea. Dalam kejadian itu, sebanyak 12
personel Perusahaan Pertanian Cihea tewas dan salah seorang penyerang kemudian
ditangkap.
Keberadaan BLPP Cihea
Balai Latihan Pegawai Pertanian Cihea (BLPP Cihea), merupakan balai latihan yang di khususkan bagi
para pegawai pertanian (penyuluh pertanian). BLPP Cihea ini didirikan pada tahun 1978 dengan peresmian yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 Januari 1978. Gedung BLPP Cihea sendiri di resmikan 4 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 5 Maret 1982 oleh Menteri Pertanian saat itu Ir.Soedarsono Hadisaputro. BLPP Cihea sekarang statusnya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah wewenang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Jawa Barat. BLPP Cihea sekarang berganti nama menjadi Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura (BPPTPH) Propinsi Jawa Barat. Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPTPH) beralamat di JL. Terusan Moch. Ali Bojongpicung, Neglasari, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43283.
by.admin
sumber referensi :
http://distan.jabarprov.go.id/distan/blog/detail/3710-mengenang-kejayaan-kawasan-pertanian-cihea
Jaringan Irigasi Cihea “ Heritage” (warisan) Kolonial Yang Masih Kokoh 25 Aug 2021 11:12 PM (3 years ago)

Daerah Irigasi Cihea merupakan salah satu daerah irigasi yang berada di Propinsi Jawa Barat, tepatnya di
Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Irigasi Cihea masuk dalam katagori Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di bawah Kementerian PUPR.
|
NO. |
KECAMATAN |
LUAS LAHAN SAWAH IRIGASI
NON-IRIGASI (Ha) |
JUMLAH |
|
|
IRIGASI |
NON-IRIGASI |
|||
|
1 |
BOJONGPICUNG |
2556.89 |
104.84 |
2661.73 |
|
2 |
CIRANJANG |
1794.98 |
37.21 |
1832.19 |
|
3 |
HAURWANGI |
1299.66 |
5.44 |
1305.10 |
|
JUMLAH |
5651,53 |
147,49 |
5799,02 |
|
DI Cihea yang bersumber dari sungai Cisokan
merupakan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1816. Sumber Air irigasi
ini adalah dengan cara membendung aliran Sungai Cisokan berlokasi di Kp.Cisuru.
Bendungan peninggalan pemerintah kolonial Belanda sampai saat ini banyak yang
masih berdiri kokoh dan berfungsi dengan baik.
Bendungan yang terletak sekitar 30 km ke
arah tenggara dari pusat kota Cianjur itu berusia lebih dari 100 tahun, tapi
kondisinya masih kokoh, bahkan diperkirakan masih akan kokoh hingga beberapa
puluh tahun ke depan.
Kalaupun karena satu dan lain hal bendungan
itu roboh, misalnya karena bencana alam, pemerintah mau tidak mau harus
membangunnya kembali. Sebab, menurut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danPertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Bendungan Cisokan
merupakan sumber pengairan utama bagi lebih dari 5.500 ha sawah di dataran
Cihea, tepatnya bagi 18 desa Kecamatan Bojongpicung dan Ciranjang. Tanpa
Bendungan Cisokan, persawahan di dataran Cihea dipastikan berubah menjadi sawah
tadah hujan.
Data Jaringan Irigasi :
1. Bendung : 2 buah
2. Bangunan Bagi : 3
3. Bangunan Bagi/Sadap : 10 buah
4. Bangunan sadap : 101 buah
5. Bangunan Terjun : 96 buah
6. Bangunan ukur : 11 buah
7. Bangunan Talang : 9 buah
8. Bangunan Suplisi : 22 buah
9. Petak Tersier : 146 buah
10.Bangunan Sypon : 3 buah
11. Gorong-gorong : 23 buah
Panjang Saluran
1. Sal. Terowongan : 1,200 km
2. Sal. Induk Cisokan : 20,146 km
3. Sal. Induk Ciranjang : 6,340 km
4. Sal. Sekunder : 29,579 km
5. Sal. Tersier : 10,827 km
6. Sal. Pembuang : 16,420 km
Jalan
1. Jalan Inspeksi : 19,840 km
Wajar bila Bendungan Cisokan berikut
puluhan kilometer saluran irigasinya merupakan salah satu infrastruktur penting
yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Cianjur. Bahkan sejarahwan Reiza D
Dienaputra (dosen Unpad) dalam Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg, Sejarah
Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942 (Bandung 2004) menyebutkan,
pembangunan sarana irigasi Cihea berhasil mengubah Cianjur menjadi daerah
penghasil beras di Priangan.
Pembangunan irigasi di dataran Cihea itu
dilakukan sejak akhir abad ke-19 dan selesai pada awal abad ke-20. "Hingga
akhir dasawarsa kedua abad ke-20, irigasi Cihea masih menjadi satu-satunya
sistem pengairan yang relatif sangat baik untuk seluruh Keresidenan
Priangan," tulis Reiza dalam buku yang diterbitkan atas kerja sama Pemkab
Cianjur dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Unpad Bandung itu.
Meski begitu, di tahun-tahun awal
keberadaannya, irigasi tersebut sempat merugikan penduduk Cianjur, yakni adanya
wabah malaria. Wabah ini timbul karena saluran pengairan di seputar irigasi
Cihea kurang dipelihara dengan baik. Akibatnya muncul rawa-rawa yang menjadi
tempat bersarangnya nyamuk malaria.
Wabah malaria itu bukanlah tumbal pertama
dari pembangunan irigasi Cihea. Justru korban lebih banyak terjadi ketika
Bendungan Cisokan yang berlokasi di Cisuru mulai dibangun.
Korban tewas terjadi terutama di saat
rakyat membangun terowongan air berdiameter 3 m sepanjang 1.200 m. Karena
memang terowongan yang mengalirkan air dari Bendungan Cisokan ke saluran
irigasi Cihea itu merupakan bagian paling berat dari proyek tersebut.
Terowongan ini dibuat dengan melubangi tebing Sungai Cisokan yang merupakan
daerah berbatu cadas.
TEROWONGAN AIR: Seperti inilah kondisi terowongan ‘Irigasi Cihea’ Bojongpicung sepanjang 1.200 meter
Ribuan rakyat, yang sebagian di antaranya
didatangkan dari luar Cianjur, dikerja-paksa untuk melubangi tebing cadas itu
dengan peralatan sederhana: belincong, linggis, dan pacul. Sedangkan makanan
sangat kurang. Tak heran bila banyak rakyat yang tewas karena kalaparan.
Usai membuat terowongan air, rakyat kembali
dikerja-paksa membuat saluran irigasi dengan lebar 5-10 m menelusuri tebing
bukit hingga ke daerah dataran Cihea. Jumlah korban meninggal saat membuat
saluran irigasi yang sekarang disebut warga setempat sebagai Walungan (Sungai)
Cisuru itu kabarnya juga tidak sedikit, terutama diakibatkan serangan penyakit
malaria.
"Pengorbanan ribuan rakyat waktu itu
tidaklah sia-sia. Karena Bendungan Cisokan berikut saluran irigasinya sampai
sekarang masih berfungsi dengan baik. Sekalipun di musim kemarau, ribuan
hektare sawah di Bojongpicung dan Ciranjang tetap bisa ditanami padi dua sampai
tigakali dalam setahun.
By.admin
Referensi :
http://bpsda-wilayah.blogspot.com/2012/03/sejarah-bendungan-cisuru.html
https://www.journalnews.co.id/2021/05/sejarah-bendungan-legendaris-cisuru-di.html
Laporan Informasi Lahan Pertanian Kab.Cianjur
(Dinas Pertanian Kab.Cianjur 2018)
http://balaiwilayahiiiciranjang.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
Pengertian jarak dan metode pengukuran 24 Aug 2021 4:10 AM (3 years ago)

Jarak antara dua buah titik dapat berupa jarak miring yaitu panjang langsung yang menghubungkan kedua titik tersebut, jarak vertikal atau tegak yang merupakan beda tinggi antara kedua titik, dan jarak
horisontal atau datar yaitu panjang di bidang proyeksi dari kedua titik tersebut. Dalam ilmu ukur tanah bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar, sehingga jarak yang digunakan adalah jarak horisontal. Jarak horisontal antara dua titik yang berbeda tingginya dapat ditentukan dengan mengukur bagian demi bagian jarak datarnya, atau mengukur langsung jarak miringnya dan dihitung jarak datarnya dari sudut miringnya atau beda tingginya.
Beberapa
metode pengukuran jarak adalah: (a) langkah, (b) roda ukur, (c) takhimetri, (d)
subtense bar, (e) pita ukur, (f) EDM, dan (g) sistem satelit. Ketelitian,
penggunaannya dan peralatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.
Sedangkan sistem satelit dapat juga digunakan untuk menentukan jarak, misalnya
GPS (Global Positioning System) dapat menentukan jarak karena dengan alat GPS
akan diketahui koordinat suatu titik, dan jarak dihitung dari koordinatnya.
Sudut dibedakan dalam dua macam
yaitu sudut horisontal dan sudut vertikal. Sudut horisontal
adalah sudut di bidang horisontal yang dibentuk oleh perpotongan dua bidang
vertikal, dan vertex atau titik sudut terletak pada garis vertikal di
perpotongan dua bidang. Dalam ilmu ukur tanah sudut horisontal juga merupakan
selisih antara dua buah arah yaitu arah depan (foresight) dan arah belakang
(backsight).
Sudut
horisontal dapat diukur secara langsung yaitu dengan mengukur arah
belakang dan arah depan dengan alat teodolit yang dipasang di titik sudut, dan
dapat pula diukur secara tidak langsung yaitu dengan penggukuran
jarak-jarak horisontalnya.
Sumber : MK.Dasar Pemetaan Jurusan
Teknik Sipil FTSP-USAKTI
Jenis Jenis Alat Ukur Tanah 24 Aug 2021 4:06 AM (3 years ago)

Alat ukur tanah yang utama
adalah: teodolit dan level atau penyipat datar atau waterpas,
serta alat pengukur jarak.
Teodolit
Fungsi Teodolit :
1. mengukur arah/ sudut
2. mengkur beda tinggi/ tinggi
3.
mengukur jarak
Keterangan:
1.
Okuler teropong
2.
Obyektif teropong
3.
Pengatur focus
4.
Alat pembaca micrometer
5.
Alat pemutar micrometer
6.
Penggerak halus horizontal atas
7.
Penggerak halus horizontal bawah
8.
Penggerak halus vertical
9.
Pengunci putaran horizontal atas
10.
Pengunci putaran horizontal bawah
11.
Pengunci putaran vertikal
12.
Nivo tabung
13.
Nivo kotak
14.
Skrup penyetel
15.
Lingkaran horizontal
16.
Lingkaran vertikal
17.
Loop centering optic
18. Kaca pemantul cahaya
Level/
waterpas/ penyipat datar
fungsi
: mengukur beda tinggi/ tinggi
Keterangan:
1.
Okuler teropong
2.
Obyektif teropong
3.
Tombol pemfokus
4.
Penggerak halus horizontal
5.
Nivo kotak
6.
Skrup penyetel
7. Lingkaran horizontal
Alat
pengukur jarak
pita ukur
-
dibedakan menurut bahannya: kain, fiberglas, steelon, steel/ baja, dan invar.
Invar tape terbuat dari campuran nickel (36%) dan baja, dan mempunyai koefisien
muai panas/ thermal expansion yang sangat rendah (0,000000122 per 1o C).
altimeter: alat pengukur ketinggian; clinometer: alat pengukur lereng/
slope; kompas: alat penunjuk arah dengan magnit; optical square/
prisma (pentagonal prism dan double prism): alat untuk membuat sudut siku-siku;
planimeter: alat pengukur luasan; pantograf: alat untuk
memperbesar atau memperkecil peta/ gambar; curvimeter: alat untuk
mengukur panjang kurva/ garis di peta; plane table: alat ukur tanah
(mirip teodolit) yang dilengkapi meja gambar untuk membuat peta yang digambar
langsung di lapangan.
Sumber : MK.Dasar Pemetaan Jurusan
Teknik Sipil FTSP-USAKTI
Pengertian Dasar Ilmu Surveying dan Perpetaan Bidang Pertanian 24 Aug 2021 3:52 AM (3 years ago)

Definisi, lingkup, dan jenis surveying
Surveying didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk menentukan posisi titik-titik diatas, pada, atau di bawah permukaan bumi; atau sebaliknya, yaitu memasang titik-titik tersebut di lapangan. Metode pelaksanaan di darat (survai terestris) paling sering dilakukan, tetapi metode survai di udara (aerial surveying) dan survai dengan satelit (satellite surveying) juga umum digunakan.
Surveying dapat dibagi dalam: (a) Geodetic surveying,
disini memperhitungkan adanya kelengkungan bumi, sehingga dibutuhkan
pengetahuan ilmu ukur sferis (spherical geometry) untuk perhitungannya; dan (b)
Plane surveying, disini tidak memperhitungkan adanya kelengkungan bumi,
sehingga semua hasil ukuran akan digambarkan pada bidang datar berdasarkan
rumusan ilmu ukur bidang datar. Plane surveying inilah yang dikenal sebagai ilmu
ukur tanah, dan geodetic surveying sebagai ilmu geodesi.
Di dalam Ilmu ukur tanah jarak-jarak yang diukur dianggap
sebagai garis lurus dan sudut antara dua garis dianggap terletak pada bidang
datar. Ilmu ukur tanah digunakan hanya untuk daerah yang relatif sempit yaitu
kurang dari 260 km2, karena perbedaan jarak lurus dan lengkung di
permukaan bumi sejauh 18,2 km hanya sekitar 0,10 meter (Agor, 1982). Dengan
demikian untuk bidang enjiniring yang biasanya dibutuhkan peta-peta skala besar
dan cakupan wilayahnya relatif sempit, lebih tepat menggunakan rumusan ilmu
ukur tanah ini.
Hasil pengukuran dewasa ini digunakan untuk: (a) memetakan
bumi diatas dan dibawah permukaan laut; (b) menyiapkan peta navigasi untuk
penggunaan di udara, darat dan di laut; (c) penentuan batas-batas pemilikan
tanah; (d) pengembangan bank data informasi geografi; (e) penentuan ukuran,
bentuk, gravitasi, medan magnit bumi, dan (f) menyiapkan peta-peta bulan dan
planet.
Surveying
atau metode surveying sering digunakan dan sangat membantu di bidang geografi,
geologi, astronomi, pertanian, kehutanan, archeologi, arsitektur dan teknik
sipil. Di bidang teknik sipil, surveying memainkan peranan penting selama dan
sesudah tahap perencanaan, dan pada tahap pelaksanaan konstruksi dalam berbagai
proyek jalan raya, jalan rel, gedung, perumahan, jembatan, terowongan, irigasi,
bendungan, pekerjaan pipa, dll.
Jenis
survai
Ada beberapa jenis survai yang masing-masing jenis mempunyai
kekhususan tersendiri terutama dalam hal maksud dan tujuannya. Dari tujuan
survai akan dapat ditentukan mengenai metode pelaksanaan, ketelitian atau
toleransi yang diperbolehkan, dan jenis alat yang akan digunakan.
Jenis
survai ini antara lain: (a) 'control survey' yaitu penentuan titik
kontrol horisontal dan vertikal yang berguna sebagai kerangka acuan untuk
pengukuran lain; (b) 'property survey' atau 'cadastral survey' yaitu
pengukuran batas pemilikan dan luas persil tanah; (c) 'topographic survey'
yaitu survai untuk pembuatan peta yang menggambarkan kenampakan alamiah dan
buatan serta 4ketinggian tanahnya; (d) 'construction survey' atau
'engineering survey' yaitu menetapkan titik-titik dan elevasi untuk bangunan;
(e) 'route survey' yaitu survai untuk proyek jalan raya, jalan rel,
jalur pipa, jalur listrik, saluran, dll.; (f) 'hydrographic survey'
yaitu pembuatan peta garis pantai dan kedalaman danau, sungai, waduk, dan massa
air lainnya; (g) 'photogrammetric surveying' yaitu pengukuran melalui
media foto atau citra yang direkam oleh kamera atau sensor lainnya dari pesawat
udara atau satelit.
Arti
dan jenis peta
Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada bidang
datar yang digambarkan dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Sistem
proyeksi ini diperlukan karena permukaan bumi berbentuk lengkung, sedangkan
permukaan peta merupakan bidang datar. Dengan demikian setiap peta sebenarnya
mengandung distorsi.
Bidang proyeksi yang digunakan dalam proyeksi peta adalah
bidang-bidang yang bisa didatarkan yaitu kerucut, silinder dan bidang datar.
Ilmu ukur tanah menganggap bahwa bidang permukaan bumi berbentuk datar, kerena
itu bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar dan dengan sistem (garis
proyeksi saling sejajar), dan posisi titik-titik digambarkan dengan sistem
koordinat tegaklurus ().
Skala selalu dicantumkan didalam peta dan merupakan informasi
yang sangat penting guna mengetahui gambaran sebenarnya dilapangan. Skala
adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak di lapangan, dan cara
penulisannnya dapat dengan cara menuliskan perbandingan angka yang disebut skala
angka (numerical scale), atau dengan cara grafik yang disebut skala
grafik (graphical scale). Skala angka dapat dibagi dalam dua jenis yaitu:
(a) 'Engineer's scale' yaitu pernyataan 1 cm di peta menggambarkan
berapa meter di lapangan, misalnya: 1 cm = 10 m; (b) 'Fraction scale'
yang menyatakan perbandingan jarak di peta dan di lapangan dalam satuan yang
sama, misalnya: 1:500, 1:1.000.
Peta
bisa dibagi dalam dua bagian umum yaitu peta planimetri dan peta
topografi. Peta planimetri menggambarkan kenampakan alami dan buatan
seperti sungai , danau, batas-batas, sawah, jalan, pemukiman, dll. Sedangkan
peta topografi selain menggambarkan kenampakan alami dan buatan manusia, juga
menggambarkan keadaan relief atau tinggi-rendah permukaan tanah. (Anderson,
1985).
Peta yang menyangkut daerah luas seperti negara dan
menggambarkan kota, sungai, danau, dan batas administrasi pemerintahan disebut peta
geografi. Selain itu ada lagi jenis peta yang menggambarkan obyek-obyek
tertentu atau dengan kata lain mempunyai tema tertentu seperti peta irigasi
yang menggambarkan jaringan irigasi yang ada, peta pariwisata yang
menggambarkan obyek-obyek wisata yang ada. Peta jenis ini yang merupakan peta dengan
tema khusus disebut peta tematik.
Peta dapat digolongkan pula dalam: (a) peta garis ('line-drawn
map') yaitu peta yang digambarkan dengan simbol garis, dan (b) peta foto
('pictorial map') yaitu peta yang dihasilkan dari foto udara atau
foto satelit.
Bila
ditinjau dari jenis survainya, peta dapat dikelompokkan dalam: (a) peta
topografi, (b) peta kadaster, (c) peta enjiniring, (d) foto udara. Peta
kadaster adalah peta planimetri yang terutama menggambarkan batas-batas
pemilikan lahan, batas-batas pemerintahan dan kenampakan penting lainnya
seperti: jalan, sungai, dan lain-lain, dan biasanya digambar dengan skala
besar. Peta enjiniring merupakan peta kerja yang dipersiapkan untuk proyek
enjiniring yang biasa digunakan pada tahap perencanaan, disain, ataupun pada
tahap konstruksi. Peta enjiniring biasa digambar dengan skala besar, ketelitian
tinggi, garis kontur dan menggambarkan batas-batas pemilikan tanah dan obyek
atau kenampakan yang penting.
Sumber : MK.Dasar Pemetaan Jurusan
Teknik Sipil FTSP-USAKTI
KAPASITAS KERJA PENGOLAHAN TANAH 24 Aug 2021 1:12 AM (3 years ago)

Yang dimaksud dengan kapasitas kerja adalah kemampuan kerja suatu alat atau mesin memperbaiki
hasil (hektar, kg, lt) per satuan waktu. Jadi kapasitas kerja pengolahan tanah adalah berapa hektar kemampuan suatu alat dalam mengolah tanah per satuan waktu.
Sehingga satuannya adalah hektar per jam atau jam per hektar atau hektar
per jam per HP traktor. Kapasitas kerja suatu alat pengolahan tanah dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu:
1.
Ukuran dan bentuk
petakan
2.
Topografi wilayah
: datar, bergelombang atau berbukit,
3.
Keadaan traktor :
lama dan baru
4.
Keadaan vegetasi
(tumbuhan yang ada) dipermukaan tanah : alang-alang atau
semak belukar
5.
Keadaan tanah :
kering, basah, atau lembap, liat atau berlempung, atau keras
6.
Tingkat
keterampilan operator : sudah berpengalaman, terampil atau belum
berpengalaman
7.
Pola
pengolahan tanah : pola spiral, pola tepi, pola tengah, dan pola alfa.
Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kapasitas
kerja alat adalah:
1.
Ukuran dan bentuk
petakan: Ukuran dan atau bentuk petakan sangat mempengaruhi efisiensi kerja
dari pengolahan tanah yang dilakukan dengan tenaga tarik hewan ataupun dengan
traktor. Dengan pengaruhnya terhadap pencangkulan tidak begitu besar. Ukuran
petakan yang sempit akan mempersulit beloknya hewan penarik atau traktor,
sehingga efisiensi kerja dan kapasitas kerjanya rendah. Untuk mencapai
efisiensi kerja dan kapasitas yang tinggi, maka ukuran luas petakan harus
disesuaikan dengan tenaga penarik yang digunakan.
2.
Topografi wilayah:
Keadaan topografi wilayah meliputi keadaan permukaan tanah dalam wilayah secara
keseluruhan. Misalnya keadaan permukaan wilayah tersebut datar atau berbukit
atau bergelombang. Keadaan ini diukur dengan tingkat kemiringan dari permukaan
tanah yang dinyatakan dalam (%). Kemiringan yang baik untuk penggunaan tenaga
hewan dan traktor dalam pengolahan tanah adalah sampai 3 persen (relatif
datar). Kemirngan tanah yang lebih dari 3 persen yang masih bisa dikerjakan tractor
adalah 3 sampai 8 persen dimana pengolahan tanahnya dilakukan dangan mengikuti
garis ketinggian (contour farming system ). Bagi daerah yang berbukit-burkit
diamana bentuk petakan yang tidak teratur dan luasnya yang kecil, maka cangkul
sangat cocok untuk daerah ini. Pola terahir ini disebut dengan sistem
penterasan, dimana sawah-sawah berbentuk teras-teras yang mengikuti garis
ketinggian. Bentuk petakan teratur akan memudahkan pekerjaan pekerjaan
pengolahan tanah sehingga efisiensinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan
yang tidak teratur.
3.
Keadaan traktor:
Keadaan traktor juga akan dipengaruhi kapasitas kerja pengolahan tanah. Keadaan
traktor disini berarti apakah traktor masih baru atau sudah lama. Jadi
menyangkut umur ekonomi traktor itu sendiri. Traktortraktor sudah lama dipakai
berarti umur ekonominya sudah habis atau malah sudah terlewatkan, sehingga
sudah banyak bagian traktor yang sudah aus sehingga sering timbul kerusakan.
Kerusakan–kerusakan akan menyangkut masalah waktu, tenaga serta biaya. Sehingga
pekerjaan tidak akan efisien lagi.
4.
Keadaan vegetasi:
Keadaan vegetasi permukaan tanah yang diolah juga dapat mempengaruhi
efektivitas kerja dari bajak atau garu yang digunakan. Tumbuhan semak atau
alang-alang memungkinkan kemacetan akibat penggumpalan pada alat karena
tertarik atau tidak terpotong. Pengolahan tanah pada alang-alang atau bersemak
akan lebih efektif bila digunakan bajak piringan atau garu piring. Karena bajak
atau garu ini memiliki konstruksi yang berupa piringan dan dapat berputar
sehingga kecil kemungkinan untuk macet.
5.
Keadaan tanah:
Keadaan tanah meliputi sifat-sifat fisik tanah, yaitu keadaan basah (sawah),
kering, berlempung, liat atau keras. Keadaan ini menentukan jenis alat dan
tenaga penarik yang digunakan. Disamping itu juga mempengaruhi kapasitas kerja
dari pengolahan tanah. Tanah yang basah memberikan tahanan tanah terhadap
tenaga penarik relatif lebih rendah dibanding dengan tanah kering. Akan tetapi
pada tanah basah (sawah) memungkinkan terjadi slip yang lebih tinggi
dibandingkan pada tanah kering. Penggunaan traktor tanah pada tanah sawah dan
tanah kering biasanya digunakan roda besi tambahan pada kedua rodanya agar
dapat memperkecil slip roda yang terjadi. Akhir-akhir ini IRRI Filipina (International
Rice Research Institute ) telah mengembangkan traktor dengan kedua rodanya terbuat
dari besi yang terdiri dari lempeng-lempeng besi yang khususdirancang untuk
pengolahan tanah sawah. Demikian juga traktor 4 roda, bila digunakan pada tanah
sawah kedua roda belakangnya dipasang roda besi tambahan guna memperkecil slip
rodanya. Bajak piring atau garu piring lebih efektif bekerja pada tanah kering
dibanding pada tanah basah. Sedangkan bajak singkal lebih efektif bila
digunakan pada tanah yang basah, agak liat dibanding pada tanah kering.
6.
Tingkat
keterampilan operator: operator yang berpengalaman dan terampil akan memberikan
hasil kerja dan efisiensi kerja yang lebih baik dibanding operator yang belum
terampil dan belum berpengalaman. Oleh karena itu dalam penggunaan traktor
untuk pengolahan tanah, perlu terlebih dahulu memberikan latihan terampil
kepada operator yang menjalankannya. Usaha ini untuk memberikan hasil pekerjaan
yang lebih efisien dan lebih efektif.
7.
Pola pengolahan
tanah: Pola pengolahan tanah erat hubungannya dengan waktu yang hilang karena
belokan selama pengolahan tanah. Pola pengolahan harus dipilih dengan tujuan
untuk memperkecil sebanyak mungkin pengangkatan alat. Karena pada waktu
diangkat alat itu tidak bekerja. Oleh karena itu harus diusahakan bajak atau
garu tetap bekerja selama waktu operasi dilapangan. Makin banyak pengangkatan
alat pada waktu belok, makin rendah efisiensi kerjanya. Pola pengolahan tanah
yang banyak dikenal dan dilakukan adalah pola spiral, pola tepi, pola tengah
dan pola alfa (pada gambar 28). Pola spiral yang paling banyak digunakan karena
pembajakan dilakukan terus menerus tampa pengangkatan alat. Dari uraian dimuka
jelas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang disebutkan tadi sangat besar pengaruhnya
terhadap kapasitas kerja pengolahan tanah. Oleh karena itu, dalam rencana
melaksanakan pembukaan lahan atau pencetakan sawah keenam faktor tersebut harus
dipertimbangkan dan diperhatikan. Pada tabel 1. berikut ini diberikan beberapa
kasus kapasitas kerja pengolahan tanah menurut jenis alat penarik. Satuan
kapasitas kerja pada Tabel ini adalah hektar per jam per Hp traktor untuk
tenaga penarik dan hektar per musim untuk tenaga ternak.
Dengan menggunakan
angka kapasitas kerja (Ha/Jam/Hp) dapat ditentukan kapasitas kerja dari suatu
traktor yang diketahui tenaga mesinnya. Misalnya terdapat suatu unit traktor
tangan dengan tenaga mesinnya 8 HP dan bajaknya adalah bajak rotary. Jika traktor
ini mengolah tanah sawah sebanyak 2 kali bajak sampai siap tanam, maka kapasitas
kerja (Ha/jam) adalah :
8 Hp x 0,007
Ha/jam Hp = 0,056 Ha/jam
Sumber referensi :
MK.Mekanisasi Pertanian (Zulfikar, S.P., M.P)
PERENCANAAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR 24 Aug 2021 12:51 AM (3 years ago)

DEFINISI
IRIGASI
Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara
pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan
untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.
Secara alamiah :
1.
Secara
alamiah air disuplai kepada tanaman melalui air hujan.
2.
Cara
alamiah lainnya, adalah melalui genangan air akibat banjir dari sungai, yang
akan menggenangi suatu daerah selama musim hujan, sehingga tanah yang ada dapat
siap ditanami pada musim kemarau.
Secara buatan :
Ketika penggunaan air ini mengikutkan pekerjaan rekayasa
teknik dalam skala yang cukup besar, maka hal tersebut disebut irigasi buatan (Artificial Irrigation).
Irigasi buatan secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua)
bagian, yaitu :
1.
Irigasi
Pompa (Lift Irrigation), dimana air
diangkat dari sumber air yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, baik secara
mekanis maupun manual.
2.
Irigasi
Aliran (Flow Irrigation), dimana air
dialirkan ke lahan pertanian secara gravitasi dari sumber pengambilan air.
TUJUAN dan
MANFAAT IRIGASI
Tujuan Irigasi.
Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan
irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaaan dan
pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah
yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis.
Manfaat Irigasi.
Adapun manfaat dari suatu sistem irigasi,
adalah :
a.
Untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah yang curah
hujannya kurang atau tidak menentu.
b. Untuk mengatur pembasahan tanah, agar daerah
pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim
kemarau maupun musim penghujan.
c.
Untuk menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur
dan zat-zat hara penyubur tanaman pada
daerah pertanian tersebut, sehingga tanah menjadi subur.
d. Untuk kolmatase, yaitu meninggikan tanah yang
rendah / rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi.
e.
Untuk pengelontoran air , yaitu dengan mengunakan air irigasi, maka kotoran
/ pencemaran / limbah / sampah yang terkandung di permukaan tanah dapat
digelontor ketempat yang telah disediakan (saluran drainase) untuk diproses
penjernihan secara teknis atau alamiah.
f.
Pada daerah dingin, dengan mengalirkan air yang suhunya lebih tinggi
dari pada tanah, sehingga dimungkinkan untuk mengadakan proses pertanian pada
musim tersebut.
KELEBIHAN
IRIGASI
Kelebihan dari pada dibangunannya suatu sistem irigasi
dan bangunan-nya, secara umum adalah sebagai berikut :
a. Mengatasi kekurangan pangan.
b. Meningkatkan produksi dan nilai jual
hasil tanaman.
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Pembangkit Tenaga Listrik.
e. Transportasi Air (Inland Navigation).
f. Efek terhadap Kesehatan.
g. Supply Air Baku.
h. Peningkatan Komunikasi / Transportasi.
Flowchart Perencanaan
Jaringan Irigasi
PERENCANAAN PETAK
Ada dua jenis petak yang akan dialiri yaitu petak
tersier sebanyak 5 petak dan petak sekunder sebanyak 3 petak.
2.1 Petak Tersier
Petak
tersier yang kami bangun adalah sebanyak 5 petak sawah dengan perencanaan sebagai berikut :
1) Ukuran
luas petak masing – masing yaitu , 113,462
Ha, 54,869 Ha, 128,803 Ha, 57,365 Ha dan 100,439 Ha.
2) Letak
petak berada dibelakang pintu sadap dan hanya menerima air dari bangunan sadap.
3) Rencana
petak secara keseluruhan dapat mudah untuk dialiri air dan mudah pula air
buangan mengalir ke saluran drainasi.
4) Bentuk
petaknya tidak sama antara lebar dan panjangnya.
2.1 Petak
Sekunder
Petak
sekunder yang kami bangun adalah sebanyak 3 petak sawah dengan perencanaan sebagai berikut :
1) Ukuran
luas petak masing – masing yaitu , 97,059
Ha, 62,112 Ha, dan 59,828 Ha.
2) Setiap
petak sekunder hanya menerima air dari
satu bangunan bagi yang terletak di
saluran induk atau saluran sekunder lainnya, serta tidak mendapat air suplesi
dari saluran lain.
3) Rencana
saluran sekunder terletak melalui punggung, untuk memudahkan mengalirnya air
irigasi ke sebelah kanan dan kiri, dan air dapat mengairi keseluruh daerah yang
akan diairi.
Gambar
2.1 Denah petak sawah beserta keterangan
Dimana
:
-
Petak sawah 1 = petak
sekunder 1
-
Petak sawah 2 = petak
sekunder 2
-
Petak sawah 3 = petak
sekunder 3
-
Petak sawah 4 = petak
tersier 1
-
Petak sawah 5 = petak
tersier 2
-
Petak sawah 6 = petak
tersier 3
-
Petak sawah 7 = petak
tersier 4
-
Petak sawah 8 = petak
tersier 5
PERENCANAAN DEBIT SALURAN
Mencari Debit air irigasi
di setiap petak sawah :
Untuk
menghitung besarnya debit air yang dibutuhkan untuk setiap petak, data yang
dibutuhkan adalah data luas (A) dari masing-masing petak dan besarnya kebutuhan
air semua petak sawah (Ir). Dimana diketahui nilai kebutuhan air semua petak
sawah (Ir) = 1,38 lt/dt.ha
Rumus
untuk mencari debit air pada petak sawah yaitu:
|
Qsawah
= A . Ir |
Dimana :
Qsawah =
kebutuhan air / debit air irigasi di petak sawah
A =
luas petak sawah yang aliri
Ir = kebutuhan air irigasi di tiap petak sawah
Tabel 2.1.
Kebutuhan air irigasi di setiap petak sawah
|
SAWAH |
A
(Ha) |
Q
(lt/dtk) |
Q
(m3/dtk) |
|
1 |
107,834 |
148,824 |
0,148824 |
|
2 |
69,013 |
95,238 |
0,095238 |
|
3 |
66,475 |
91,736 |
0,091736 |
|
4 |
126,069 |
195,722 |
0,195722 |
|
5 |
63,739 |
98,955 |
0,098955 |
|
6 |
60,695 |
94,649 |
0,094649 |
|
7 |
143,114 |
222,185 |
0,222185 |
|
8 |
111,599 |
173,257 |
0,173257 |
Untuk menghitung besarnya debit
air yang mengalir pada setiap saluran
irigasi data yang dibutuhkan yaitu nilai efisiensi (e) dan debit air yang
mengalir pada tiap petak (Qp). Untuk efisiensi debit saluran irigasi dipakai
standar efisiensi debit saluran atau factor kehilangan, yaitu :
1.
Pada petak tersier, e =
0,8
2.
Pada saluran sekunder, e
= 0,9
3.
Pada saluran primer, e =
0,9
Rumus
mencari debit air (Qs) untuk tiap saluran irigasi yaitu :
|
Qs = Qp/e |
Contoh Perhitungan:
Debit Aliran Irigasi di
Saluran Sekunder 6
Luas
Sawah petak tersier 5 : 111,599 ha
A = 111,599 x 90% =
100,439 ha
Efisiensi Tersier = 0,8
Efisiensi Sekunder = 0,9
Ir
= 1,38
Q = (100,439 x 1,38 ) / 0,8
= 173, 257 lt/det
Q
saluran Sekunder = Q tersier / 0,9
=
Data
perhitungan debit air pada setiap saluran irigasi dapat dilihat pada Tabel 2.2
Tabel 2.2 Debit aliran air irigasi di setiap saluran
|
Saluran |
Nilai Efisiensi (e) |
Q (m³/det) |
|
Primer 1 |
0,9 |
0,12348 |
|
Primer 2 |
0,9 |
0,9637 |
|
Primer 3 |
0,9 |
0,87196 |
|
Sekunder 1 |
0,9 |
0,14882 |
|
Sekunder 2 |
0,9 |
0,09524 |
|
Sekunder 3 |
0,9 |
0,09174 |
|
Sekunder 4 |
0,9 |
0,54933 |
|
Sekunder 5 |
0,9 |
0,30246 |
|
Sekunder 6 |
0,9 |
0,19251 |
|
Tersier 1 |
0,8 |
0,19572 |
|
Tersier 2 |
0,8 |
0,09465 |
|
Tersier 3 |
0,8 |
0,22219 |
|
Tersier 4 |
0,8 |
0,09896 |
|
Tersier 5 |
0,8 |
0,17326 |
PERENCANAAN PENAMPANG SALURAN
Didalam perhitungan dimensi suatu
saluran baik itu saluran pembawa (saluran primer, sekunder, tersier dan
kwartener) maupun saluran pembuangan, pada dasarnya sama.
Rumus yang saat ini biasa digunakan adalah rumus
Strickler :
Tabel 2.3 Debit
aliran air irigasi di setiap saluran
|
Q (m3/detik) |
b : h |
Kecepatan air (v) untuk tanah lempung
biasa (m/detik) |
m |
Keterangan |
|
0,000 – 0,050 |
1,0 |
Min. 0,25 |
1:1 |
Catatan : |
|
0,050 – 0,150 |
1,0 |
0,25 – 0,30 |
1:1 |
*bmin = 0,30 m |
|
0,150 – 0,300 |
1,0 |
0,30 – 0,35 |
1:1 |
*Q = A*V |
|
0,300 – 0,400 |
1,5 |
0,35 – 0,40 |
1:1 |
Q = debit air, m3/det |
|
0,400 – 0,500 |
1,5 |
0,40 – 0,45 |
1:1 |
A = luas basah, m2 |
|
0,500 – 0,750 |
2,0 |
0,45 – 0,50 |
1:1 |
V = kecepatan air, m/det |
|
0,750 – 1,500 |
2,0 |
0,50 – 0,55 |
1:1 |
V = k*R2/3*I1/2 |
|
1,500 – 3,000 |
2,5 |
0,55 – 0,60 |
1:1,5 |
R = jari-jari hidrolis = A:O |
|
3,000 – 4,500 |
3,0 |
0,60 – 0,65 |
1:1,5 |
O = keliling basah |
|
4,500 – 6,000 |
3,5 |
0,65 – 0,70 |
1:1,5 |
I = kemiringan saluran |
|
6,000 – 7,500 |
4,0 |
0,70 |
1:1,5 |
|
|
Saluran |
K (koefisien
kekasaran) |
T (talud) |
h/b |
W (waking-jagaan) |
Lahar Tanggul-tanggul |
|
Tersier-kuartier |
40 |
1:1 |
1 |
0,30 |
1,00 |
|
Sekunder Q
= 0,50 m3/det |
40 |
1:1 |
1 |
0,40 |
1,00 |
|
Primer + sekunder |
|||||
|
Q
= 0,5 – 1 m3/det |
40 |
1:1 |
2 |
0,50 |
1,50 |
|
Q
= 1 - 2 m3/det |
40 |
1:1 |
2,5 |
0,60 |
1,50 |
Menghitung Perencanaan Bangunan Pintu Air Irigasi
|
Lebar Meja (m) |
Tinggi
Energi (m) |
Besar
Debit (m³/det) |
|
0,50 |
0,33 |
0,00-0,16 |
|
0,50 |
0,50 |
0,03-0,30 |
|
0,75 |
0,50 |
0,04-0,45 |
|
1,00 |
0,50 |
0,05-0,60 |
|
1,25 |
0,50 |
0,07-0,75 |
|
1,50 |
0,50 |
0,08-0,90 |
Contoh Perhitungan:
1. Saluran
Primer 1 dengan Pintu Romijn
Untuk
Perencanaan dibatasi dengan syarat teknis sebagai berikut:
·
Untuk satu pintu biasa
diambil :
-
Lebar pintu (b) =
1.5 m
-
Qmaks =
1,23488 m3/dtk
-
Hmaks (tinggi muka air
diatas ambang) = 0.5 m
Maka :
Jika diambil 1
pintu :
Q = 1,71*b*h3/2 à
b = 1.5 m
1,23488 = 1,71*(0.5)*h3/2
h = (1,23488/(1,71*1.5))2/3
= 0,614 m
h = 0,614 m ≥ hmaks = 0,5 m
(No OK à Tidak memenuhi syarat)
Jika
diambil 2 pintu :
Q = Q/2 = 1,23488/2 = 0,61744
m3/dtk
Dicoba
dengan tinggi muka air (h) = 0,5 m
Q = 1,71*b*h3/2 à
h = 0,5 m
0,61744 = 1,71*b*0,53/2
b = 1,02 m à
diamil b = 1,1 m < b mks = 1,5 m àoke
Dicek
:
·
Tinggi h :
Q = 1,71*b*h3/2 à
b = 1,1 m
0,61744 = 1,71*1,1*h3/2
h =
0,476 < h maks =0,5 m àoke
·
Debit : Q =
1,71*(1,1)*(0.5)3/2
= 0.665034 m3/dtk >
0,61744 m3/dtk àOK
Untuk
2 pintu
Q
= 2 * 0.665034 = 1,330068 > 1,23488 m3/dtk àOK
Jadi, dimensi pintu air untuk saluran saluran Primer 1
adalah :
|
Dua buah pintu romijn dengan ketentuan masing-masing
pintu: Lebar pintu (b) = 1,1 m Qmak = 1,23488 m3/dtk Tinggi muka air diatas
ambang (h maks) = 0,5 m |
2. Saluran
Sekunder 1 dengan Pintu Romijn adalah sbb :
Rumus
Pintu Romijn :
Q
= 1,71 * b*
Untuk
Perencanaan dibatasi dengan syarat teknis sbb:
·
Untuk satu pintu biasa
diambil :
-
Lebar pintu (b) =
0.5 m
-
Qmaks =
0.148824.m3/dtk
-
Hmaks (tinggi muka air
diatas ambang) = 0.33 m
Maka :
Jika diambil 1
pintu :
Q =
1,71*b*h3/2 à
b = 0.5 m
0.148824 = 1,71*(0.5)*h3/2
h =
(0.148824/(1,71*0.5))2/3
=
0.312 m
h =
0.312 m ≤ hmaks = 0.33 m (OK à
ambil 1 pintu)
h
~ 0,32
dicek
: untuk 1 pintu :
·
Debit : Q = 1,71*(0.5)*(0.32)3/2
= 0.1620828351 m3/dtk
> 0.154771532 m3/dtk àOK
Jadi,
dimensi pintu air untuk saluran saluran sekunder 1 adalah :
|
Satu buah pintu romijn dengan ketentuan : Lebar pintu (b) = 0,5 m Qmak = 0,16208 m3/dtk Tinggi muka air diatas
ambang (h maks) = 0,32 |
*Perhitungan pintu
air untuk saluran yang lainnya sama seperti diatas, dan hasil perhitungan dapat
dilihat pada Tabel 4.5
Tabel
4.5 Perencanaan Dimensi Bangunan Pintu Air Irigasi
|
Saluran |
Q (m³) |
B (m) |
H |
Cek Debit |
||
|
Hitung |
Rencana |
Qpasang |
Ket |
|||
|
Primer 1 |
1.23488 |
1.1 |
0.476 |
0.5 |
1.33007 |
Ok ( 2 pintu) |
|
Primer 2 |
0.9637 |
1.1 |
0.521 |
0.4 |
1.19210 |
Ok ( 2 pintu) |
|
Primer 3 |
0.87196 |
1.5 |
0.487 |
0.4 |
0.90686 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder 1 |
0.14882 |
0.5 |
0.312 |
0.32 |
0.15477 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder
2 |
0.09524 |
0.5 |
0.232 |
0.3 |
0.14049 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder 3 |
0.09174 |
0.5 |
0.226 |
0.3 |
0.14049 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder 4 |
0.54933 |
1 |
0.469 |
0.5 |
0.60457 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder 5 |
0.30246 |
1 |
0.315 |
0.4 |
0.43260 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sekunder 6 |
0.19251 |
0.5 |
0.37 |
0.4 |
0.21630 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Tersier 1 |
0.19572 |
0.5 |
0.37 |
0.3 |
0.21630 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Tersier 2 |
0.09465 |
0.5 |
0.231 |
0.3 |
0.14049 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Tersier 3 |
0.22219 |
0.5 |
0.407 |
0.5 |
0.30229 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Tersier 4 |
0.09896 |
0.5 |
0.237 |
0.3 |
0.14049 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Tersier 5 |
0.17326 |
0.5 |
0.345 |
0.4 |
0.21630 |
Ok ( 1 pintu) |
|
Sumber Referensi : YOGI OKTOPIANTO ( Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma, 2011) |
Falsafah Bajak dan Cangkul 23 Aug 2021 7:45 AM (3 years ago)

Penulis dan pujangga dahulu kala banyak menuliskan karyanya dalam bentuk sandi atau
simbolis yang mana isi dan maksud yang terkandung di dalam hati serta sanubarinya diekspresikan dalam bentuk cerita yang berupa sanepa atau lambang yang nantinya kesemuanya diserahkan kepada para pembaca atau pemerhati untuk menafsirkan tentang makna atau artinya. Lebihlebih para penulis dan pujangga yang menuliskan karyanya di dalam bahasa Jawa, mereka lebih pandai lagi dalam olah sandi.
Harus diingat dan disadari bahwa menulis dan membuat cerita dalam bentuk sandi
adalah merupakan suatu seni, apalagi tulisan atau cerita sandi ini memang
membutuhkan suatu energi yang ekstra karena karya ini bersifat ganda atau
berlipat (reflection on reflection). Dalam artikel ini akan dikemukakan
pendapat pakar syariah yaitu Umar Hisyam (1974) dalam bukunya Sunan Kalijaga
tentang Falsafah Cangkul dan Bajak.
Lebih lanjut menurutnya, pada suatu hari Sunan Kalijaga sedang berjalan-jalan
bersama-sama dengan muridnya melewati beberapa hutan kecil dan sawah ladang
pada daerah Kadilangu, Demak, yaitu suatu daerah di mana beliau berdomisili dan
berada.
Di dalam perjalanan itu beliau menjumpai seorang petani yang sedang bekerja
menggarap sawahnya, lalu Sunan Kalijaga bertanya:
"Dengan apa kau mengerjakan sawahmu itu, Pak?"
"Dengan linggis tuanku" jawab petani.
"Berapa lama kamu dapat menyelesaikan satu petak sawah?"
"Sepuluh hari tuan".
"Begitu lama sekali", jawab Sunan Kalijaga sambil mengerutkan
keningnya tanda berfikir keras dan sangat iba akan perjuangan petani tersebut,
sesaat kemudian Sunan Kalijaga berkata:
"Kalau kamu mau Pak, ajaklah kawan-kawanmu bertandang ke rumahku, nanti
akan kuberi alat-alat pertanian, supaya kamu sekalian bisa dengan cepat
menyelesaikan pekerjaanmu dalam menggarap sawah yang satu harinya bisa
menyelesaikan satu petak sawah".
Beberapa hari kemudian setelah berembuk / bermufakat maka masyarakat
berbondong-bondong ke tempat Sunan Kalijaga dan di sana Sunan Kalijaga meminta
waktu untuk mengheningkan cipta serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau
berupaya minta pertolongan agar rakyat seluruhnya mendapat jalan yang cepat dan
terbaik di dalam mengerjakan sawahnya. Dalam sekejap saja terciptalah
beribu-ribu alat pertanian antara lain cangkul dan bajak, kemudian alat itu
dibagi-bagikan kepada para petani.
Akhirnya Sunan Kalijaga menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan menjadi
buah bibir di seluruh pelosok desa dan kampung se kabupaten Demak, bahkan
sebagai ilustrasi murid dan pengikutnya makin banyak pula yang berasal dari
daerah sana.
Dari cerita sandi di atas mari kita berenung sejenak untuk menafsirkan
makna bajak dan cangkul yaitu:
1. Bajak
Terdiri dari beberapa bagian yang kesemuanya itu mempunyai makna-makna
tersendiri, yaitu:
a. Pegangan
Penafsiran yang bisa disampaikan bahwa kepada kita di dalam usaha mencapai
cita-cita hidup ini, manusia haruslah mempunyai pegangan dan pedoman hidup atau
dasar falsafah hidup yang kuat, agar tidak mudah digoda atau diombang-ambingkan
suasana atau dengan kata lain mempunyai ketenangan jiwa dan stabil.
b. Pancadan
Berasal dari kata mancad = bertindak. Artinya, bila manusia telah mengetahui
akan pedoman-pedoman hidup di atas tadi, haruslah mereka berbuat yang sesuai
dengan ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu hendaknya diamalkan, bila tidak, maka
tidak akan bisa mencapai cita-cita hidup yang telah didambakan dengan kata lain
tidak akan mendapat keberkahan.
c. Tanding
Artinya membanding-bandingkan. Walaupun telah memiliki, mengetahui atau
mempunyai ilmu tinggi, janganlah kita fanatik buta. Berlapang dadalah,
yaitu dengan cara memperbandingkan atau mengujinya serta belajar lagi dan
mengikuti perkembangannya karena tidak ada kehidupan yang statis tapi dinamis.
d. Singkal
Berasal dari bahasa Jawa yang berarti sugih atau kaya akan akal fikiran. Bila
kita pandai akan bisa dan piawai membandingkan antara satu dengan yang lain,
maka akan memperofeh ilmu dan pengalaman hidup yang sangat briliant.
e.
Kejen
Dari kata ke-ijen, kepada satu, hanya untuk satu, yaitu satu pikiran yang
dipusatkan kepada satu tujuan, yakni cita-cita hidup manusia untuk bisa
dicapai masyarakat adil dan makmur.
f. Olang-aling
Rintangan, artinya segala sesuatu yang menuju kebaikan dan keutamaan pasti
mengalami rintangan akan tetapi semua bisa dilalui dengan selamat sentosa.
g. Racuk
Berarti ke arah pucuk, yaitu setelah rintangan-rintangan dapat diatasi, maka
masyarakat sampailah pada cita-cita mulia yaitu adil dan makmur serta
tentram.
2. Cangkul
Terdiri dari tiga bagian, yakni: pacul, bawak dan doran.
a. Pacul
Adapun makna atau tafsiran yang terkandung dari pacul yaitu sebagai berikut:
Ngipatake prakara kang muncul, artinya melemparkan segala sesuatu yang nongol
ke permukaan, segala sesuatu yang tidak beres, segala sesuatu yang
menonjol yang tidak benar dan mengganggu dalam kehidupan harus dihilangkan dan
dihindarkan supaya mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram.
b. Bawak
Obahing awak, artinya bergeraknya anggota badan. Di dalam mencapai cita-cita
manusia haruslah rajin. Obahing awak artinya bekerja giat dan rajin, tidak
hanya menanti taqdir saja, tetapi hendaknya dengan usaha yang nyata, artinya
dengan segala ikhtiar. Penulis ingatkan kepada kita seluruhnya bahwa
"usaha tanpa doa adalah takabur dan doa tanpa usaha adalah sia-sia".
c. Doran
Ndedonga marang Pangeran, artinya memohon kepada Tuhan. Agar mencapai ke arah
cita-cita, juga dengan jalan berdoa kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah
tempat segala meminta pertolongan dan siapapun kita dan apapun pangkat kita,
akhirnya Tuhan jualah yang menentukan.
Berdasarkan falsafah di atas yang sudah dituliskan oleh para penulis pendahulu
kita, maka penulis juga akan ingatkan karya pujangga Raden Ngabehi
Ronggowarsito yang dianggap dan terkenal sebagai ramalan Jayabaya pada bait
sebagai berikut:
Amenangi
zaman edan
Ewuh aya ing pambudi
Milu edan ora tahan
Yen ora milu anglakoni
Boya kaduman melik, kaliran
weksanipun
Ndilalah karsa Allah
Begja-begjane kanglali
Luwih begja kang eling Ian
waspada
Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:
Hidup di jaman gila
Memang susah
Mencoba ikut tidak sampai
hati
Malau tidak mengikuti
Tak memperoleh apapun,
akhirnya menderita kelaparan
Namun sudah menjadi
kehendak Yang Maha Kuasa
Meskipun yang lupa hidup
makmur
Masih lebih bahagia yang
senantiasa ingat dan waspada
Itulah yang bisa penulis sampaikan terutama buat diri kami semoga bisa
bermanfaat dan menambah nuansa kita mengenang falsafah dan sejarah bangsa kita
sendiri dewasa ini.
Oleh : Ir. Dasril Munir, MM dan
Didit Eko Setiawan, ST.
Penulis adalah auditor
Itjen DKP
Sumber: Majalah Sinergi,
2005
Perbedaaan Agriculture versus Agribisnis 19 Aug 2021 6:17 AM (3 years ago)
Berdasarkan sejarah perkembangannya pertanian dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan yaitu :
1.
Pemburu dan pengumpul. Manusia
pertama hidup di daerah hutan tropik di sekitar laut Cina Selatan yaitu bangsa
Alitik (prapaleolitik) yang merupakan kelompok manusia pengumpul makanan dan
berburu serta menangkap ikan.
2.
Pertanian Primitif .Ketika manusia
pengumpul dan berburu mulai berusaha menjaga bahan makanan maka mulai terjadi
suatu mata rantai antara periode pengumpul dan berburu dengan pertanian
primitif.
3.
Pertanian tradisional orang menerima
keadaan tanah, curah hujan, dan varietas tanaman sebagaimana adanya dan
sebagaimana yang diberikan alam. Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya
sekedarnya sampai tingkat tertentu seperti pengairan, penyiangan, dan
melindungi tanaman dari gangguan binatang liar dengan cara yang diturunkan oleh
nenek moyangnya.
4.
Pertanian Progresif (Modern). Manusia
mengguanakan otaknya untuk meningkatkan penguasaannya terhadap semua yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman dan hewan.
Pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan
aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari
itu, pertanian/agrikultur adalah sebuah cara hidup (way of life atau livehood)
bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai
sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani, sebagai pelaku
sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus,
melainkan juga sebagai homo socius dan homo religius.
Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya
unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan
sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan
sistem pertanian.
Paradigma agribisnis yang dikembangkan oleh Davies dan
Goldberg, yang berdasar pada lima premis dasar agribisnis.
1.
Pertama, adalah suatu kebenaran umum
bahwa semua usaha pertanian berorientasi laba (profit oriented), termasuk di
Indonesia.
2.
Kedua, pertanian adalah komponen
rantai dalam sistem komoditi, sehingga kinerjanya ditentukan oleh kinerja
sistem komoditi secara keseluruhan.
3.
Ketiga, pendekatan sistem agribisnis
adalah formulasi kebijakan sektor pertanian yang logis, dan harus dianggap
sebagai alasan ilmiah yang positif, bukan ideologis dan normatif.
4.
Keempat, Sistem agribisnis secara
intrinsik netral terhadap semua skala usaha, dan
5.
kelima, pendekatan sistem agribisnis
khususnya ditujukan untuk negara sedang berkembang.
Perubahan dari agriculture menjadi agribisnis berarti
segala usaha produksi pertanian ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk
sekedar memenuhi kebutuhan sendiri termasuk pertanian gurem atau subsisten
sekalipun. Penggunaan sarana produksi apapun adalah untuk menghasilkan
“produksi”, termasuk penggunaan tenaga kerja keluarga, dan semua harus dihitung
dan dikombinasikan dengan teliti untuk mencapai efisiensi tertinggi.
Sepintas paradigma agribisnis memang menjanjikan
perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi para petani. Namun jika kita kaji
lebih mendalam, maka perlu ada beberapa koreksi mendasar terhadap paradigma
yang menjadi arah kebijakan tersebut.
Asumsi utama paradigma agribisnis bahwa semua tujuan
aktivitas pertanian kita adalah profit oriented sangat menyesatkan. Masih
sangat banyak petani kita yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi
komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri.
Mereka adalah petani-petani yang luas tanah dan
sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan,
seperti padi, jagung, ataupun ketela. Mencari keuntungan adalah wajar dalam
usaha pertanian, namun hal itu tidak dapat dijadikan orientasi dalam setiap
kegiatan usaha para petani. Petani kita pada umumnya lebih mengedepankan
orientasi sosial-kemasyarakatan, yang diwujudkan dengan tradisi gotong royong dalam
kegiatan mereka.
Paradigma sistem agribisnis tidak akan menjadi suatu
kebenaran umum, karena akan selalu terkait dengan paradigma dan nilai budaya
petani lokal, yang memiliki kebenaran umum tersendiri. Oleh karena itu
pemikiran sistem agribisnis yang berdasarkan prinsip positivisme sudah saatnya
kita pertanyakan kembali.
Masyarakat petani kita memiliki seperangkat sistem
nilai, falsafah, dan pandangan terhadap kehidupan (ideologi) mereka sendiri,
yang perlu digali dan dianggap sebagai potensi besar di sektor pertanian.
Sementara itu perubahan orientasi dari peningkatan produksi ke oreientasi
peningkatan pendapatan petani belum cukup jika tanpa dilandasi pada orientasi
kesejahteraan petani.
Peningkatan pendapatan tanpa diikuti dengan kebijakan
struktural pemerintah di dalam pembuatan aturan/hukum, persaingan, distribusi,
produksi dan konsumsi yang melindungi petani tidak akan mampu mengangkat
kesejahteraan petani ke tingkat yang lebih baik.
Dari sudut
pandang kelembagaan, struktur agribisnis di Indonesia untuk hampir semua
kornoditas
masih tersekat·sekat. Struktur yang
tersekat-sekat ini tentunya
menjadi
penghambat utama pembangunan
agribisnis di Indonesia.
Struktur agribisnis yang tersekat-sekat ini dicirikan oleh
beberapa hal
sebagai berikut :
1.
Pertama, subsistem
agribisnis hulu (produksi dan perdagangan sarana produksi pertanian)
dan subsistem agribisnis hilir (pengoIahan hasil pertanian dan
perdagangannya) dikuasai oleh pengusaha menengah dan besar
yang bukan
petani. Petani sepenuhnya hanya bergerak pada
subsistem
agribisnis penghasil produk primer.
2.
Kedua, antar subsistem
agribisnis
tidak ada hubungan organisasi fungsional dan hanya
diikat
oleh
hubungan pasar produk antara yang
juga
tidak
sepenuhnya
kompetitif.
3. Ketiga, adanya asosiasi pengusaha yang bersifat
horizontal dan cenderung berfungsi sebagai kartel. Berbagai asosiasi
pengusaha ini dapat ditemui
pada
subsistem agribisnis hulu maupun
subsistem agribisnis hilir.
4. Keempat, agribisnis dilayani oleh paling
sedikit lima departcmen teknis (Pertanian, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi, Koperasi dan PPK). Berbagai departemen ini tentunya memiliki visi
ataupun
mandat yang berlainan, sehingga berbagai kebijakan
yang
ditujukan pada agribisnis belum tentu integratif dan selaras
satu dengan
lainnya
dipandang dari sudut agribisnis
sebagai
suatu sistem.
Permasalahan struktural yang
dihadapi agribisnis tersebut juga berakibat pada
lemahnya daya
saing
agribisnis,
Struktur agribisnis
yang tersekatsekat dapat menciptakan masalah transmisi dan masalah
marjin ganda.
Masalah transmisi ini terjadi
dalarn berbagai bentuk, sepcrti misalnya transmisi harga
yang
tidak
sirmetris.
informasi perubahan preferensi konsumen yang
tidak
dapat
sampai dengan baik
ke arah
subsistem hulunya, serta
adanya
inkonsistensi mutu produk
sejak dari
hulu sampai
ke hilir dalam
sistem
agribisnis.
Lebih jauh
lagi,
struktur yang
tersekat-sekat menjadikan inovasi berjalan lambat disetiap subsistem agribisnis. Sedangkan marjin ganda di agribisnis terjadi
melalui praktek
penetapan harga
yang
jauh
di atas harga pada
kondisi
kompetitifnya di setiap subsistem yang tersekat·sekat tersebut.
Dampak nyata
dari
marjin
ganda
ini adalah harga pokok penjualan produk
akhir
agribisnis menjadi relatif tinggi, sehingga daya
saingnya menjadi rendah, Masalah transmisi dan masalah marjin ganda juga berdampak buruk
bagi investasi dibidang agribisnis, karena masalah tersebut dapat
menyebabkan naiknya resiko usaha.
Penataan
dan
pengembangan struktur agribisnis nasional perlu diarahkan pada dua sasaran
pokok, yaitu: Pertama, mengembangkan struktur agribisnis yang
terintegrasi secara
vertikal mengikuti aliran
produk, Struktur agribisnis yang
terintegrasi secara
vertikal ini memungkinkan subsistem agribisnis dari
hulu
sampai
hilir
dikelola dengan efisien dan
saling mendukung satu
subsistem dengan subsistem lainnya.
Kedua, mengembangkan organisasi bisnis pctani agar
mampu
mcmperoleh nilai tambah yang ada di subsistcm
hulu maupun
hilir
dari sistem ngribisnis. Secara individu petani akan sulit merebut nilai tambah
tcrsebut.
Keberhasilan pembangunan agribisnis di Indonesia ditentukan juga oleh
arah kebijakan ekonomi
makro. Pembangunan yang diarahkan pada industrialisasi yang tidak memiliki basis sumbcrdaya yang kuat, seperti industri substitusi impor, sering
melahirkan kebijakan
kebijakan makro yang
mengharnbat perkembangan agribisnis.
Pembangunan
pertanian Indonesia harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbang
pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang
paling kurang beruntung di perdesaan./***
Di
kutip dari ; Makalah ANALISIS
PERUBAHAN PARADIGMA PERTANIAN AGRIBISNIS MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN SECARA
FILSAFAT ILMU DI INDONESIA Penulis IDAWATI Program Studi Ilmu Penyuluhan
Pembangunan IPB 2016.
Peluang Bisnis Beternak Domba Bibit Unggul Untuk Ketangkasan (Domba Garut) 9 Aug 2021 6:51 AM (3 years ago)

adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut (disebut wol), daging, dan susunya. Jenis domba yang paling dikenal orang adalah domba peliharaan (Ovis aries), yang diduga keturunan dari moufflon liar dari Asia Tengah bagian Selatan dan Barat Daya. Untuk tipe lain dari domba dan kerabat dekatnya, lihat kambing antilop. Domba berbeda dengan kambing.
Domba termasuk dalam sub family Caprinae dan family Bovidae. Genus Ovis mencakup semua jenis domba, sedangkan domba domestikasi termasuk ke dalam spesies Ovis aries.
Terdapat 7 jenis domba liar yang berbeda terbagi ke dalam 40 macam varietas yang berbeda. Spesies domba yang telah mengalami domestikasi meliputi domba Argali (Ovis ammon) berasal dari Asia Tengah, domba Urial (Ovis Vignei) juga berasal dari Asia, sedangkan domba Moufflon (Ovis Musimon) berasal dari Asia Kecil dan Eropa.
Paling tidak ada tujuh spesies domba:
1. Argali, Ovis ammon
2. Domba peliharaan, Ovis aries
3. Bighorn Sheep, Ovis canadensis
4. Thinhorn Sheep, Ovis dalli
5. Mouflon, Ovis musimon
6. Domba salju, Ovis nivicola
7. Urial, Ovis orientalis
Banyaknya ras domba membuat orang biasa membagi berdasarkan kemanfaatannya:
a) domba penghasil wol
b) domba pedaging
c) domba penghasil wol sekaligus pedaging
Domba Garut
Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat dan telah dibudidayakan secara turun temurun. Domba garut merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Berdasarkan SK Kementan RI No.2914 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rumpun Domba Garut, karakteristik domba garut adalah sebagai berikut :
Sifat kualitatif (dewasa) :
1. Warna : a) tubuh dominan : kombinasi hitam-putih; b) kepala : kombinasi hitam-putih;
2. Tanduk : a) domba jantan : besar dan panjang dengan variasi bentuk melingkar atau melengkung mengarah ke depan dan ke luar; b) domba betina : bertanduk kecil atau tidak bertanduk;
3. Bentuk telinga : kecil (rumpung) dengan panjang < 4 cm sampai sedang (ngadaun hiris) dengan panjang antara 4 – 8 cm;
4. Garis muka : cembung;
5. Garis punggung : lurus sampai agak cekung;
6. Bentuk ekor : segitiga, dengan bagian pangkal lebar dan mengecil ke arah ujung (ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong);
7. Temperamen : agresif terutama pada domba jantan
Keunggulan Domba Garut
Salah satu keunggulan Domba Garut, adalah mempunyai bobot badan hidup yang cukup berat. Domba Garut jantan dewasa mempunyai bobot yakni antara 47 kg - 68 kg, sementara Domba Garut betina dewasa berkisar antara 28 kg - 45 kg. Dengan bobot hidup seberat itu, maka tentunya sangat cocok dijadikan sebagai salah satu hewan ternak pedaging.
Namun sisi keunggulan lainya dari Domba Garut adalah kemampuan dalam olah ketangkasannya. Karena memang salah satu ciri keunggulan Domba Garut adalah sebagai domba kontes (perlombaan ketangkasan)
Salah satu lokasi peternakan Domba Garut sebagai domba kontes adalah di Kp.Ciguntur Desa Cipendawa Kec.Pacet Canjur. Pak Asep sebagai pemilik peternakan sekaligus sebaga Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HP-DKI). Saat ini Pak Asep memelihara puluhan ekor domba unggul jenis Domba Garut khusus untuk domba kontes ( lomba ketangkasan).
Berbagai event lomba ketangakasan baik tingkat regional Jawa Barat maupun level nasional telah diikutinya. Salah satu domba yang dimilikinya pernah meraih Juara Umum dalam lomba ketangkasan Piala Presiden Jokowi Tahun 2019. Tak urung domba yang dimilikinya mempunyai harga yang cukup mahal yakni puluhan juta rupiah untuk setiap ekornya (antara 35 juta rupiah sampai dengan 70 juta rupiah). Tak heran domba yang dimilikinya sebagai juara kontes Piala Presiden Tahun 2019 saat ini ditaksir harganya tak kurang dari Rp. 100 juta an.
Dalam pentas ketangkasan Domba Garut ini, tidak semata mata melihat kemampuan domba dalam beradu pukulan. Akan tetapi ada beberapa kriteria penilaian Juri yang dilakukan dalam menilai seekor Domba Garut memiliki keunggulan dibanding dengan Domba Garut lainnya.
Beberapa kriteria yang dilakukan penilaian juri diantaranya adalah :
1. Kerapihan dan kebersihan bulu , serta kesehatan fisik dst
2. Corak dan warna kulit/bulu yang di miliki dst
3. Adeg - adeg/postur badan ; garis muka, garis punggung, tinggi pundak, lebar dada, bentuk /kesimetrisan tanduk, panjang badan, dst.
4. Kemampuan adu pukulan ( maksimum mampu melakukan adu pukulan sebanyak 20 kali)
5. Mental bertanding ( dilihat dari kemampuan dan karakteristik domba dalam menghadapi lawan tandingnya)
Perlu upaya yang serius dan perhatian dalam memelihara Domba Garut untuk ketangkasan ini. Salah satu yang diperhatikan Pak Asep dalam hal ini adalah menjaga keunggulan genetik domba peliharaannya.
Saat ini Pak Asep memelihara beberapa ekor domba jantan unggul baik dari keturunan Domba Garut asli maupun hasil persilangan Domba Garut dengan jenis Domba Moreno.
Beberapa domba jantan unggul ini tetap dipertahankan sebagai sumber keturunan Domba Garut Asli yang nantinya dapat dikembangbiakan dan sebagai sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
Bila anda berminat untuk mendapatkan anakan Domba Garut dengan usia kurang lebih setahun bisa diperoleh dengan kisaran harga antara 2 - 5 juta rupiah per ekor.
Contac person :
Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HP DKI)
PAK ASEP
Kp.Ciguntur Desa Cipendawa Kec.Pacet - Kab. Cianjur
HP.0838 1738 5553
By.admin/09/08/21
Penerapan Standar Prosedur Operesional (SPO) Pisang ( Tahap Panen dan Pasca Panen) 8 Aug 2021 6:55 AM (3 years ago)

Penentuan saaat panen adalah memantau /melihat keadaan buah kapan buah dapat dipanen.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Tepi buah pisang tidak bersudut tetapi rata.
2.
Buah tampak berisi
/padat.
3.
Bunga yang mongering
pada ujung buah mudah dipatahkan
4.
Warna kulit buah dari
hijau muda menjadi hijau tua.
5.
Daun bendera pada
tanaman sudah mongering.
6.
Buah dapat dipanen
antara 90 -110 hari setelah muncul jantung
Panen adalah proses pengambilan buah yang sudah menunjukan
ciri (sifat khusus) matang panen.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Lakukan
pemanenan pisang pada waktu pagi hari
2.
Gunakan parang yang
tajam dan bersih, sebelum digunakan dicuci dengan lysol/bayclin.
3.
Turunkan kayu atau
bamboo penyangga tandan secara perlahan
4.
Tebang batang pisang
dengan cara menusuk batangnya atau membacok separuh batang setinggi 2/3 dari
tinggi batang agar tandan pisang tidak menyentuh tanah.
5.
Raih tandan pisang
selanjutnya dipotong dengan golok tajam, dipotong disebelah atas buku tandan
(30 cm diatas sisir pertama)
6.
Plastik kerodong dapat
dibuka sebelum atau setelah panen tergantung kondisi.
7.
Balikan
segera tandan pisang yakni tangkai tandan menghadap kebawah.
8.
Pada
tempat pengumpulan tandan pisang diberi alas untuk menghindari buah rusak atau
tergores.
Penanganan Batang Bekas Panen
Penanganan batang bekas panen adalah menjaga kebersihan kebun dengan
membuang batang pisang yang buahnya sudah di panen.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Memotong batang pisang
setelah dipanen hingga kepangkal.
2.
Memotong batang pisang
menjadi bagian –bagian kecil/pendek.
3.
Mengumpulkan batang
pisang tersebut disuatu tempat yang telah ditentukan yang tidak mengganggu
aktifitas kerja.
4.
Mengubur atau memendam
batanng pisang agar tidak menjadi sumber penyakit.
5.
Untuk sisa batang
pisang pada lahan yang tidak mengganggu pertanaman atau meningkatkan suhu
dengan cara membakar untuk memusnahkan OPT yang terdapat pada batang.
6.
Batang
pisang ini dapat dibuat sebagai bahan mentah pembuatan kompos dengan presedur
yang berlaku.
Penyisiran
Penyisiran
adalah proses memisah-misahkan bagian sisir buah.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Penyisiran dengan
menggunakan pisau tajam dengan memotong batang tandan disekitar sisiran buah.
2.
Hindari luka pada buah
saat penyisiran kemulusan buah tetap terjaga.
3.
Tangkai sisiran diberi
daun kering/serasah untuk menghindari getah bekas sisiran tidak menempel pada
buah.
Pemeraman
Pemeraman adalah membantu pematangan buah.
Prosedur Pelaksanaan ;
1. Memasukan
sisir/tandan pisang yang akan diperam kedalam kantong plastik/karung goni.
2. Tempatkan
karbit sebanyak 5 gr untuk satu tandan pisang ke dalam tumpukan bungkus pisang.
3. Ikat
dan tutup an biarkan selama 24 jam.
4.
Bila
menggunakan ethrel celup tandan/sisir selama 30 detik ke larutan ethrel 1.000
ppm (1cc ether/liter air), kemudian ditiriskan /digantung
Sortasi
dan Pengkelasan
Sortasi dan
pengkelasan adalah melakukan dan pemisahan berdasarkan tingkat kematangan buah.
Prosedur Pelaksanaan ;
1. Memilih
dan memisahkan antara buah pisang yang baik dan yang tidak cacat, rusak atau busuk.
2. Kemudian
lakukan pengkelasan/pengelompokan buah pisang yang telah disortasi menjadi
kelompok kelas sesuai ukuran (besar/kecil), bentuk kematangan buah, berat buah
dan keseragaman warna.
3. Kelas
A jumlah buah per sisir lebih dari 12 buah dengan bobot per sisir lebih besar
dari 3,0 kg, Kelas B Jumlag buah persisir 10-12 buah dengan bobot persisir 2,5
– 3,0 kg, Kelas C jumlah buah persisir kurang dari 10 buah dengan bobot
persisir kurang dari 2,5 kg.
Pengemasan
Pengemasan adalah
menempatkan pada keranjang /kemasanyang sesuai.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Gunakan alat kemas
seperti keranjang bamboo.
2.
Keranjang bamboo
dilapisi oleh daun pisang kering (serasah) untuk membatasi antara sisir atau
tandan pisang dengan kemasan agar mutu buah tetap terjaga.
3.
Buah yang sudah dikemas
ditempatkan pada tempat yang kering.
Transportasi
Transportasi adalah proses memindahkan buah pisang ke pasar.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Angkut buah pisang yang
sudah dikemas kekendaraan atau gerobak pengangkutan.
2.
Didalam pengangkutan,
dalam bentuk ;
- Tandan, letakan
posisi tandan pisang tegak lurus (posisi tangkai buah menghadap ke bawah). Bila
di dalam kemasan lebih dari satu tandan, antara tandan diberi penyekat serasah.
- Sisir, lapisi
tiap sisir dengan daun pisang kerang atau serasah.
3. Susun kemasan/kotak pisang
dalam kendaraan pengangkut atau dengan memperhatikan kekuatan kemasan.
By.Admin
Sumber pustaka : Direktorat Jenderal Hotikultura
Departemen Pertanian
Penerapan Standar Prosedur Operesional (SPO) Pisang ( Tahap Pra Panen) 8 Aug 2021 6:46 AM (3 years ago)

Pengertian SPO merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Mutu produk buah merupakan bagian integral dari sub sistem produksi buah-buahan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem perdagangan dewasa ini telah menempatkan mekanisme standar mutu dan jaminan mutu buah sebagai persyaratan pokok yang wajib dipenuhi oleh seluruh produsen buah, tidak terkecuali untuk buah pisang.
Salah satu upaya untuk menghasilkan buah pisang
sesuai keinginan konsumen dapat dilakunan melalui penerapan Standar Prosedur
Operasional (SPO) Pisang. Standar yang digunakan dalam panduan budidaya buah
yang baik dan benar ada tiga kelompok, yaitu ;
1.
Anjuran ( A ) yaitu dianjurkan untuk
dilaksanakan.
2.
Sangat dianjurkan ( SA
) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.
3.
Wajib ( W ) yaitu harus
dilaksanakan.
Dari
standar yang ditetapkan di atas untuk menentukan penilaian atau sertifikasi
terhadap usaha tani yang dilakukan di kebun petani dikelompokan menjadi produk ;
1. Prima Satu (P-1) adalah
peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya
ramah terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan sertifikasi P-1 harus sudah
melakukan 90% seluruh kegiatan sangat dianjurkan SA dan 60 % dari seluruh
kegiatan Anjuran.
2. Prima Dua (P-2) adalah
peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Untuk mendapatkan sertifikasi P-2 harus sudah
melakukan 70% seluruh kegiatan sangat
dianjurkan SA dan 40 % dari kegiatan
Anjuran.
3. Prima Dua (P-3) adalah
peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
Untuk mendapatkan sertifikasi P-3 harus sudah melakukan 60% seluruh
kegiatan sangat dianjurkan SA dan 20 % dari
kegiatan Anjuran.
Untuk
mendapatkan sertifikasi Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2) dan Prima Tiga (P-3) kegiatan
yang bersifat wajib harus dilakukan.
Tahapan Penerapan
Teknologi Standar Prosedur Operesional
(SPO) Pisang
1. Penentuan Lokasi
Penentuan
lokasi adalah memilih lokasi tanam yang menjamin agar usaha produksi pisang
dapat dioptimalkan dan mencegah kegagalan proses produksi, serta dapat
menhasilkan buah sesuai dengan mutu yang ditetapkan.
Prosedur Pelaksanaan,
1. Menghubungi stasiun meteorology terdekat untuk
mendapatkan data iklim terdekat.
2. Mengukur pH tanah.
2. Penyediaan
Benih
Penyediaan
benih adalah menyediakan benih yang produksi dan
kualitasnya tinggi, terjamin kemurnian (jenis, varietas) dan memiliki prospek
pasar yang jelas peluangnya di masa depan, sehat/bebas dari hama penyakit.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Perbanyakan benih pisang
dari anakan
2.
Perbanyakan benih
pisang dari bonggol
3.
Benih Kultur Jaringan
3.
Penyiapan Lahan
a. Pembersihan lahan
Penyiapan
lahan adalah membersihkan lahan dari benda-benda yang dapat mengganggu
pertumbuhan tanaman.
Prosedur Pelaksanaan ;
1. Membersihkan
lahan yang mengganggu sistem perakaran tanaman maupun menghambat penyerapan
unsur makanan
2. Buang
kotoran-kotoran, daun-daun dan ranting bekas pangkasan yang dapat menjadi
sumber penularan hama dan penyakit.
3. Bongkar
dan bakar tanaman yang sakit.
4. Gunakan
alat parang atau alat lainnya yang bersih (dicelup dengan menggunakan sabun
Lysol/bayklin setelah digunakan untuk memotong atau membersihkan tanaman yang
sakit)
5. Penyiapan
saluran air atau parit kebun yang bebas dari rumput, sampah dedaunan serta kayu
yang menyumbat (untuk lokasi yang system grainasenya kurang baik)
6. Aflikasi
herbisida dilakukan untuk lahan yang luas dan berdasarkan pedoman penggunaan
herbisida yang diijinkan.
b. Pengajiran
Pengajiran adalah membuat jarak
tanaman hingga diperoleh populasi tanaman sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Tentukan arah lereng
dan terbit matahari
2.
Membuat arah barisan
sejajar terbit matahari atau memotong lereng, dengan jarak 3 – 4 m
3.
Membuat tanda dalam
barisan dengan jarak 2 – 2,5 m
c. Pembuatan lubang tanaman
Pembuatan lubang tanaman adalah suatu
upaya menyiapkan lingkungan tumbuh tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang
secara maksimal.
Prosedur Pelaksanaan ;
1. Lubang
dibuat dengan ukuran ; Panjang 50 –
60cm, Lebar 50 – 60 cm, Dalam 50 – 60
cm.
2. Pada
saat pelubangan pisahkan tanah lapisan atas (arah timur/kiri) dan tanah lapisan
bawah (arah barat/kanan).
3. Isi
lubang dengan pupuk kandang hingga ½ kedalaman lubang. Pupuk kandang telah
dicampur dengan trikoderma sebanyak 100 gr.
4. Lubang
tanam biarkan terbuka selama 2 minggu.
d. Penutupan lubang Tanam
Penutupan lubang tanam adalah menutup
lubang tanam sehingga tanaman dapat tumbuh normal.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Pada penutupan lubang
tanaman bila tanah masam berikan 10 Kg pupuk kandang yang telah dicampur dengan
50 gr Trikoderma sp, dan 375 gr kapur dolomite (kalau Ph kurang dari 3,5)
2.
Pupuk kandang/kompos
tersebut sebagian dimasukan kedalam lubang tanam dan sebagian dicampurkan
dengan tanah bagian atas (top soil).
3.
Dalam penutupan lubang
tanam, tanah bagian atas (top soil dimasukan terlebih dahulu baru disusul tanah
bagian bawah (sub soil).
4.
Penutupan lubang tanam
dilakukan setelah 2 minggu lubang tanam dibiarkan terbuka.
4.
Penanaman
Penanaman adalah
meletakan benih (bibit) pada lubang tanam yang telah dipersiapkan sesuai dengan
jarak tanam.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Semua peralatan untuk
penanaman dicuci dengan Lysol/bayclin.
2.
Sebelum dilakukan
penanaman, lubang tanam (yang sudah ditutup/ditimbun) dilubangi kembali
seukuran dengan bonggol benih (bibit).
3.
Jarak tanam untuk
dataran rendah 4 X 4 meter, dararan tinggi 4 X 2,5 meter.
4.
Benih (bibit) dikeluarkan dari polybag, namun sebelum
ditanam benih dicelupkan ke dalam suspensi/campuran agens hayati Pf
(Pseudomonas Fluorescens) dengan air (perbandingan 1 : 10) selama 15 menit.
5.
Benih ditanam sampai
sebatas 5 – 10 cm diatas pangkal batang.
6.
Lubang ditutup kembali
dengan tanah galian.
7.
Penanaman dilakukan
pada awal musim hujan.
8.
Jika sarana irigasi
tersedia penanaman dapat dilakukan kapan saja disesuaikan dengan kebun pasar.
9.
Setelah dipakai semua
peralatan dicuci dan disimpan.
5.
Pemupukan
Pemupukan adalah Memenuhi kebutuhan
unsur hara tanaman dan perakaran bisa berkembang lebih baik.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Semua peralatan dicuci
dengan bersih sebelum digunakan.
2.
Pupuk dasar (pupuk
kandang) diberikan 10 kg perumpun setiap 6 bulan sekali.
3.
Pemupukan I dan IV
dilakukan 3 dan 9 bulan sebanyak 100 gr dan SP 36 sebanyak 50 gr.
4.
Pemupukan II dan III
dilakukan 3 dan 6 bulan setelah pemupukan pertama dengan memberikan urea dan
KCL masing-masing sebanyak 100 gr.
5.
Pemupukan selanjutnya
berikan pupuk sesuai dengan dosis seperti pola diatas
6.
Pupuk diberikan
melingkar dengan kedalaman 10 -15 dan jarak 50 – 60 cm dari pangkal rumpun yang
dilanjutkan dengan penutupan pupuk dengan tanah, jerami atau daun kering.
6.
Pengairan
Pengairan
adalah pengatur ketersediaan air yang
cukup untuk pertumbuhan tanaman.
Prosedur
Pelaksanaan ;
1. Air
yang digunakan untuk penyiraman harus berkualitas baik, tidak tercemar zat
bahaya dan limbah pabrik serta bibit penyakit.
2. Pengairan
lahan harus dilakukan paling lambat 3 – 4 hari setelah tanam jika tanam pada
saat tidak turun hujan.
3. Penyiraman
dilakukan dengan disiram dari atas anakan yang masih muda secara perlahan dan
mengenai semua daun pisang, kecuali hujan.
4. Pada
anakan yang baru di tanam dan saat keluarnya bunga, kebutuhan air antara 50 –
90 liter, sedangkan untuk tanaman yang berubah membutuhkan ± 200 liter per
minggu.
Pemotongan
jantung pisang adalah memotong jantung pisang (ontong) setelah sisir terakhir
keluar
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Semua peralatan dicuci dengan Lysol/bayclin
sebelum digunakan.
2.
Pemotongan ontong
dilakukan bila buah terakhir yang normal sudah melengkung ke atas atau 10 -15
cm dari sisir terakhir.
3.
Pemotongan
dengan menggunakan pisau dari arah kanan pada 10 – 15 cm dari sisir terakhir
normal.
8. Pemberongsongan
Pemberongsongan adalah membungkus
buah sehingga diperoleh buah dengan permukaan kulit buah mulus.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Pembrongsongan
dilakukan pada saat seludung pisang pertama belum membuka dan jantung pisang
(ontong) sudah mulai menunduk.
2.
Pemberongsongan
dilakukan dengan menggunakan plastic berwarna biru (polyethylene), dengan
mengusahakan agar seludung atas tidak masuk kedalam plastic srongsong.
3.
Secara berkala
dilakukan pemeriksaan untuk mencegah tersangkutnya seludung yang sudah terlepas
agar tidak membusuk pada tandan buah.
9.
Penyanggahan
Definisi,
Menyanggah pohon pisang agar tidak roboh karena beratnya buah.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Penyanggahan dilakukan
dengan menggunakan bambu.
2.
Penyanggahan bamboo
dipasang searah dengan posisi tandan buah diikat pada batang pohon.
10. Pengendalian Hama Penyakit Terpadu
Pengendalian
hama penyakit terpadu adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian
yang diakibatkan oleh OPT (hama, pathogen, dan gulma) dengan cara memadukan
satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Lakukan pengamatan OPT secara berkala (seminggu sekali) terhadap
OPT utama.
2.
Kenali
dan identifikasi gejala serangan, jenis OPT, dan musuh alaminya.
3.
Perkirakan
OPT yang perlu diwaspadai dan dikendalikan.
11. Pengaturan Jumlah Daun
Pengaturan
jumlah daun adalah memotong daun untuk menjaga ukuran dan penampakan buah
Prosedur Pelaksanaan ;
1.
Alat pemotong daun
perlu direndam dengan bayclin.
2.
Pemotongan dilakukan
dengan meninggalkan 6 – 8 helai daun.
3.
Pilih daun yang telah
tua atau menguning lalu potong dengan membentuk 450 dan potong bagian
batang yang menjuntai sehingga batang tampak bersih.
4.
Kumpulkan daun yang
dipotong pada tempat yang telah ditentukan, untuk daun yang terserang penyakit
pisahkan ditempat lain untuk dibakar.
5.
Jaga
kebersihan kebun.
By.Admin
Sumber pustaka : Direktorat Jenderal Hotikultura
Departemen Pertanian












.jpg)
.jpg)




.jpg)