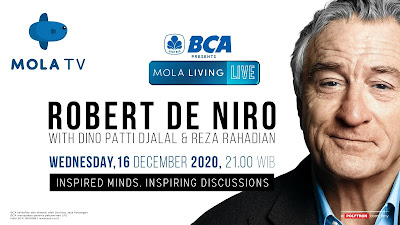3 Alasan Mengapa The Killer’s Shopping List Menarik Ditonton 25 May 2022 7:17 PM (2 years ago)

Jika
membicarakan tentang drama Korea, saya bukan termasuk penikmat setianya yang
melahap hampir semua rilisan baru tanpa peduli genre, pemain, maupun isu yang
dibawa. Saya tergolong amat selektif karena menonton serial membutuhkan
komitmen lebih besar yang merentang selama beberapa minggu dibanding menonton
film yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam saja. Itulah mengapa kala
saya menantikan atau memutuskan untuk melahap satu drama Korea, maka jelas ada
sesuatu yang menarik perhatian diri ini buat mencicipinya. Salah satu judul
terbaru yang membuat hamba tergelitik sedari terpapar teaser trailernya yakni The Killer’s Shopping List yang tayang
di Viu mulai 28 April ini.
Setidaknya ada
tiga alasan yang mendorong saya untuk menantikan kehadiran serial bergenre
komedi misteri ini;
1 1) Genre
Kalau kamu
mengenal saya dengan baik, setidaknya ada dua jenis cerita yang sering saya
tempatkan di skala prioritas tertinggi; drama dan misteri (entah dikemas
sebagai thriller maupun horor). Menilik dari judulnya saja, kita sudah bisa
menebak The Killer’s Shopping List kemungkinan
besar akan berada di ranah kedua dengan kuncinya berada di kata “pembunuh”.
Seolah itu belum cukup menarik perhatian, serial yang konon dipersiapkan untuk
merentang sepanjang 8 episode ini mencoba mengombinasikan elemen misteri
pembunuhannya dengan genre komedi.
Satu perpaduan
yang tentu jarang-jarang ada dalam khasanah drama Korea, bukan? Maksud saya,
alih-alih menghantarkannya sebagai tontonan thriller serius menggunakan nada
pengisahan yang kelam seperti kebanyakan tontonan dengan topik serupa produksi
sineas Negeri Ginseng, drama ini menghantarkannya dengan pendekatan yang lebih
ringan dan penuh canda tawa. Kombinasi yang sejatinya cukup beresiko, tapi
berpotensi melahirkan sajian mengasyikkan apabila tertangani dengan baik.
2 2) Sinopsis
Cerita
Selain genre
serta pendekatan yang diambil, faktor lain yang membuat saya tergugah untuk
mencicipi The Killer’s Shopping List adalah
sinopsis ceritanya yang tampak menarik. Ketimbang menghadirkan tokoh utama
dalam sosok detektif atau penegak hukum yang sudah cukup makan asam garam kala
menangani kasus pembunuhan, drama ini menempatkan seorang pegawai supermarket
kecil di pinggiran kota Seoul. Karakter tersebut bernama Dae-Sung yang
diceritakan punya daya ingat luar biasa tapi karena gagal tes PNS selama 3
tahun berturut-turut, hidupnya terombang-ambing sehingga memaksanya untuk
bekerja di supermarket MS Mart milik sang ibu, Myung-Sook.
Kehidupannya
yang terasa biasa-biasa saja ini lantas berubah kala sebuah pembunuhan terjadi
di dekat tempatnya bekerja. Satu-satunya petunjuk yang bisa didapat melalui
kasus tersebut yakni struk belanja di MS Mart. Dibantu oleh sang kekasih yang
bekerja sebagai petugas kepolisian, A-Hee, Dae-Sung yang tidak memiliki
kompetensi di bidang investigasi dan forensik ini pun memutuskan untuk
menyelidiki kasus pembunuhan ini serta mencari tahu siapa pelakunya. Menarik,
bukan?
3) Jajaran
Pemain
The Killer’s Shopping List semakin
menarik perhatian karena jajaran pemain yang dilibatkan juga cukup mentereng.
Lee Kwang-soo yang baru saja kita lihat aksinya dalam A Year-End Medley dan The
Pirates: The Last Royal Treasure didapuk untuk memerankan Dae-Sung si tokoh
utama. Drama ini menandai kembalinya sang aktor ke layar televisi setelah empat
tahun. Di sini, dia beradu akting dengan aktris sekaligus personil grup musik
AOA, Seol Hyun, yang memainkan peran sebagai A-Hee serta aktris senior Jin
Hee-Kyung yang direkrut untuk melakonkan Myung-Sook. Salah satu peran tersukses
yang dimainkan oleh Jin Hee-Kyung yakni saat beliau memerankan pemimpin geng
Sunny, Chun-hwa, dalam Sunny yang
mengumpulkan 7 juta penonton ketika tayang di bioskop Korea Selatan pada tahun
2011 silam.
Apabila kamu
juga tertarik untuk mengetahui seberapa seru The Killer’s Shopping List, kamu bisa nonton drama Korea ini di
layanan streaming Viu yang dapat diakses melalui website maupun aplikasi smartphone mulai 28 April.
Review The Red Sleeve: Kisah Cinta Putra Mahkota dan Selir Bikin Baper 29 Dec 2021 6:30 AM (3 years ago)
Beberapa waktu lalu, saya menjajal satu drama Korea Selatan yang sedang ramai diperbincangkan, The Red Sleeve, di platform Viu. Konon, drama saeguk alias drama sejarah yang dibintangi oleh Lee Jun-ho (salah satu personil boyband populer 2PM) dan Lee se-young ini terus mengalami kenaikan dari sisi rating di tiap episode.
Dimulai dengan angka 5,7% di episode perdana, kini drama yang guliran pengisahannya disadur dari novel berjudul The Red Sleeve Cuff rekaan Kang Mi-kang ini sudah nyaris merapat ke angka 11%. Mengagumkan, bukan? Dilandasi oleh pencapaiannya yang impresif tersebut, saya pun tergerak untuk menjajalnya. Apalagi sudah cukup lama diri ini tidak menonton serial buatan Negeri Gingseng yang melempar kita jauh ke beberapa ratus tahun silam.
Belakangan lebih banyak menyantap sajian bergenre misteri thriller dengan komentar sosial politik menohok atau makjang (semacam sinetron dengan plot lebay) yang bikin emosi meletup-letup sampai rasanya ingin nyakar orang lain. Kehadiran The Red Sleeve yang didefinisikan oleh seorang kawan sebagai drama penuh sopan santun karena berlatar kerajaan ini jelas memberi penyegaran. Walau tentu saja konflik soal perebutan tahta yang melingkunginya sama sekali tidak ada santun-santunnya.
Sedari awal, The Red Sleeve ini sudah bikin hati kepincut. Saya yang tak tahu menahu soal plotnya sempat mengira bahwa drama ini akan berada di jalur misteri. Maklum, adegan pembukanya menampilkan seorang dayang bernama Seong Deok-im (saat dewasa diperankan oleh Lee Se-young) sedang menceritakan kisah seram kepada rekan-rekannya.
Tapi sejurus kemudian, nada pengisahan seketika berubah kala drama ini menampilkan karakter beserta setting yang sebenarnya. Tak seperti para dayang muda lainnya di kerajaan pada era Dinasti Joseon, Seong Deok-im digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, sekaligus pemberontak. Alih-alih bermimpi menjadi selir raja – judul drama ini merujuk pada lengan baju berwarna merah yang dikenakan oleh para selir – demi kenaikan status, Seong Deok-im lebih menginginkan kehidupan bebas.
Dia menyadari betul, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung berupa lenyapnya kebahagiaan secara perlahan tatkala dia menyerahkan hidupnya sebagai selir. Karakteristik si protagonis perempuan yang rebel ini menjadikan guliran narasi The Red Sleeve terasa menarik untuk disimak terlebih si protagonis laki-laki punya pembawaan yang jauh bertolak belakang sehingga ada dinamika dalam relasi mereka.
Si protagonis laki-laki merupakan putra mahkota atau calon pewaris tahta di kerajaan bernama Yi San (Lee Jun-ho). Berbeda dengan Seong Deok-im yang cenderung ceria, cucu dari Raja Yeongjo ini terasa dingin, arogan, sekaligus perfeksionis. Tak mengherankan sebetulnya mengingat didikan sang kakek pun keras. Yi San yang menyimpan luka atas kematian ayahnya ini tak hanya membawa beban ekspektasi dari Raja Yeongjo, tapi juga membawa ambisi ingin mewujudkan pemerintahan yang adil kala dirinya naik tahta. Meski dirinya adalah pewaris tunggal yang sah, tapi perjalanannya untuk naik tahta tak lantas mudah.
Bak umumnya drama saeguk, ada intrik yang perlahan semakin memanas dan pengkhianatan. Teman baik Yi San, Hong Deok-ro (Kang Hoon), sudah memantik kecurigaan sejak awal mula. Karakternya oportunis dan licik di balik pembawaannya yang hangat.
Bagaimana hubungan mereka berkembang dari sahabat menjadi musuh adalah satu alasan yang membuat episode terbaru The Red Sleeve selalu dinanti-nanti, selain tentunya hubungan Yi San dengan Seong Deok-im. Pertemuan pertama mereka saat masih sama-sama bocah terasa hangat, sementara saat keduanya sudah dewasa terasa manis.
Berhubung drama ini berada di jalur romance, saya jelas ingin melihat bagaimana tumbuh berkembangnya hubungan mereka. Apalagi chemistry apik Lee Jun-ho dengan Lee Se-young membuat kita gregetan kala menyaksikan kebersamaan dua karakter yang mereka perankan.
Kamu juga
penasaran dengan kisah cinta ala Putra Mahkota bersama dayangnya ini? Tenang
saja, kamu bisa menonton The Red Sleeve melalui aplikasi Viu lengkap dengan
subtitle Indonesia dan kualitas gambar HD. Tunggu apalagi, yuk langsung
saksikan The Red Sleeve di Viu yang tayang setiap Sabtu dan Minggu.
Yuk, Intip 4 Fakta Menarik Drama Korea Happiness! 21 Dec 2021 7:48 AM (3 years ago)
Buat kamu penggemar drakor dengan genre thriller, drakor terbaru berjudul Happiness bisa masuk ke dalam list tontonan barumu. Meski memiliki judul Happiness, namun ceritanya justru jauh dari "bahagia". Dibintangi oleh Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik, drama yang berjumlah 12 episode ini menceritakan tentang bagaimana masyarakat Korea bertahan di tengah adanya wabah penyakit baru.
Latar cerita Happiness
dimulai sesaat setelah wabah Covid-19 yang menyerang seluruh dunia telah
teratasi. Meski begitu, Korea Selatan kemudian justru terancam dengan wabah
virus jenis baru yang membuat penderitanya mengalami delusi parah dan selalu
merasa haus. Sayangnya, rasa haus ini hanya bisa diatasi dengan meminum darah
manusia, mirip seperti zombie.
Di tengah kekalutan masyarakat akan wabah baru ini, sebuah apartemen yang dihuni oleh Yoon Sae Bom (Han Hyo Joo) dan Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik) ditutup karena terdapat kasus penyebaran di dalamnya. Hal ini membuat para penghuni harus bertahan hidup di tengah ketakutan serta rasa tidak percaya di antara mereka.
Fakta Menarik Drama Happiness
Bisa dibilang, drama ini merupakan salah satu drama yang sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar drama Korea. Pasalnya, selain temanya yang unik, drama ini juga menjadi proyek comeback bagi beberapa aktor pemerannya. Nah, berikut beberapa fakta mengenai drakor Happiness yang perlu kamu ketahui:
Merupakan Proyek Comeback Park Hyung Sik dan Han Hyo Joo
Happiness merupakan proyek comeback
kedua aktor pemeran utamanya, Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik. Han Hyo Joo
terakhir kali membintangi drama korea W:
Two Worlds yang tayang lima tahun lalu, dan setelah itu vakum dari drama
untuk fokus membintangi berbagai film. Sementara, Park Hyung Sik sebelumnya
baru saja menyelesaikan wajib militer, selama kurang lebih dua tahun, pada awal
Januari 2021 lalu.
Tentunya ini menjadi obat rindu bagi para penggemar kedua
aktor Korea ini, ya. Banyak juga yang penasaran bagaimana chemistry keduanya berperan sebagai pasangan dalam drama ini.
Selain Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik, Happiness juga merupakan proyek comeback aktor Jo Woo Jin yang berperan sebagai Han Tae Seok, agen militer yang bertanggung jawab atas penyebaran wabah tersebut, setelah membintangi drama terakhirnya pada tahun 2018.
Kolaborasi Kedua Sutradara
dan Penulis Skrip
Happiness juga menjadi comeback kolaborasi antara sutradara Ahn Gil Ho dan penulis skrip Han Sang Woon, setelah sebelumnya bekerjasama dalam drama Watcher di tahun 2019. Kedua drama ini sama-sama memiliki genre thriller, membuat penonton penasaran mengenai bagaimana kolaborasi keduanya akan menghasilkan drama dengan cerita yang fresh dan rating yang tinggi seperti sebelumnya.
Bukan Sekadar Cerita Wabah
Penyakit dan Zombie
Meski memiliki tema utama mengenai wabah penyakit yang menjadikan penderitanya bersikap seperti zombie, Happiness juga menyajikan layer cerita yang lebih dari itu. Happiness menyelipkan kisah mengenai diskriminasi kelas sosial di tengah masyarakat Korea, seperti yang terjadi pada apartemen yang dihuni oleh pasangan Yi Hyun dan Saebom, di mana kelas atas dapat dengan mudah melindungi diri dari wabah. Sementara masyarakat kelas bawah menjadi yang paling rentan menghadapi wabah tersebut. Diskriminasi antara kelas atas, bawah, dan menengah ini bisa dikatakan merupakan cerminan kejadian yang juga terjadi di kehidupan nyata masyarakat Korea saat ini.
Wabah yang Unik
Bila biasanya kita disuguhkan wabah zombie di mana
penderitanya akan berubah menjadi mayat hidup, maka di Happiness penderita wabah ini dapat menjadi manusia kembali. Mereka
dapat menjadi normal dan tidak merasakan haus untuk beberapa waktu. Hal ini
kemudian yang menjadikan pergolakan batin dan psikologi, apakah penderita wabah
ini harus dibunuh atau dibiarkan hidup?
Menarik, bukan? Nah, kalau kamu penasaran dengan bagaimana
kelanjutan kisah Yi Hyun dan Saebom dalam menghadapi kejahatan di tengah
penularan wabah penyakit ini, Happiness
sudah tayang di aplikasi VIU setiap Sabtu dan Minggu. Yuk, langsung tonton dan
saksikan ketegangannya!
Review - The Publicist (Viu Original Series) 7 Oct 2021 1:40 AM (3 years ago)

“Kamu masih cinta kah sama laki-laki brengsek di depan kamu ini?”
Ada yang pernah mendengar drama Indonesia berjudul The Publicist? Beberapa waktu lalu, saya baru menemukan original series produksi Viu bekerjasama dengan Moviesta Pictures ini yang ternyata sudah memenangkan tiga penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2018 termasuk Best Drama Series dan Best Supporting Actress untuk Poppy Sovia. Sejujurnya, hamba termasuk jarang menyentuh serial produksi dalam negeri (well, trauma terhadap sinetron di TV masih membayangi) kecuali untuk beberapa judul yang sudah mencuri perhatian melalui premis, kedekatan pada materi sumber jikalau berbentuk adaptasi, serta jajaran pemain yang terlibat. Khusus untuk Viu Original Series The Publicist ini, faktor terakhir lah yang membuat saya tergerak untuk mencicipinya. Betapa tidak, barisan pelakonnya tergolong menjanjikan seperti Prisia Nasution, Adipati Dolken, Baim Wong, Poppy Sovia, serta Reza Nangin. Belum lagi sutradara yang ditunjuk untuk mengomandoi proyek ini pun mempunyai jejak rekam membanggakan, Monty Tiwa (Sabtu Bersama Bapak, Critical Eleven). Jadi, bagaimana tidak tergiur untuk menjajalnya? Apalagi guliran pengisahan yang dibawa The Publicist juga terhitung segar.
Ya, serial ini memang masih bergerak di ranah drama romantis. Tapi apa yang kemudian membuatnya terasa berbeda adalah latar belakang dari sang tokoh utama, Julia Tanjung (Prisia Nasution), yang berprofesi sebagai personal consultant. Melalui The Publicist, kita sedikit banyak melihat bagaimana cara kerja dari seorang konsultan dan publisis dalam menciptakan citra tertentu bagi public figure sehingga masyarakat bisa bersimpati atau minimal menyadari keberadaannya. Dalam serial ini, tugas Julia adalah membantu seorang aktor berbakat peraih dua Piala Citra, Reynaldi (Adipati Dolken), untuk membersihkan imejnya yang kadung hancur lantaran terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Pekerja film emoh merekrutnya karena tingkah lakunya yang sulit diatur, sementara publik menolaknya karena menganggap public figure semestinya bisa dijadikan teladan. Menilik tantangannya tersebut, jelas bukan perkara mudah bagi Julia untuk mendongrak kembali karir Reynaldi yang terjun bebas terlebih kliennya ini sendiri bukan pribadi yang mudah diajak kerjasama. Punya ego tinggi, gampang tersulut amarah, dan sering menghilang kala keadaan tak berjalan sesuai dengan kemauannya. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan karir aktor semacam ini?
Kenyataannya, didukung oleh asisten
Reynaldi, Erika (Poppy Sovia), Julia perlahan tapi pasti bisa menembus dinding
pertahanan sang aktor setelah mencoba mengenalnya lebih dalam. Upayanya untuk
melahirkan kembali karir kliennya ini melalui panggung teater membuahkan hasil
yang kemudian turut mendekatkan mereka berdua sekaligus memercikkan api-api
asmara. Selama 13 episode, The Publicist yang
menjalani pengambilan gambar di Jakarta dan Tokyo, Jepang, ini menyoroti
bagaimana kisah kasih antara seorang aktor dengan publisisnya ini bersemi. Duet
maut antara Prisia Nasution dengan Adipati Dolken memungkinkan penonton untuk
terpikat lalu tertarik menyimak cerita cinta berdua. Terlebih, karakter yang
mereka perankan sejatinya bertolak belakang sekalipun sama-sama keras. Julia
adalah pribadi yang disiplin, memandang serius pekerjaannya serta tak menerima
kesalahan-kesalahan kecil, sedangkan Reynaldi yang pembangkang bukanlah tipe
manusia yang bersedia tunduk pada peraturan. Bagaimana dua insan yang mempunyai
karakteristik bertentangan ini akhirnya bisa bersatu merupakan daya tarik bagi The Publicist.
Kalau mau cobain nonton The Publicist, bisa ditonton gratis di
Viu yes.
REVIEW - BAD SAMARITAN 22 Apr 2021 3:41 AM (4 years ago)
“He’s gonna kill us.” Beberapa waktu lalu, hamba baru menemukan sebuah hidden gem yang tak banyak diperbincangkan oleh netizen dan sepertinya malah sudah mulai terlupakan keberadaannya. Film tersebut berjudul Bad Samaritan, disutradarai oleh Dean Devlin (Geostorm), serta dirilis pada tahun 2018 silam. Saat menontonnya, diri ini sampai bertanya-tanya, “apa yang aku lakukan tiga tahun lalu sampai mengabaikan film ini?.” Jawaban yang mungkin paling masuk akal adalah, Bad Samaritan tidak mendapatkan respon yang menggembirakan dari publik maupun kritikus kala diluncurkan. Tidak ada pujian, tidak ada pula cacian, hanya dianggap sebagai angin lalu. Bentuk resepsi yang jujur saja saya pertanyakan karena film bergenre thriller ini tergolong salah satu yang paling menggigit di genrenya dalam beberapa tahun terakhir. Kamu memang tidak akan menemukan jalinan pengisahan yang benar-benar baru maupun mindblowing, tapi saat film tersebut mampu mencengkrammu erat-erat sedari awal sampai akhir, mengapa kebaruan ini menjadi sesuatu yang penting? Maksudku, bukankah saat filmnya sanggup membawamu ikut terhanyut ke dunia di dalam film seharusnya sudah cukup ya?
Bad Samaritan sendiri menempatkan fokus penceritaannya kepada seorang petugas jasa valet mobil di restoran Italia bernama Sean (Robert Sheehan). Bersama rekan kerja sekaligus teman baiknya, Derek (Carlito Olivero), keduanya menjalani “pekerjaan sampingan” dengan membobol rumah para pelanggan resto. Selagi pemilik mobil menyantap makanan, salah satu dari mereka mengarahkan mobil ke rumah si pemilik dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Perbuatan kriminal dua sohib ini mulanya berjalan lancar-lancar saja sampai Sean kena batunya. Saat menyusup ke rumah seorang pria kaya yang mengendarai Maserati, Cale (David Tennant), Sean mendapati temuan mengejutkan yang selamanya mengubah hidupnya: seorang perempuan bernama Katie (Kerry Condon) disekap di dalam kantor Cale. Sean mulanya berniat untuk menyelamatkan Katie sampai dia menyadari bahwa kaki Katie dirantai sementara waktunya sangat terbatas. Belum lagi dia harus menghindari kamera pengawas yang terhubung langsung ke ponsel Cale. Butuh perencanaan matang alih-alih spontanitas untuk bisa membebaskan diri dari rumah tersebut.
Telepon dari Derek yang mengabarkan status Cale yang siap meluncur seketika membuyarkan misi penyelamatan ini. Tapi Sean yang merasa bertanggungjawab secara moral – terlebih dia telah berjanji kepada Katie akan menyelamatkannya – enggan membiarkan begitu saja apa yang telah ditemukannya. Dia membuat laporan ke pihak berwenang mengenai temuannya tersebut meski ini berarti membahayakan dirinya sendiri. Bukan, bukan polisi atau FBI yang dikhawatirkannya melainkan Cale yang telah siap sedia untuk membuat kehidupan protagonis kita ini terasa seperti neraka. Seram, bukan? Fakta bahwa penonton telah diberi tahu sedari awal mengenai “si jahat” dan “si baik” tidak lantas mengurangi kenyamanan dalam menyaksikan Bad Samaritan. Memang betul skrip racikan Brandon Boyce tak terlalu berminat meluncurkan kejutan serta mengeksplorasi sosok Cale yang sejatinya menarik untuk dibedah, tapi kepiawaian Devlin bersama Brian Gonosey si penyunting gambar memungkinkan bagi film untuk bercerita secara rapat. Lajunya telah dikondisikan bergegas sedari awal dan sedari kunjungan Sean ke rumah-rumah yang disantroninya, intensitas terus beranjak naik.
Momen pertama yang membuat jantung terasa deg-deg ser adalah ketika Sean menemukan Katie, ingin menyelamatkannya, dan dia menerima telepon dari Derek mengenai status Cale. Bagaimana jika protagonis kita ini ketahuan? Bagaimana jika dia menjadi korban selanjutnya? Tak butuh waktu lama bagi Bad Samaritan untuk mengonfirmasi bahwa Sean memang telah diincar oleh Cale. Kekayaan serta koneksi yang dipunyainya memudahkan baginya untuk menghancurkan kehidupan Sean. Ya, ada sekelumit komentar sosial disini perihal status sosial serta seberapa kuat pengaruh yang dipunyai oleh masyarakat berkantong tebal. Tapi film memang tak berminat untuk menghadirkannya sebagai kritik dan memilih sepenuhnya berdiri di jalur tontonan popcorn bergenre thriller yang semata-mata diniatkan untuk membuat jantungmu berdegup kencang. Disamping pengarahan serta editing yang lincah, kekuatan lain dari Bad Samaritan bersumber dari akting prima jajaran pelakonnya khususnya David Tennant. Saya angkat topi untuknya yang berhasil membuat Cale sebagai sosok villain yang mengintimidasi, menakutkan, sekaligus menyebalkan. Tanpa harus mengetahui apa yang telah diperbuatnya, kita sudah bisa mendeteksi ada sesuatu yang jahat darinya hanya melalui tatapan dan caranya memerlakukan Sean serta Derek di awal film.
Exceeds Expectations (3,5/5)
Bad Samaritan yang menegangkan ini bisa kamu tonton secara streaming di Mola TV dengan membayar biaya berlangganan Rp. 12.500 per bulan. Selain film ini, aku juga menemukan banyak harta karun di sana.
REVIEW - PERCY 18 Apr 2021 8:35 PM (4 years ago)
“There’s a lot of farmers around the world who can’t stand up, I figure I should.” Pada tanggal 6 Agustus pagi di tahun 1998, seorang petani dari Saskatchewan, Kanada, bernama Percy Schmeiser menerima “surat cinta” dari Monsanto, perusahaan agrikultur raksasa yang telah menancapkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Isi surat tersebut tak saja membuat Percy terkejut, tapi juga luar biasa marah. Betapa tidak, tanpa ada pemberitahuan, peringatan, atau bahkan teguran sebelumnya, dia mendadak digugat oleh Monsanto setelah mereka menemukan tanaman kanola jenis Roundup Ready (tanaman ini sudah dimodifikasi secara genetik) tumbuh berkembang di lahan Percy. Ini dianggap sebagai suatu masalah lantaran benih kanola jenis Roundup Ready telah dipatenkan haknya oleh Monsanto dan tidak semua petani diizinkan untuk menanamnya kecuali sudah membeli lisensinya secara resmi. Berhubung Percy tak pernah berbisnis dengan perusahaan ini soal benih, penemuan tersebut jelas dianggap sebagai pelanggaran. Atau mengutip langsung dari kata yang dipergunakan oleh si penggugat, “dia telah mencurinya.” 
Ketidakadilan yang dialami oleh petani yang telah puluhan tahun menjalankan bisnis keluarga di bidang pertanian ini mengilhami Clark Johnson untuk menggarap Percy (atau dikenal sebagai Percy vs Goliath di Amerika Serikat). Film berdurasi 120 menit ini tak menitikberatkan pada perjalanan hidup si karakter tituler atau bagaimana pihak pembela melakukan penyelidikan demi melindungi kliennya dari gugatan bernilai puluhan ribu dollar, melainkan lebih tertarik untuk menyoroti kehidupan seorang petani tua yang mulanya tenang hingga badai besar tiba-tiba menerjang dan membuat seluruh keluarganya ikut terombang-ambing bersamanya. Ya, jika kamu mencari tontonan dengan sisi investigatif kuat dibalik isu lingkungan dan kemanusiaan, Percy boleh jadi akan membuatmu kecewa. Ini tak seperti Dark Waters (2019) atau Erin Brockovich (2000) yang cenderung meletup-letup dalam pengisahannya. Menilik pendekatan kisahnya yang cenderung personal, Johnson mencoba mengantarkan kisah perlawanan Pak Schmeiser menghadapi pihak Monsanto dengan lebih tenang, bersahaja, tapi tetap mempunyai daya sentak cukup kuat dalam sisi emosi.
Percy (diperankan oleh Christopher Walken) adalah seorang pria berusia 73 tahun yang digambarkan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dibalik tampilan luarnya yang terlihat santai, kalem, serta cenderung masa bodoh, beliau peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mencintai istrinya, Louise (Roberta Maxwell), mengayomi pekerja-pekerjanya, dan menyayangi putranya yang enggan mengikuti jejaknya sebagai petani, Peter (Luke Kirby). Tapi saat ada pihak yang mengobrak-abrik kehidupannya – konon, gugatan dari Monsanto berpotensi membuat Percy kehilangan lahannya – dia enggan untuk berdiam diri dan menunjukkan perlawanan. Dari merekrut seorang pengacara yang sebetulnya tidak memiliki banyak pengalaman, Jackson (Zach Braff), untuk membantunya menghadapi Monsanto di pengadilan, sampai menerima tawaran dari aktivis lingkungan hidup bernama Rebecca Salcau (Christina Ricci) untuk mencari dukungan dari publik melalui seminar-seminar. Kesediaan Percy untuk berorasi merupakan fakta yang mengejutkan bagi Louise karena suaminya tersebut tak pernah merasa nyaman kala berbicara di depan banyak orang. Namun semenjak Percy tampil di media, keliling Amerika Utara, bahkan terbang ke India, bala bantuan berupa dukungan moral dan uang terus mengalir. Banyak petani terdzalimi yang merasa terwakili dan terinspirasi dengan perjuangan Pak Schmeiser.
Meski tak ada penyelidikan atau pengungkapan fakta yang akan membuatmu terperangah, Percy masih sanggup menjerat atensi kita karena kisahnya yang terasa dekat. Bukan kali pertama kasus gugatan seperti ini dilayangkan oleh Monsanto (maupun perusahaan agrikultur sejenis) kepada petani biasa dan bisa jadi bukan kali terakhir. Apa yang terjadi kepada Percy bisa saja terjadi kepada kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, teman baik kita atau tetangga kita. Itulah mengapa apa yang disajikan oleh film ini terasa penting karena membuka mata siapapun mengenai perjuangan para petani dalam hadapi ancaman dari para pemilik modal yang masih terus terjadi sampai detik ini. Lakon apik Christopher Walken dalam memerankan Pak Schmeiser adalah kekuatan lain yang dipunyai oleh Percy karena berkat beliau dan pesan pentingnya, hamba dapat menerima presentasi visualnya yang terkesan murah dan bersimpati ke tokoh yang dimainkannya. Siapa coba yang tak terenyuh melihat seorang pria tua yang hanya ingin merawat lahannya seperti diamanatkan oleh para pendahulunya dan menjalani masa senjanya dengan damai tiba-tiba diseret oleh perusahaan raksasa yang serakah ke pengadilan untuk membayar ganti rugi? Mungkin hanya mereka yang mendukung penuh Monsanto.
Acceptable (3/5)
*Kalau kepengen nyobain nonton Percy, kalian bisa langsung streaming dengan melipir ke Mola TV. Harga langganannya Rp. 12.500 saja per bulan*REVIEW : COUNTERPART (TV SERIES) 27 Feb 2021 5:52 AM (4 years ago)

“We’re caught in the middle of something, whether we want to be or not.”
Saat sedang overthinking merenungi kehidupan sembari memikirkan ide cerita agar dapur tetap ngebul, Justin Marks terpikir gagasan gila, “bagaimana kalau aku bikin sebuah serial yang tidak hanya dibintangi oleh satu J.K. Simmons saja tapi ada dua?.” Tentu, ini hanya karangan hamba semata. Tapi bagaimanapun awal mulanya, “menggandakan” Pak Simmons adalah sebuah rencana yang jenius. Dia adalah aktor yang lebih dari sekadar kompeten dan kemenangannya di Oscar berkat perannya sebagai guru musik yang sadis dalam Whiplash (2014) adalah pembuktiannya. Melalui serial keluaran Sony Pictures Television berjudul Counterpart yang merentang sepanjang dua musim dengan total 20 episode, beliau diberi dua peran unik yang menguji kemampuan berlakonnya. Peran yang dimainkannya sama-sama bernama Howard Silk dan pada dasarnya, kedua karakter ini berbagi kesamaan di sepanjang hidup mereka sekalipun jauh terpisah. Akan tetapi, saat memperbincangkan soal karakteristik, kamu akan melihat keduanya sebagai orang berbeda. Nyaris tidak ada persamaan yang akan membuatmu bertanya-tanya, “bagaimana bisa dua manusia yang mempunyai sejarah masa lalu serupa dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang berlainan?.”
Ya, dua Howard Silk ini memang dikisahkan memiliki perjalanan hidup yang sama. Baik dari orang tua, jenjang pendidikan, sampai urusan asmara. Identik, tapi bukan saudara kembar. Howard pertama yang kita kenal (sebagai pembeda disebut Howard Alpha) berasal dari dunia yang kita tempati sekarang. Dia mempunyai pekerjaan yang membosankan sekaligus tak jelas kegunaannya di kantor PBB cabang Berlin selama 30 tahun. Saat dirinya menghadap ke atasan, Peter Quayle (Harry Lloyd), dengan harapan akhirnya bisa naik jabatan, Howard justru mendapat kejutan tak disangka-sangka. Dia dipertemukan dengan “kembarannya” yang juga bernama Howard (disebut sebagai Howard Prime) yang berasal dari Sisi Lain. Sebuah tempat yang tak hanya asing bagi kita, tapi juga karakter inti di serial ini. Konon, Sisi Lain adalah bagian dari dunia paralel yang tercetus pada tahun 1987 saat sebuah eksperimen yang berlangsung pada masa Perang Dingin mengalami kegagalan. Ada gerbang yang tiba-tiba muncul dan saat kita melintasinya, kita akan memasuki dunia yang sama persis dengan kita. Pembedanya, dunia dimana Prime bernaung mengalami kerusakan parah setelah terjadi pandemi yang disinyalir dikirimkan secara sengaja oleh dunia Alpha yang seketika menciptakan permusuhan diantara dua dunia ini.
Kedatangan Howard Prime yang berstatus sebagai agen rahasia ke dunia Alpha sendiri didorong oleh misinya untuk meringkus seorang pembunuh bayaran bernama Baldwin (Sara Serraiocco) yang kabur ke dunia Alpha. Menurut pengakuan Howard Prime, Baldwin berencana membunuh istri Howard Alpha, Emily (Olivia Williams) yang kini terbaring koma di rumah sakit. Apa tujuannya? Tidak ada yang tahu pasti. Selama beberapa episode awal Counterpart, Marks memang menghadirkan cukup banyak pertanyaan dengan harapan dapat menggaet atensi penonton. Bagi yang menggemari tontonan thriller spionase dan tidak keberatan dengan laju penceritaan yang bergerak secara perlahan, apa yang disodorkan oleh Counterpart ini mesti diakui menarik. Malah, sangat menarik. Serial mengupas misterinya sedikit demi sedikit yang seiring berjalannya durasi semakin membuatmu kecanduan. Menariknya, bukan hanya semata-mata memancing keingintahuan kita mengenai rahasia yang tersembunyi dibalik kedatangan Howard Prime maupun intrik dua dunia, melainkan turut mendorong kita pada perenungan filosofis mengenai manusia dan kehidupan.
Melalui sosok dua Howard, penonton dihadapkan pada studi karakter yang mempertanyakan tentang karakteristik manusia. Apakah karakter seseorang adalah bawaan dari lahir yang sulit diubah atau bisa dibentuk secara fleksibel oleh pengalaman hidup? Ya, kita akan terus mempertanyakan ini seraya mengagumi betapa apiknya performa yang disuguhkan oleh J.K. Simmons. Beliau tak semata-mata menduplikasi peran yang pernah dimainkan sebelumnya, melainkan betul-betul berupaya untuk menghadirkan sosok Howard dengan interpretasi baru. Di tangannya, Howard Alpha berhasil digambarkan sebagai everyman yang hidupnya lempeng-lempeng saja, sementara Howard Prime tampil penuh percaya diri dalam setiap langkah yang diambilnya. Tanpa harus ditambah aksesoris berlebihan – Simmons hanya menggunakan topi sebagai pembeda – keduanya sanggup terlihat kontras. Kamu bisa mendeteksi perbedaan diantara mereka secara jelas dan kamu pun bisa menyematkan simpati kepada keduanya sekalipun secara penokohan sangat bertentangan. Hebat memang Pak Simmons ini!
Penasaran dengan kelanjutan intrik yang dihadapi oleh duo Howard? Kalian bisa melahap seluruh episode Counterpart sampai musim kedua di layanan streaming Mola TV. Biaya berlangganannya murah kok. Untuk paket standar, kamu bisa dapatkan hanya dengan Rp. 12.500. Sementara untuk paket HBO GO, kamu akan dikenai biaya sebesar Rp. 65.000. Pembayarannya bisa dilakukan melalui ATM maupun OVO. Selain Counterpart, banyak serial lain yang menarik lho mulai dari Two Weeks To Live hingga Into The Dark.
REVIEW : TWO WEEKS TO LIVE (TV SERIES) 21 Feb 2021 5:55 AM (4 years ago)
“My whole life is a lie.” Saat pertama kali melihat trailer Two Weeks to Live, sulit untuk tak melontarkan komentar, “apakah ini interpretasi modern dari Game of Thrones? Maksud saya, ada Maisie Williams di sana.” Ya, pemeran utama miniseri asal Inggris berjumlah enam episode hasil kolaborasi antara Sky UK dan HBO Max ini adalah Williams yang dikenal berkat perannya sebagai Arya Stark di serial fenomenal tersebut. Menariknya, kesamaan antara dua serial ini tidak terhenti hanya sampai disitu saja. Karakter yang dimainkan oleh Williams, Kim Noakes, mempunyai perjalanan hidup yang sedikit banyak mengingatkan kita pada Arya. Seorang perempuan mungil yang bertransformasi menjadi remaja pemberontak dan pembunuh keji. Melalui Two Weeks to Live, Kim dikisahkan tinggal dalam kabin yang tersembunyi nun jauh di pedalaman kabin ini dikisahkan membawa misi rahasia untuk memburu pembunuh sang ayah. Selama menjauhi peradaban manusia, ibunya, Tina (diperankan dengan sangat apik oleh Sian Clifford), menggembleng putri semata wayangnya ini untuk menjadi perempuan berdikari yang dapat membela dirinya sendiri dalam kesempatan apapun. Dibalik tampilan luarnya yang tampak polos nan mungil, seriously, you don’t want to mess with Kim.
Kim sendiri tinggal bersama Tina di kabin selama 15 tahun tanpa pernah sekalipun merasakan pengalaman hidup di “dunia luar”. Dia hanya pernah menonton film sebanyak empat judul saja (salah satunya adalah Home Alone 2), dirinya menganggap lirik lagu “I Will Survive” sebagai puisi asli buatan ibunya, dan Kim selalu mengonsumsi pil anti polusi yang tidak lain tidak bukan adalah permen mint biasa. Tapi saat usianya menginjak 21 tahun dan merasa sudah siap untuk membalas kematian ayahnya, Kim nekat melarikan diri dari kabin. Ditengah pelariannya ini, dia bertemu dengan dua saudara, Nicky (Mawaan Rizwan) yang cenderung culun dan Jay (Taheen Modak) yang sepertinya tidak kebagian jatah saat Tuhan bagi-bagi otak, di sebuah bar. Mengetahui bahwa Kim adalah perempuan polos yang bisa ditipu dengan mudah, keduanya pun membuat guyonan dengan mengatakan bumi sedang berada di ambang kehancuran dan mereka hanya punya waktu untuk hidup selama dua minggu saja. Tentu saja, berita bohong ini seketika membuat Kim panik. Kim yang tadinya berniat mengeksekusi “to do list” terlebih dahulu untuk menikmati pengalaman hidup yang tak pernah dirasakannya, lantas mengubah rencana. Sebelum dunia berakhir, dia harus menunaikan misi utamanya yakni mencabut nyawa orang yang bertanggung jawab dibalik kematian sang ayah.
Menilik misi utama yang diemban oleh sang karakter inti, Two Weeks to Live memang terdengar seperti sajian kriminal dengan intensitas tinggi. Kurang lebih akan mengingatkanmu pada Hanna – baik versi layar lebar maupun serial – yang berceloteh soal seorang gadis yang digembleng menjadi mesin pembunuh di pedalaman. Akan tetapi, miniseri garapan Al Campbell yang naskahnya ditulis oleh Gaby Hull bersama Phoebe Eclair-Powell dan Lucy Montgomery ini memilih untuk menyajikannya dengan kandungan humor yang terhitung pekat. Bukan berbentuk komedi gelap dimana kelucuan-kelucuannya muncul dari peristiwa yang tidak semestinya ditertawakan, melainkan murni berwujud slapstick yang mencuat dari barisan karakter-karakternya yang seluruhnya digambarkan ajaib. Satu-satunya karakter “lurus” di sini adalah Tina yang itupun dibekali dialog-dialog kocak berisi nyinyiran dan sarkasme dengan metafora yang janggal. Lainnya? Kamu mungkin akan mengelus dada jika benar-benar bertemu dengan karakter seperti mereka. Dari Kim yang selalu takjub dengan apapun yang dilihatnya di peradaban modern, lalu Nicky yang tak bisa mengambil tindakan tegas, kemudian Jay dengan keputusan-keputusan bodohnya, sampai villain yang menganggap diri mereka keren meski kenyataannya, well… konyol. Duo Brooks dan Thompson (Jason Flemyng-Thalissa Teixeira) ini macam grup lenong yang memaksakan diri buat menjadi pembunuh bayaran.
Pun begitu, Campbell tak lantas mempreteli kebengisan mereka di sini. Keduanya tetap menjadi ancaman serius bagi Kim, Tina, Nicky, dan Jay lantaran tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi rencana mereka. Walau ya, adegan pembunuhannya tetap dibawakan secara komikal. Ditengah bombardir humor disana sini, Two Weeks to Live yang setiap episodenya berdurasi 24 menit ini nyatanya masih sanggup pula untuk tampil intens. Salah satu momen terbaik di Two Weeks to Live yang menampilkan duel antara Kim dengan pembunuh ayahnya membuat perhatianku lekat ke layar. Terasa seru, mendebarkan, sekaligus mengundang gelak tawa. Betapa tidak, dua karakter yang sedang berada dalam situasi hidup dan mati ini masih sempat-sempatnya ngelawak. Entah berbalas kata, main lempar-lemparan barang, hingga membahas soal norma-norma kesopanan. Ya, Kim tersinggung karena lawannya ini menusuk punggungnya saat dia sedang berbalik. “Rude!” begitu teriaknya dan hamba mengangguk-angguk setuju sambil ketawa terbahak-bahak.
Kisah Kim yang menggelitik nan seru di Two Weeks to Live ini bisa kalian tonton di layanan streaming Mola TV. Sudah tersedia lengkap sampai episode ke-6 lho. Untuk bisa menontonnya, kamu cukup berlangganan paket standar seharga Rp. 12.500 untuk 30 hari atau paket HBO GO sebesar Rp. 65.000. Pembayarannya pun mudah bisa dilakukan melalui ATM maupun OVO.
REVIEW : THE FIRST (TV SERIES) 11 Feb 2021 6:46 AM (4 years ago)

Baru beberapa bulan
lalu, hamba menjadi saksi kehebatan akting Sean Penn dalam The Professor and the Madman. Satu film kecil yang apik tapi
sayangnya tak banyak dibicarakan. Lalu Mola TV mengakuisi serial berumur pendek
produksi kolaborasi antara Hulu asal Amerika Serikat dan Channel 4 dari
Inggris, The First, yang membuat saya
harus kembali mengakui bahwa Pak Penn memang layak mengoleksi dua piala Oscar.
Ya, dia lagi-lagi berlakon secara cemerlang di sini. Bahkan, The First sejatinya digerakkan oleh
performa sang aktor yang karakternya ditempatkan dalam poros utama penceritaan.
Ini adalah serial bertipe character
driven dimana penonton menyaksikan proses tumbuh berkembangnya satu
karakter dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks. Dalam kasus The First, persoalan tersebut berkenaan
dengan duka, luka, serta kehilangan. Bukan topik yang mudah buat dikonsumsi ya?
Itulah mengapa membutuhkan keselarasan dalam akting, pengarahan, sekaligus
naskah agar tak terjerembab menjadi sajian grieving
porn yang terlampau melelahkan buat disimak. Untungnya bagi serial kreasi
Beau Willimon (otak dibalik terciptanya serial kece pemenang penghargaan House of Cards) ini, hal tersebut tak
pernah benar-benar terjadi. Kita dapat memahami seraya menempatkan diri dalam
posisi Tom Hagerty yang diperankan oleh Sean Penn.
Pada mulanya,
kita tak mengetahui persoalan apa yang meradang Tom. Di episode pembuka
penonton hanya mengetahui bahwa dia dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk
mengomandoi sejumlah awak astronot dalam misi membawa manusia untuk pertama
kalinya ke Planet Mars. Misi perdana hasil kerjasama antara NASA dengan
perusahaan swasta Vista yang dipimpin oleh Laz Ingram (Natasha McElhone)
tersebut nyatanya berakhir tragis. Roket yang ditunggangi oleh para astronot
tiba-tiba meledak hanya beberapa saat setelah diluncurkan. Euforia menyambut
peristiwa bersejarah bagi umat manusia seketika digantikan oleh isak tangis.
Orang tua korban meminta pertanggungjawaban kepada Vista dan Laz pun diseret ke
hadapan Kongres. Demi meminimalisir dampak kerusakan yang harus ditanggung
perusahaan, Laz lantas meminta bantuan kepada Tom yang dinilainya paham dengan
situasi di belakang layar. Meski dilingkupi kekecewaan lantaran dibebastugaskan
secara sepihak dan dirundung pula perasaan bersalah karena tak mendampingi
rekan-rekannya yang gugur dalam tugas, Tom bersedia memberi kesaksian untuk
Vista. Apalagi Laz bersedia memberinya kesempatan kedua untuk berpartisipasi
dalam misi selanjutnya ke planet merah apabila Kongres meloloskan permintaan
Vista.
Melalui tukar
dialog antara Tom dengan Laz, kita perlahan mengetahui akar permasalahan dari
absennya si protagonis dalam misi menuju Mars: kematian sang istri. Ada duka,
luka, serta rasa kehilangan mendalam yang mendorong Tom ke lembah gelap. Tak
hanya mengacaukan kehidupan profesionalnya, kesedihan yang berlarut-larut ini
turut mempengaruhi hubungannya dengan sang putri, Denise (Anna Jacoby-Heron),
yang belakangan memilih untuk hengkang dari rumah. Tapi pada penghujung episode
perdana, Denise kembali muncul di hadapan ayahnya. Munculnya kekhawatiran bahwa
sang ayah turut menjadi korban – yang berarti dia menjadi yatim piatu –
mendorongnya untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini. Tom seolah memperoleh
“berkah terselubung” melalui peristiwa naas yang menewaskan rekan-rekannya
sebab dari sanalah dirinya berkesempatan untuk menebus kesalahan seraya
terhubung kembali dengan Laz maupun Denise. Selama delapan episode dengan
durasi rata-rata sepanjang 45 menit, serial berlatar tahun 2030 ini tak saja
memperlihatkan proses Tom untuk menyembuhkan jiwanya yang terluka, tetapi juga
mengetengahkan pada intrik dibalik perekrutan awak-awak baru yang akan
dilibatkan pada misi terbaru Vista.
Alhasil, si
tokoh utama dihadapkan pada pertarungan lebih besar yang menjadi ujian bagi
kesiapannya memimpin satu misi penting. Pertarungan dengan dirinya sendiri yang
masih memiliki luka menganga dari masa lampau, serta pertarungan dengan ego-ego
menjulang dari rekan kerjanya. Sean Penn mempertontonkan akting yang ciamik
dalam pergumulan yang menguras emosi ini. Dia terlihat lelah, dia tampak marah,
dan dia pun menunjukkan wibawa dari seorang pemimpin. Interaksinya bersama Anna
Jacoby-Heron memancarkan kehangatan dalam subplot hubungan ayah dengan anak
perempuannya, sementara Natasha McElhone yang menyimpan kerapuhan dibalik citra
perempuan tangguh yang ditonjolkannya menjadi pendamping yang pantas bagi Penn
di garda terdepan permainan lakon. Keduanya adalah bensin utama dalam
melesatkan narasi dalam The First.
*Saat ini The
First sudah tersedia lengkap sampai episode 8 di situs streaming Mola TV.
Kalian bisa menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar
Rp. 12.500/30 hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan
melalui OVO maupun virtual account.*
REVIEW : ROMULUS (TV SERIES) 31 Dec 2020 1:32 PM (4 years ago)

Jika kamu
menyukai serial berlumurkan intrik, disadur dari cerita epos masa lampau, dan
mempunyai production value mumpuni
dalam merekonstruksi latar waktu, sajian asal Italia yang bertajuk Romulus ini sudah semestinya berada
dalam daftar tontonanmu. Merentang sepanjang 10 episode, serial produksi Sky
Italy yang dikomandoi oleh Matteo Rovere bersama dengan Michele Alhaique dan
Enrico Maria Artale tersebut mencoba merekonstruksi sejarah dibalik berdirinya
kota Roma. Alih-alih mengetengahkan pada legenda Romulus-Remus yang telah
diakrabi oleh para penggandrung kisah-kisah mitologi, serial menghadirkan
interpretasi anyar yang tak kalah menggigitnya dimana plot berkaitan dengan
perebutan tahta kekuasaan, ikatan kekeluargaan, serta peristiwa-peristiwa
supranatural membanjiri setiap episodenya. Romulus
sendiri tak berlama-lama dalam memperkenalkan latar belakang penceritaan dengan
seketika menaikkan intensitas di episode pembuka yang membawa penonton menuju
Alba Longa. Melalui introduksi singkat di awal, kita mengetahui bahwa pada abad
ke-8 sebelum Masehi, area ini tengah dilanda kekeringan berkepanjangan yang
menyulitkan para penduduknya yang mencakup 30 suku untuk memperoleh sumber
pangan memadai serta akses ke air bersih.
Berdasarkan
hasil penerawangan ahli nujum setempat, Numitor (Yorgo Voyagis) – Raja Alba
yang konon ditunjuk sebagai ketua aliansi 30 suku – diminta untuk mengasingkan
diri agar hujan kembali turun di kampung halaman mereka. Dengan demikian, ada
kekosongan pada tampuk kepemimpinan menyusul perginya sang raja. Jika merunut
pada garis keturunan, posisi Raja Alba ini semestinya diwariskan pada salah
satu dari si kembar, Yemos (Andrea Arcangeli) dan Enitos (Giovanni Buselli),
yang merupakan cucu kandung dari Numitor. Tapi keputusan tersebut ditolak
mentah-mentah oleh beberapa raja yang menilai keduanya masih terlalu muda dan
minim pengalaman untuk memimpin 30 suku yang sebelumnya berperang satu sama
lain ini. Seolah keadaan masih belum cukup pelik, kekasih rahasia Enitos
sekaligus pendeta perempuan di Alba, Ilia (Marianna Fontana), mendapat nubuat
dari Dewa yang memperlihatkan masa depan buruk bagi tanah kelahirannya apabila
si kembar tak dipisahkan. Tak ingin pertumpahan darah benar-benar terjadi,
Illia pun meminta Enitos untuk meninggalkan Alba. Belum juga memenuhi
permintaan sang kekasih, Enitos meregang nyawa di tangan sang paman, Amulius
(Sergio Romano), yang dihasut untuk menyulut kemarahan rakyat pada Yemos yang
dinarasikan sebagai pembunuh saudara kandungnya.
Diburu oleh
pasukan Amulius dan masyarakat yang menolak kehadirannya, Yemos pun melarikan
diri ke hutan dimana dia bertemu dengan Wiros (Francesco Di Napoli) dan koloni
anak-anak muda buangan yang liar. Usai beberapa waktu yang sulit untuk
mengenyahkan trauma serta perasaan bersalah atas kematian saudara kembarnya,
ditambah lagi lingkungan barunya juga tak menerimanya dengan ramah, Yemos
akhirnya memberanikan diri untuk merancang strategi pembalasan dendam terhadap
sang paman seraya menyelamatkan Alba dari kehancuran yang lebih dalam. Tunggu,
tunggu, tunggu… sinopsisnya ini kok seperti membeberkan keseluruhan plot dalam Romulus ya? Kalau kamu berpikiran demikian,
jangan dulu merasa gusar. Apa yang saya celotehkan ini hanya mencakup konten
dalam tiga episode pertama – yang mana bahkan belum mencapai setengah dari
total episode. Romulus memang
mempunyai plot sangat padat sehingga menyulitkanmu untuk lengah barang sejenak
lantaran ada banyak karakter, intrik, serta informasi yang harus diproses.
Sepintas memang terdengar berat, tapi keahlian tim penulis skenario dan para
sutradara dalam menyampaikan kisah memungkinkan setiap episodenya menjerat
atensimu. Kamu akan selalu dilingkupi keingintahuan untuk mengetahui apa yang
akan terjadi selanjutnya.
Ya, Romulus memang secandu itu. Terlebih
bagi mereka yang menyukai cerita berisi intrik perebutan kekuasaan. Menariknya
lagi, disamping jago dalam urusan menjaga intensitas yang terus merangkak naik
seiring bergulirnya episode, serial ini pun tak main-main dalam hal tata
produksi. Bukan saja penggambaran dunianya terlihat megah, tetapi juga detil.
Saking niatnya menjaga otentisitas, Romulus
bahkan berani menggunakan Bahasa
Latin Kuno sebagai pengantar ketimbang Italia atau Inggris seperti serial
sejenis (!). Gila, bukan? Tuntutan yang berat ini nyatanya tak menjadi soal
bagi jajaran pemainnya yang sanggup berlakon apik sekaligus membuat kita
semakin merasa terlibat dengan upaya Yemos dalam membersihkan nama baiknya dan
merebut kembali haknya sebagai manusia.
*Saat ini Romulus
sudah tersedia sampai episode 7 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa
menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30
hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui
OVO maupun virtual account.*
SPECIAL - MOLA LIVING LIVE 22 Dec 2020 11:02 PM (4 years ago)

Ada satu original content di Mola TV yang menurut hamba sangat menarik untuk
disimak dan menjadikannya sebagai pembeda dengan jasa penyedia layanan streaming lain, yakni Mola Living Live. Bukan berwujud film
panjang maupun serial, konsep yang dikedepankan oleh acara ini adalah
bincang-bincang. Narasumber yang didatangkan pun tidak main-main; figur publik
kelas dunia, saudara-saudara, tersayang! Tengok saja deretan nama yang sudah
bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara seperti Luc Besson (sutradara),
Darren Aronofsky (sutradara), Spike Lee (sutradara), Sharon Stone (aktris),
Mike Tyson (petinju), sampai Robert De Niro (aktor). Siapa coba yang tidak
mengenal mereka? Lebih-lebih jika kamu menggemari film. Pencapaian yang mereka
torehkan selama berkecimpung di industri film – bahkan Tyson sempat pula
berkontribusi di bidang seni ini – tidaklah main-main. Sebagian diantaranya
telah menggenggam Oscar sebagai penanda pencapaian tertinggi dari sisi
kualitas, sementara sebagian yang lain tergolong akrab dengan kata “box office”
sebagai penanda pencapaian tertinggi dari sisi kuantitas.
Dalam Mola Living Live yang diniatkan sebagai sajian yang menginspirasi sekaligus mencerahkan, tokoh-tokoh tersebut berbagi cerita mengenai perjalanan hidup mereka yang tak selamanya “unicorn and rainbow” atau penuh kesempurnaan. Kepada pembawa acara yang acapkali berganti-ganti di tiap episodenya – dari Reza Rahadian, Rayya Makarim, Timo Tjahjanto, Dino Patti Djalal, sampai Susi Pudjiastuti (ya, Bu Susi yang itu!) – mereka mengungkap kisah-kisah di masa lalu maupun pemikiran-pemikiran yang boleh jadi tak banyak diketahui oleh khalayak ramai. Setelah menyaksikan enam bincang-bincang ini, saya pribadi menyukai episode yang mendatangkan Sharon Stone, Spike Lee, serta Darren Aronofsky. Alasannya sederhana saja, ketiga nama tersebut tampak sangat antusias dalam menanggapi lontaran-lontaran pertanyaan yang diajukan oleh host. Mesti diakui, Reza Rahadian pun sangat bersemangat kala berhadapan dengan narasumber. Dia mempunyai ketertarikan mendalam, dia memiliki keingintahuan menggebu-nggebu, dan penyampaiannya pun luwes. Alhasil, pertanyaan yang meluncur pun mempunyai bobot lebih ketimbang sekadar remeh temeh untuk menghabiskan kuota durasi semata.
Dari Sharon Stone yang sangat
ceria, kita mendengar tentang perjuangannya menapaki karir. Dikaruniai otak
cemerlang, keputusannya untuk menekuni dunia hiburan mulanya digugat
habis-habisan oleh orang tuanya. Bahkan sosoknya yang dijuluki “sex symbol” pernah pula terkendala
dengan bentuk tubuh yang dinilai terlalu besar oleh pelaku industri. Tapi tekad
kuatnya untuk meringankan kondisi finansial keluarganya yang serba pas-pasan –
terlebih sang kakak pun terjeremus ke dunia narkoba – membuatnya memperoleh
banyak tawaran sebagai model iklan. Kala itu, dia mengingat, sebagian besar
pekerjaan diterimanya begitu saja demi membuat dapur tetap ngebul termasuk
peran-peran yang diterimanya di layar lebar. Latar belakang keluarga memaksanya
untuk bersikap realistis ketimbang idealis. Usai satu dekade penuh keringat
serta air mata, karir Mama Stone seketika melesat saat Basic Instinct (1992) meledak luar biasa. Dari mulanya dikenal
sebagai “aktris dari film ono”, berkat film ini statusnya berubah menjadi
aktris papan atas yang dielu-elukan banyak orang. Apakah dia bahagia? Well, untuk sesaat dia menikmati
kesuksesan yang diraihnya sampai pada satu titik dirinya merasa telah direnggut
privasinya. Tak ada waktu untuk kebebasan, tak ada waktu untuk menikmati hasil
perjuangannya.
Sebagai seseorang yang aktif di
belakang layar, Darren Aronofsky dan Spike Lee tidak mendapat pengalaman
tersebut. Akan tetapi, keduanya sama-sama merasakan bagaimana peliknya menggaet
investor untuk mendanai film-film mereka. Apalagi dua sosok ini tidak mementingkan
aspek komersil dalam karya, melainkan pesan yang disampaikan. Ditambah lagi,
baik Aronofsky maupun Lee adalah pribadi yang kontroversial. Aronofsky yang
turut dikenal sebagai aktivis lingkungan enggan berkompromi dengan struktur
penceritaan yang konvensional, sementara Lee tergolong amat vokal dalam
menentang isu rasisme di Amerika Serikat. Meski kerap dihadang
hambatan-hambatan untuk mewujudkan karya, kecintaan keduanya yang sangat
mendalam pada film membuat mereka berhasil bertahan. Lee terus mengingatkan
dirinya sendiri untuk bersyukur karena dia mempunyai pekerjaan impian yang
mayoritas orang di dunia tak memilikinya, dan Aronofsky menjadikan penolakan
demi penolakan yang dihadapinya sebagai pengingat bahwa dia mempunyai sesuatu
yang istimewa serta layak untuk diperjuangkan. Jika kamu menyerah dengan
penolakan, bukankah itu artinya kamu percaya bahwa karyamu memang tak cukup
baik?
Episode Robert De Niro yang baru
saja tayang perdana pada 16 Desember kemarin pun tak kalah menariknya. Beliau
berbagi tentang pengalamannya bekerja sama dengan sutradara langganannya Martin
Scorsese serta ilmu-ilmu keaktoran usai diinterogasi oleh Reza Rahadian yang
penasaran dengan formula dibalik akting yang menghantarkannya pada dua piala
Oscar. Tak hanya Reza, penonton yang menyaksikan secara langsung pada jam 9
malam pun berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Mola Living Live mengondisikan acaranya untuk bersifat interaktif
sehingga kita tak sebatas duduk diam mendengar perbincangan, tetapi juga bisa
ikut berpartisipasi dalam perbincangan tersebut. Asyik, bukan? Untuk bisa
mengakses episode-episode terdahulu dari Mola
Living Live atau menantikan episode selanjutnya yang akan menghadirkan
tokoh lain yang tak kalah hebatnya, kamu cukup mendaftar serta membayar biaya
berlangganan Mola TV. Tenang saja, biayanya tak mahal kok. Paket reguler untuk
satu bulan hanya Rp. 12.500, sedangkan kalau kamu ingin tambahan mengakses HBO
GO bayarnya sebesar Rp. 65.000. Semua pembayaran bisa dilakukan melalui
transfer ATM maupun OVO.
REVIEW : RIG 45 (TV SERIES) 2 Dec 2020 3:34 AM (4 years ago)

“Someone is trying to hide something about the accident.”
Selalu menyenangkan saat kamu
menemukan sebuah film atau serial yang sebelumnya berada di bawah radar banyak
orang dan ternyata mempunyai kualitas di atas rata-rata. Hamba sudah jarang
bereksperimen semacam ini – well,
pandemi membuat saya lebih sering cari aman demi menjaga mood – sehingga saat
memperoleh penugasan untuk mengulas serial asal Swedia bertajuk Rig 45, diri ini sempat was-was.
Lebih-lebih, informasinya di dunia maya pun tak terlampau banyak. Bagaimana
jika ternyata serial tersebut tak ciamik? Atau lebih parah lagi, bagaimana jika
kemudian serial ini tak ubahnya dongeng pengantar tidur? Ya, saya memang
dilanda overthinking selama beberapa
saat yang untungnya tak pernah benar-benar terwujud. Sempat skeptis dengan
kualitas yang ditawarkan oleh Rig 45, alangkah
terkejutnya hamba kala mendapati betapa mengasyikkannya serial sepanjang 6
episode ini. Sebagai penggemar tontonan misteri, guliran pengisahan yang
disodorkan oleh serial produksi Viaplay (televisi berbayar di Swedia) ini
sedikit banyak mengingatkan saya kepada salah satu mahakarya Agatha Christie, And Then There Were None, dimana sepuluh
orang asing diundang ke sebuah pulau oleh seorang misterius dan satu persatu
dari mereka tewas dibunuh.
Dalam Rig 45, para karakter tidak diundang secara khusus ke tempat
terpencil melainkan memang memiliki kepentingan untuk berada di sana. Mereka
yang mempunyai peranan dalam serial ini dideskripsikan sebagai pekerja di
anjungan pengeboran minyak lepas pantai no 45. Total ada tujuh kru yang diberi
porsi tampil signifikan, yakni Mikkel (David Dencik), Douglas (Gary Lewis),
Vidar (Joi Johannsson), Petra (Lisa Henni), Pontus (Bjorn Bengtsson), Mary
(Judith Roddy), serta Halvar (Jakob Oftebro). Konflik dalam serial mencuat dari
sebuah kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu kru bernama Ritva meregang
nyawa. Guna menginvestigasi kasus ini, perusahaan Benthos Oil selaku empunya
anjungan pun mengirimkan pegawainya, Andrea (Catherine Walker), yang kemudian
datang bersama pilot helikopter, Jens (Soren Malling). Setibanya di lokasi,
Andrea mengendus kejanggalan dibalik tewasnya Ritva. Seolah-olah ada yang
berusaha ditutupi oleh para kru. Saat Andrea mencoba menggali informasi lebih
dalam, kecelakaan lain terjadi yang nyaris menewaskan seorang kru. Pada titik
ini, dirinya semakin yakin bahwa peristiwa yang menimpa dua kru tersebut
bukanlah kebetulan. Apalagi informasi yang diterimanya dari kantor pusat
membeberkan sejumlah info mengejutkan. Ditengah badai besar yang menerjang
lautan dan memerangkap karakter-karakter ini di anjungan, Andrea lantas menarik
kesimpulan yang menyatakan bahwa ada seorang pembunuh berdarah dingin diantara
para kru.
Tak butuh waktu lama bagi saya
untuk dibuat kepincut oleh Rig 45 yang
seketika membenamkan penonton ke dalam kasus sedari menit pembuka. Menyaksikan
bagaimana para karakter berbisik-bisik di belakang Andrea, serta
penemuan-penemuan awal dibalik tewasnya Ritva, serta merta menyalakan sinyal
yang menandakan bahwa ada rahasia besar yang berusaha untuk ditutupi di
anjungan 45 ini. Pertanyaannya, apa perkara yang sedang disembunyikan tersebut
sampai-sampai si pelaku merasa perlu untuk melakukan pembunuhan? Tanya ini
tentu tak serta merta terjawab. Demi mengikat perhatian kita, Per Hanefjord
selaku sutradara menebar petunjuk secara bertahap dimana dia menempatkan setiap
karakter dalam posisi abu-abu. Disamping Andrea, tak ada yang bisa benar-benar
kamu percaya di sini. Sosok yang tampak menyambut baik kehadiran sang
penyelidik, Halvar, pun mempunyai masa lalu kelam yang enggan dibagikannya.
Pada satu titik, karakternya bahkan terlihat seperti memanfaatkan keberadaan
Andrea demi mengamankan posisinya. Dalam setiap episodenya, Hanefjord beserta
duo penulis skrip, Ola Noren dan Roland Ulvselius, terus menghadirkan
informasi-informasi baru guna mempermainkan persepsi kita sehingga penonton
kembali mempertanyakan hipotesa yang telah dibangun. Benarkah si A layak untuk
dicurigai? Atau jangan-jangan, ini hanya trik dari si pembuat film untuk
memperdaya penonton?
Ditambah adanya kelokan-kelokan
penceritaan – dimana sang kreator bisa saja membunuh karakter yang tak pernah
kamu duga – Rig 45 jelas terasa
mengasyikkan buat disimak. Hanefjord pun piawai dalam menjaga intensitas yang
memungkinkan setiap episodenya memiliki daya cekam yang konstan dan handal pula
dalam menciptakan atmosfer yang mengusik kenyamanan kita. Latar anjungan yang
terpencil, memiliki ruang gerak terbatas, serta berpencahayaan temaram
menguarkan nuansa klaustrofobik yang pekat. Tanpa adanya pembunuh yang
berkeliaran di sana, dan sebatas mengandalkan amukan alam dalam wujud badai,
sejatinya sudah cukup membuat saya gelisah. Maka begitu ditambah keberadaan
karakter-karakter mencurigakan – yang kesemuanya dimainkan dengan amat baik
oleh jajaran pemain – anjungan 45 adalah deskripsi dari mimpi buruk yang
sesungguhnya. Kamu hanya bisa berdoa dan berharap agar secepatnya hengkang dari
anjungan terkutuk ini. Jika terus bertahan di sana dalam situasi yang sama
sekali tidak kondusif tersebut, tak pelak hanya ada dua pilihan yang tersisa
untukmu, yakni membunuh atau dibunuh.
*Saat ini Rig 45 sudah tersedia
lengkap dari season 1 sampai 2 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa
menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30
hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui
OVO maupun virtual account.*
REVIEW - YOUNGER (TV SERIES) 27 Nov 2020 3:55 AM (4 years ago)

“The problem with memories is they lock us in the past, and we both
need to move forward. As much I want you in my life, I can’t right now. And I
hope you understands why.”
Di masa pandemi yang tak
henti-hentinya menguji kesehatan mental saban hari, menonton film atau serial
ringan yang membuat hati riang gembira adalah jalan ninja hamba untuk menjaga
kewarasan. Beberapa judul urung saya ulas lantaran satu dan lain hal yang mudah-mudahan
lekas terselesaikan, tapi saya mencoba kembali menghadirkan review untuk Younger yang diri ini tonton di Mola TV. Satu judul serial yang
sejatinya telah mengudara sejak tahun 2015 dan musim ketujuhnya kini tengah
dipersiapkan. Diadaptasi dari novel bertajuk serupa rekaan Pamela Redmond
Satran, Younger merupakan tontonan
bergenre komedi yang benar-benar saya butuhkan saat ini. Tiap musimnya hanya
terdiri dari 12 episode – dengan masing-masing episode berdurasi di kisaran 20
sampai 30 menit saja – sehingga memudahkan untuk ditonton secara marathon. Dan
memang, hamba mampu menuntaskan musim pertamanya hanya dalam waktu sehari saja
(!). Betapa tidak, serial ini memiliki segalanya untuk membuatmu jatuh hati seperti:
1) barisan karakter yang mudah untuk disukai, 2) jalinan pengisahan yang
menarik sekaligus dekat dengan persoalan keseharian, dan 3) humor-humor yang
efektif dalam mengocok perut. Mudahnya, apa lagi yang dibutuhkan dari serial
ini? Dengan adanya dua faktor kunci, relatability
and likeability, sudah cukup untuk bikin diri ini kesengsem sampai-sampai
menobatkan Younger sebagai serial
kesayangan saat ini.
Narasi yang diusung oleh Younger sendiri bisa dibilang tergolong
unik. Tentang seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun dari pinggiran kota bernama
Liza Miller (Sutton Foster) yang baru saja bercerai dengan suaminya. Tidak
mempunyai sumber penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Liza
pun nekat “merantau” ke New York City dengan harapan dapat memulai karir baru.
Sayangnya, protagonis kita ini telah menginjak kepala empat dan dia pun tak
memiliki pengalaman kerja selama dua dekade. Alhasil, Liza pun terdampar di
kontrakan sang sahabat, Maggie (Debi Mazar), yang berprofesi sebagai seniman.
Pedih. Di kala harapan sepertinya telah sirna, Liza berjumpa dengan pemuda
berusia 26 tahun, Josh (Nico Tortorella), di bar. Josh yang menaruh hati
kepadanya ini ternyata mengira Liza masih berusia 20 tahunan. Mulanya sih dia
meyakini bahwa Josh sedang mabuk. Tapi Maggie melihat kesalahpahaman ini
sebagai sebuah kesempatan emas untuk menyelamatkan kehidupan finansial
sahabatnya. Dia melontarkan ide, bagaimana jika Liza berpura-pura masih berusia
26 tahun? Toh secara tampang masih memungkinkan – ya, dia awet muda – dan tak
ada pula yang mengenalnya di New York. Jadi tak ada salahnya mencoba, bukan?
Liza yang dihinggapi keragu-raguan pun mencoba mencari pekerjaan dengan
identitas barunya yang tanpa dinyana-nyana membuatnya mendapatkan posisi di
sebuah perusahaan penerbitan buku yang cukup besar!
Dari sinilah Younger lantas berkembang menjadi kian menarik. Memang betul Liza
sudah mempunyai pengalaman di bidang penerbitan sebelum dirinya memilih pensiun
dini dan pengetahuannya soal buku pun melampaui atasannya yang jutek, Diana
Trout (Miriam Shor). Tapi mengaku sebagai gadis berumur 26 tahun membuatnya
menghadapi tantangan-tantangan baru. Baik dari jobdesc dimana dia dituntut untuk menguasai media sosial yang sama
sekali asing baginya, maupun dari pergaulan. Semenjak bekerja di Empirical
Press, dia kerap bergaul dengan editor muda, Kelsey Peters (Hilary Duff), yang
“sebaya” dengannya. Alih-alih memosisikan Kelsey sebagai karakter klise yang
merasa terancam dengan kehadiran pegawai baru berotak cerdas, Darren Star
selaku kreator justru menempatkannya sebagai dewi penyelamat bagi Liza. Berkat
pengetahuan Kelsey yang luas mengenai gaya hidup, si karakter utama secara
perlahan tapi pasti mulai bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya ini.
Dan inilah satu hal yang saya sukai dari Younger,
penuh dengan energi positif. Entah
muncul dari relasi Liza dengan Kelsey, relasi Liza dengan Maggie, maupun relasi
Liza dengan Josh yang belakangan kerap dikencaninya. Bahkan Diana yang tampak
karikatural sebagai perawan tua yang membenci daun-daun muda pun terkadang membentuk
hubungan yang dilandasi respek.
Liza adalah karakter yang
menarik. Sutton Foster yang sepintas seperti perpaduan Yuki Kato dengan Karina
Nadila pun bermain secara meyakinkan sebagai perempuan yang dikira masih hijau
dari sisi usia dan pengalaman hidup. Kita bisa bersimpati kepadanya, kita juga
ingin melihatnya memperoleh kebahagiaan setelah apa yang dilaluinya. Yang
lantas menjadikan Younger terasa kian
menggigit disamping energinya yang tak henti-hentinya membuat saya tersenyum
adalah barisan karakter pendukung yang tak kalah menariknya dibanding Liza.
Maggie yang notabene seniman lesbian kere merepresentasikan kaum marjinal di
kota penuh hiruk pikuk, sementara Kelsey adalah kaum ber-privilege. Serial ini sendiri – setidaknya di musim pertama – tak
pernah mengulik persoalan tersebut secara mendalam karena Darren Star lebih
tertarik untuk mengedepankan girl power
dimana perempuan-perempuan tersebut saling bahu membahu dalam menuntaskan
problematika masing-masing. Dari awalnya tampak seperti tontonan hore-hore
belaka, Younger lantas berkembang
menjadi sajian yang juga hangat saat hubungan antar karakternya kian intim. Chemistry apik yang terbentuk diantara
pemain memungkinkan bagi penonton untuk menaruh afeksi kepada mereka. Saya
pribadi menyukai hubungan Liza dengan Kelsey yang bukan saja tampak seperti
pertemanan, tapi juga ibu dan anak. Relasinya bersama Kelsey menyadarkannya
untuk menjalin komunikasi lebih baik dengan putri semata wayangnya yang kini
sedang menjalani program pertukaran pelajar di India. Manis.
*Saat ini Younger sudah tersedia
dari season 1 sampai 6 di situs streaming Mola TV. Kalian bisa menontonnya
dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar Rp. 12.500/30 hari. Murah
sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat dilakukan melalui OVO maupun
virtual account.*
REVIEW - HUMANS (TV SERIES) 3 Nov 2020 11:18 PM (4 years ago)

“You cannot fix humanity’s problems with technology.”
Pernah tidak membayangkan
memiliki robot yang bisa mengerjakan semua hal? Maksud saya, robot yang bisa
beberes rumah sampai kinclong, bisa bertindak selaiknya pelatih atau perawat
profesional, sampai bisa memasak berbagai jenis makanan sehingga tak perlu repot-repot
ke restoran. Terdengar menyenangkan, bukan? Praktis. Serial asal Inggris, Humans, yang dikreasi oleh Sam Vincent
dan Jonathan Brackley berdasarkan serial dari Swedia bertajuk Real Humans ini menerapkan premis
tersebut untuk diejawantahkan menjadi tontonan sepanjang tiga musim. Memberi
kita gambaran seandainya robot mempunyai peranan lebih krusial dalam setiap
lini kehidupan, ketimbang sebatas didayagunakan oleh korporasi-korporasi
raksasa. Demi menjadikannya kian menarik, sang kreator pun tak mendeskripsikan
robot-robot ini selaiknya mesin biasa atau menyerupai kaleng berwarna perak.
Melainkan diperlihatkan seperti halnya manusia sampai-sampai kamu tak bisa
membedakannya hanya dari pandangan secara sekilas. Bahkan, beberapa robot yang
menjadi sentral penceritaan dalam Humans
dikisahkan mempunyai emosi yang menjadikan batasan antara realita dan teknologi
menjadi kian mengabur.
Salah satu robot tersebut adalah Anita (Gemma Chan) yang “diadopsi” oleh keluarga Hawkins demi mengurus segala tetek bengek berkaitan dengan urusan rumah tangga. Sang kepala keluarga, Joe (Tom Goodman-Hill), merasa kewalahan mengurus ketiga anaknya lantaran istrinya, Laura (Katherine Parkinson), kerap disibukkan oleh pekerjaannya sebagai pengacara. Meski kehadiran Anita sendiri disambut baik oleh Joe maupun si bungsu, Laura beserta putri sulungnya, Mattie (Lucy Carless), justru terusik dengan keberadaan robot yang disebut sebagai synth tersebut. Laura menaruh kecurigaan kepada Anita yang dianggapnya berniat menggantikan posisinya sebagai seorang ibu dalam keluarga Hawkins, sementara Mattie sendiri menaruh kebencian secara umum kepada synth yang dinilainya mengancam keberadaan umat manusia. Betapa tidak, synth yang didesain sebagai robot multifungsi ini membuat manusia mengalami ketergantungan dan lapangan pekerjaan pun kian mengecil akibat penggunaannya yang semakin masif. Bukankah ini berbahaya? Berkelindan bersama narasi yang berporos pada keluarga Hawkins adalah tiga plot yang menyoroti seseorang dari masa lalu Anita, dua detektif, serta seorang pria tua yang memiliki hubungan erat dengan synth miliknya.
Ya, Humans tidak hanya meletakkan fokus penceritaannya terhadap
permasalahan pelik yang menghinggapi keluarga Hawkins akibat keberadaan sebuah
robot. Anita sendiri mempunyai latar belakang yang telah diungkap sekelumit
sedari episode-episode awal. Seperti telah dicurigai oleh Laura, synth tersebut bukanlah produk biasa
yang sebatas tunduk kepada prosedur maupun perintah yang dialamatkan kepadanya.
Dia mempunyai emosi, dia pun memiliki kesadaran atas tindakan-tindakannya yang
menjadikannya menyerupai manusia. Dari pancingan berwujud flashback yang memberikan informasi mengenai nama asli Anita
berikut kawanannya – synth yang
memiliki kesadaran – inilah Humans lantas menggelembungkan kepenasaran hamba.
Saya bertanya-tanya, siapa sebenarnya Anita? Mengapa dia bisa berbeda dibanding
robot-robot sejenisnya? Apakah ada misi tertentu yang dibebankan untuknya? Pada
saat bersamaan, rekan-rekan Anita dari masa lalu terlibat dalam kasus kriminal
yang menghadapkan mereka dengan pihak kepolisian serta sekelompok peneliti yang
mempunyai kepentingan. Melalui cabang penceritaan tersebut, serial menguarkan
aroma thriller dengan tingkatan intensitas berada di level sedang yang sudah cukup
untuk membuat penonton menginvestasikan waktu dan emosinya.
Namun Humans tak hanya menggaet atensi kita lewat serentetan misteri yang
dikedepankannya, tetapi juga lewat isu yang dibawakannya. Serial ini meminta
penonton untuk mempertanyakan soal kemanusiaan, kecerdasan buatan, serta
teknologi. Tentang bagaimana kemajuan teknologi mereduksi interaksi antara
sesama manusia, tentang bagaimana keahlian manusia tergantikan oleh robot yang
kinerjanya bisa ditekan melampaui batas, dan tentang bagaimana hati nurani
dipinggirkan lantaran robot tak memiliki emosi. Tapi bagaimana jika kemudian
robot tersebut mempunyai kesadaran seperti halnya Anita? Apakah kita akan tetap
bersikap semena-mena kepadanya karena secara teknis dia bukan makhluk hidup
ciptaan Tuhan, atau kita akan memerlakukannya seperti manusia? Humans membawa perenungan tersebut
kepada kita. Meski mungkin synth tak
akan terwujud dalam waktu dekat, persoalan terkait relasi sosial yang
merenggang akibat teknologi terasa nyambung dengan keadaan masa kini. Pemicunya
tidak berasal dari robot yang bisa dipergunakan sesuka hati melainkan dari
media sosial dan internet. Ya, seperti halnya synth, dua produk teknologi tersebut tadinya diciptakan dengan
harapan dapat mempermudah segala permasalahan umat manusia. Tapi ironisnya,
efek samping yang diberikannya justru dapat memberikan dampak negatif terhadap
kemanusiaan. Mengerikan.
*Saat ini Humans sudah tersedia
dari season 1 sampai 3 di situs streaming Mola TV.
Kalian bisa menontonnya dengan mendaftar dan membayar paket langganan sebesar
Rp. 12.500/30 hari. Murah sekali dan mudah sekali karena pembayaran dapat
dilakukan melalui OVO maupun virtual account.*
REVIEW : PELUKIS HANTU 17 Oct 2020 8:59 PM (4 years ago)

“Kita bisa mengusahakan kebahagiaan di masa depan, selama kita jujur
dan tulus memberikan kemampuan terbaik kita.”
Pelukis Hantu adalah film yang menyenangkan. Begitulah kesan
pertama yang tergores selepas menontonnya. Sepintas lalu, tontonan yang
mengombinasikan genre horor dan komedi ini memang terlihat seperti sajian seram
kelas B yang dibuat untuk mengeruk keuntungan semata tanpa peduli kualitas – jejak
rekam genre ini tak cihuy. Lebih-lebih, MD Pictures memutuskan untuk
menerjunkannya secara langsung ke layanan penyedia streaming yang tentu memantik kecurigaan hamba: kenapa? Maklum,
pengalaman menonton film Indonesia dalam satu bulan terakhir ini sungguh bikin
kepala nyut-nyutan sehingga keragu-raguan pun melejit ke angkasa. Sungguh, saya
telah berpasrah kepada Tuhan. Akan tetapi, Pelukis
Hantu yang menandai untuk pertama kalinya Arie Kriting memulai debut
penyutradaraannya, menunjukkan bahwa masihlah ada harapan terhadap produk yang
dilempar ke OTT (over the top atau
layanan streaming). Mengikuti jejak
rekannya sesama komika, Bene Dion, yang tahun lalu menghasilkan Ghost Writer yang mengesankan, Bung Arie
mencoba untuk menghadirkan sebuah sajian hiburan yang tak saja membuat
penontonnya tergelak-gelak sekaligus terperanjat, tetapi juga mendapatkan
sesuatu. Ya, dia turut memasukkan hati ke dalam penceritaan demi menguarkan
sisi emosional dari penceritaan serta isu yang kompleks mengenai luka dan
trauma. Sebuah langkah yang terhitung berani untuk karya perdana.
Dalam Pelukis Hantu, kita diperkenalkan pada seorang pelukis amatir
bernama Tutur (Ge Pamungkas) yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran
karya-karyanya tak laku terjual. Padahal di waktu bersamaan, dia harus membayar
biaya pengobatan ibunya, Ana (Aida Nurmala), yang sedang sakit keras. Saat
harapan seperti telah mengabur, Tutur menerima telepon dari teman lamanya, Udin
(Abdur Arsyad), yang mengabarinya mengenai lowongan untuk menjadi salah satu
pengisi acara dalam sebuah program mistis di televisi. Bukan sembarang pengisi
acara, melainkan menempati posisi “pelukis hantu” dimana dia harus melukis
memedi dengan mata tertutup. Sebagai seseorang yang memiliki idealisme tinggi –
plus dia tak punya bakat melihat makhluk gaib – Tutur sempat dirundung keraguan
karena merasa sudah membohongi publik. Tapi berhubung dia tak punya pilihan
lain, mengapa tidak dicoba saja dulu? Pada awalnya, protagonis kita ini
berpura-pura saja memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam lain
sampai kemudian… kemampuan itu benar-benar menghinggapinya (!). Sesosok
kuntilanak kerap menampakkan diri di hadapannya setiap kali matanya ditutup. Di
satu sisi, penampakan ini jelas membantu kelancaran karirnya. Namun di sisi
lain, Tutur mulai mempertanyakan motif si kuntilanak. Dia menduga, ada pesan penting
yang sejatinya ingin disampaikan kepadanya. Dibantu oleh seorang blogger spesialis supranatural, Amanda (Michelle Ziudith), dan Udin, Tutur pun berupaya untuk menyibak
misteri dibalik kemunculan Mbak Kunti yang ternyata berkaitan dengan tragedi
masa lampau.
Menilik latar belakang Arie
sebagai seorang komika, tidak mengherankan saat kemudian Pelukis Hantu yang naskahnya juga dia tulis menunjukkan
keunggulannya dalam hal ngelaba. Kecakapannya dalam mengatur tempo, menggali
materi, sekaligus dukungan para pelakon memungkinkan untuk sebagian besar humor
meluncur secara mulus. Saya berulang kali tergelak-gelak mendengar kelakarnya
yang menyentil sana-sini – khususnya sektor hiburan dan politik – lalu bermain-main
dengan kata, sampai menyelipkan referensi ke budaya populer. Yang menarik,
humor yang dikedepankan oleh film ini terintegrasi dengan plot utama alih-alih
muncul secara acak entah darimana bak kumpulan-kumpulan sketsa. Memanfaatkan
situasi tidak wajar si karakter utama yang kemudian melahirkan celetukan maupun
tektokan menggelitik diantara para tokoh. Secara pribadi, saya menyukai
keberadaan Abdur Arsyad di sini yang digambarkan sebagai karakter oportunis
dengan kemampuan otak yang, well…
pas-pasan, serta Hifdzi Khoir sebagai produser serakah yang hanya memikirkan
satu hal: rating. Momen-momen terlucu dalam Pelukis
Hantu mencuat saat melibatkan dua manusia tersebut. Ekspresi, penyampaian,
serta timing-nya diperhitungkan
secara jeli. Membuat saya seketika mengurungkan niat untuk menggampar keduanya dengan
kanvas lantaran karakternya yang didesain menyebalkan. Pengen banget tak hih,
tapi kok ya kocak jadi bisalah sedikit diampuni tingkah polahnya yang naudzubillah itu.
Keduanya mencuri lampu sorot dari
Ge Pamungkas dan Michelle Ziudith selaku bintang utama yang cenderung fluktuatif.
Saat mendapat tugas untuk melucu, Ge sejatinya tidak mengalami kendala. Tapi ketika
giliran untuk berlakon serius tiba dimana Tutur harus mengeluarkan segala perasaan
terpendamnya, pada saat itulah Ge menunjukkan keterbatasannya. Tak ada emosi
yang tersalurkan kepada penonton sehingga mereduksi kesempatan bagi film untuk
mengundang air mata. Jujur saja, saya menyayangkannya mengingat babak ketiga Pelukis Hantu yang mengedepankan topik mengenai
“berdamai dengan luka” memiliki potensi untuk menggerus hati. Michelle Ziudith
yang memiliki jam terbang lebih tinggi
perkara menangani momen dramatik pun tak banyak membantu. Karakternya tak
mengalami perkembangan berarti dan seolah-olah hanya diposisikan sebagai love interest semata bagi Tutur. Bahkan,
konflik personalnya dengan keluarga perlahan terpinggirkan saat pencarian Tutur
semakin dalam. Michelle juga mendapat kesempatan amat minim untuk bersenda
gurau, padahal hey, lihatlah betapa lucunya dia di Mekah I’m Coming tempo hari. Saya membayangkan, film mungkin akan menjadi
lebih asyik apabila Amanda dengan penampilan bak cenayangnya ini tidak diberi
plot percintaan dan lebih sebagai partner
in crime yang gila bagi duo Tutur-Udin. Buat rekan tektokannya Udin yang
hanya butuh sedikit lagi pemantik agar celetukannya semakin tidak terkontrol
sehingga membuat karakter utama kita terus menerus pusing tujuh keliling di
kala mencari kebenaran soal Mbak Kunti.
Pun begitu, meski Pelukis Hantu agak sedikit bermasalah di
sektor drama yang kurang greget dan titik penyelesaiannya pun tidak seemosional yang diharapkan,
film masih jago dalam hal bersenang-senang. Membuktikan bahwa Arie adalah
sutradara pendatang baru yang karirnya patut diwaspadai. Selama 97 menit, saya
mendapati tontonan hiburan pelepas penat yang memang dibutuhkan di masa-masa sulit
seperti ini. Elemen horornya sendiri tidak sepekat komedinya, bahkan cukup minim. Tapi Arie mampu
menghadirkan satu dua trik menakut-nakuti yang membuat hamba terlonjak dari
kursi. Ditambah lagi, riasan wajah untuk Kuntilanak tergolong mengerikan. Jadi
bagaimana mungkin diri ini bisa duduk dengan tenang saat sosoknya tiba-tiba nongol
seolah ingin menerkam penonton? Sungguh tidak ada akhlak.
Bisa ditonton di Disney+ Hotstar
Indonesia
Exceeds Expectations (3,5/5)
REVIEW : SEPERTI HUJAN YANG JATUH KE BUMI 16 Oct 2020 5:15 AM (4 years ago)

“Melarikan diri dari rasa sakit hati itu, enggak akan membuat kita
lebih baik. Sakit hati itu harus kita nikmati.”
Terlampau sering di dalam rumah
selama pandemi Covid-19, membuat pikiran saya sering melantur kemana-mana. Pernah
pada suatu hari yang tidak terlalu indah, saya mendadak punya keinginan amat random, “duh pengen deh nonton film percintaan remajanya Screenplay Films yang
ajaib itu. Udah lama sekali rasanya.” Ternyata, dari sekian banyak doa yang
pernah hamba rapalkan, doa ini termasuk yang dikabulkan secara cepat oleh Tuhan.
Tiba-tiba saja rumah produksi ini, bekerjasama dengan IFI Sinema dan Netflix,
meluncurkan Seperti Hujan yang Jatuh ke
Bumi ke raksasa penyedia layanan streaming.
Film romansa yang didasarkan pada novel laris bertajuk sama rekaan Boy Candra
(karyanya yang lain, Malik dan Elsa,
pun sudah diadaptasi) ini memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi
sajian cinta-cintaan khas Screenplay. Di sini, kamu bisa mendapati: 1) jalinan
penceritaan yang agak sulit dibayangkan akan terwujud dalam kehidupan nyata, 2)
dialog berisi untaian kata-kata puitis yang diucapkan oleh para karakter dalam
setiap hembusan nafas mereka, dan 3) production
value yang tampak berkelas guna membedakannya dengan sajian-sajian serupa
yang khusus ditayangkan di stasiun televisi. Terdengar menyiksa menarik,
bukan? Tentu saja, seperti sudah hamba duga sebelumnya, film ini pun tak kalah
ajaibnya sekalipun telah merekrut nama-nama seperti Lasja F Susatyo (Mika, Sebelum Pagi Terulang Kembali) sebagai sutradara, serta Upi (Teman Tapi Menikah, My Stupid Boss) dan Piu Syarif (Moammar
Emka’s Jakarta Undercover) sebagai penulis skenario.
Yaaa namanya juga cinta. Manusia
bisa mengabaikan logika dan enggan memberikan alasan saat sudah kepincut dengan
seseorang. Seperti Hujan yang Jatuh ke
Bumi pun demikian. Saya tak pernah bisa memahami jalan pikiran para
karakternya sampai pada satu titik akhirnya memilih untuk menyerah, lalu teringat
pada permintaan hamba yang acak. “Bukankah
kamu sendiri yang mendamba tontonan percintaan ajaib? Sekarang sudah di depan
mata lho, nikmati saja keajaibannya.” Begini nih Bun akibatnya kalau berdoa
sembarangan ke Tuhan, ku-a-lat. Sebetulnya sih film ini memulai penceritaan
dengan cukup meyakinkan. Chemistry antara
Jefri Nichol dan Aurora Ribero yang asyik seolah mengindikasikan kalau kisah
asmara di sini akan menggemaskan. Bahkan, saya sempat tersipu-sipu gemas
menyaksikan interaksi keduanya yang memang menjadi keunggulan utama film ini.
Bung Nichol memainkan peran sedikit berbeda dari biasanya dengan menjelma
sebagai aktivis lingkungan yang selalu
menggalau lantaran tak sanggup mengutarakan rasa. Dia bermain meyakinkan, begitu
pula Aurora yang enerjik dan senantiasa menyebarkan energi positif ditengah
nada penceritaan yang sendu. Saya sempat mengira, Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi akan meletakkan fokusnya pada dinamika
hubungan berstatus friendzone dari
dua manusia ini. Apalagi selepas Nara berjanji tak lagi-lagi mudah hati kepada
laki-laki. Tapi ternyata, film mengedepankan dua karakter lagi ke arena utama
penceritaan yang alih-alih membuat kisahnya menjadi kian menarik, malah justru
membuatnya terasa membosankan.
Masalah utamanya, karakter Juned
tak pernah benar-benar terlihat meyakinkan untuk menjadi seseorang yang membuat
Nara mengingkari janjinya sendiri. Satu hal yang saya pertanyakan, kenapa Nara
bisa mendadak kepincut dengan Junaedi sementara pertemuan pertama mereka
meninggalkan kesan buruk? Apa yang menyebabkan Nara berubah pikiran sedemikian
cepat apalagi di waktu yang sama dia sudah tak ingin lagi disakiti? Bukankah memilih
untuk kembali membuka diri kepada lelaki yang telah memperlakukannya dengan tak
hormat itu beresiko? Jujur, hamba bingung dengan jalan pikiran Dek Nara ini.
Andai keputusannya dilandasi oleh keinginan membalas dendam kepada Kevin yang
tidak tegas – terus-terusan maju mundur untuk mendeklarasikan cintanya kepada
Nara – sejatinya saya bisa mafhum. Tapi kenyataannya tak demikian,
saudara-saudara. Dia pun diperlihatkan kesengsem betulan kepada Juned yang
selalu diceramahi oleh ibunya (Karina Suwandi) dengan tema, “bukalah hatimu, Nak. Move on.” Ditambah
akting datar tanpa ekspresi dari Axel Matthew Thomas, makin tak bisa pahamlah
hamba mengapa Nara bisa sebegitu cintanya dengan lelaki yang selalu bersikap
sengak kepada orang-orang yang ditemuinya ini, termasuk kepada Kevin yang
membawa pada kesimpulan bahwa perangainya memanglah menyebalkan bukan karena
trauma patah hati. Atau, ini semata-mata kesalahan Axel dalam
menginterpretasikan peran? Entahlah. Yang jelas, interaksi mereka berlangsung
anyep, konflik yang mengemuka pun terasa repetitif. Belum ada separuh jalan
sudah kebosanan.
Diri ini sejatinya masih sanggup
menerima dialog-dialog puitisnya yang menggelikan (meski tetap belum bisa
mengalahkan mahakarya Bunda Tisa TS). Namun melihat Nara-Juned berduaan tanpa
ada chemistry atau menyaksikan kebersamaan
Kevin-Tiara yang dinaungi awan gelap, rasanya ingin bobo mumpung lagi hujan.
Tanpa sokongan akting apik duo pemain utama dan elemen teknis bekerja dengan
baik seperti sinematografi serta iringan musik, mungkin Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi sudah membawa saya ke alam mimpi
sedari awal.
Bisa ditonton di Netflix
Acceptable (2,5/5)
REVIEW : BIDADARI MENCARI SAYAP 13 Oct 2020 11:24 PM (4 years ago)

“Dalam rumah tangga itu ada nilai hormat. Nggak melulu cinta.”
Cinta terhalang perbedaan etnis
dan keyakinan sejatinya sudah beberapa kali dijadikan topik pembicaraan dalam
sejumlah film Indonesia. Ada yang disisipkan sebagai subplot belaka, tapi tak
sedikit pula yang diajukan sebagai konflik utama. Judul-judul yang saya nilai
berhasil mengulik isu sensitif ini antara lain Cin(T)a (2009), 3 Hati Dua
Dunia Satu Cinta (2010), serta Cinta
Tapi Beda (2012). Ketiganya memberikan gambaran mengenai peliknya memadu
kasih di Indonesia kala dua belah pihak menganut agama yang berlainan. Salah
satu dari mereka harus ada yang bersedia mengalah dengan melepaskan keyakinan
apabila ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila sama-sama kekeuh, maka tentu mustahil untuk
merealisasikan sebuah rumah tangga terlebih dalam khasanah sinema dalam negeri.
Keengganan sineas untuk menghadapi kecaman publik – yang selalu mengikuti tiap
kali muncul film bertema toleransi dalam perbedaan – membuat film memilih jalan
aman dalam konklusi: memenangkan agama alih-alih cinta. Kalaupun ada yang kemudian
berpindah agama, jelas bukan dari kalangan mayoritas kecuali siap menerima
konsekuensi. Bidadari Mencari Sayap
produksi Citra Sinema bersama MD Pictures yang mencoba lebih “berani” dengan
meletakkan fokusnya pada kehidupan rumah tangga ketimbang sebatas berpacaran
seperti film sejenisnya, adalah contoh. Si karakter perempuan yang notabene
non-Muslim (tidak disebutkan secara spesifik agamanya) dikisahkan menjadi
mualaf untuk bisa menikahi kekasihnya yang berasal dari keluarga Muslim taat.
Karakter perempuan yang dimaksud
bernama Angela (Leony Vitria Hartanti). Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup
nyaman bersama suaminya, Reza (Rizky Hanggono), putra semata wayangnya, serta
ayahnya yang dipanggil Babah (Nano Riantiarno). Meski telah bertahun-tahun
menikah, pasangan ini nyatanya masih kesulitan untuk menyatukan jurang
perbedaan diantara mereka. Reza selalu merasa terusik dengan komentar-komentar
menyentil yang kerap dilontarkan Babah, sementara Angela belum kunjung bersedia
untuk mengenakan hijab sekalipun telah disindir terus menerus oleh mertuanya.
Seolah keadaan masih belum cukup pelik bagi pasangan ini, Babah sering membawa
makanan atau hewan yang dipandang haram oleh Reza tanpa meminta persetujuan
terlebih dahulu. Berhubung dua belah pihak sama-sama mudah tersulut emosi – dan
enggan pula untuk saling memahami keadaan masing-masing – maka pertengkaran
demi pertengkaran pun kerap terjadi. Pertengkaran yang sebetulnya bisa saja
diselesaikan secara mudah melalui dialog hati ke hati, tapi justru dipersulit
saat Reza memilih untuk hengkang sementara dari rumah. Alasannya sih karena
dikirim atasannya untuk tugas di luar kota. Padahal kenyataan yang sebenarnya,
dia dipecat dari pekerjaannya dan terlalu malu untuk mengakuinya kepada Angela.
Ya, Reza terlalu malas untuk menghadapi perdebatan-perdebatan tak penting
dengan sang istri di saat dia tengah berupaya untuk merintis karir sebagai
supir taksi online.
Harus diakui, perdebatan yang
mencuat dalam Bidadari Mencari Sayap
memanglah tidak penting. Kalau enggan disebut, mengada-ada. Andai saja ini
berlangsung ketika usia pernikahan Reza-Angela masih seumur jagung, bisalah
dipahami. Dua manusia dari dua dunia yang bertolak belakang sama-sama mengalami
gegar budaya, seperti bagaimana Angela yang mualaf meraba-raba mengenai
kepercayaan barunya dan Reza yang berpikiran konservatif mesti beradaptasi
dengan gaya hidup keluarga istrinya. Tapi saat keduanya sudah dikaruniai anak –
bahkan si anak sudah bersekolah pula yang artinya mereka telah menikah
setidaknya selama 6 tahun – adanya pertengkaran besar yang dipantik oleh babi,
anjing, atau hijab jelas membuat hamba mengernyitkan dahi. Kalau begitu, itu
artinya mereka tak pernah membahas permasalahan ini di awal-awal menikah dong?
Mereka tak pernah mendiskusikannya, tak pernah mencari solusinya, dan terus
membiarkannya berlarut-larut sehingga kerap berulang setiap tahunnya (atau
setiap harinya). Jika benar demikian, kok sanggup ya bertahan dalam pernikahan
yang sedemikian toxic-nya? Apa karena
ingin menjaga reputasi keluarga masing-masing sehingga bercerai tak pernah
menjadi opsi? Atau jangan-jangan hanya ingin tampil dramatis saja? Aria Kusumadewa yang menyutradarai sekaligus menulis naskahnya
tidak pernah juga memberi alasan untuk menguatkan latar belakang dibalik upaya
keduanya bertahan. Malah, dalam satu adegan Reza berujar, “aku sangat mencintai istriku,” yang ingin rasanya saya balas, “Mbel, cinta kok ditarung tiap hari. Itu
rumah tangga apa Rumah Uya kok isinya ribut mulu?”
Alhasil, sulit untuk bersimpati
kepada dua tokoh utama dalam film ini. Mereka tampak sangat egois dan
menyebalkan. Maksud saya, mereka bisa lho berdialog dengan Babah atau Ibu Reza
soal letak keberatan masing-masing, apalagi Babah tidak juga digambarkan
sebagai mertua yang gemar menyiksa menantunya. Malah, beliau yang terlihat
tertindas di film ini. Reza gemar marah-marah untuk menyikapi setiap persoalan,
sementara Angela pun setali tiga uang. Saya sampai kagum Babah masih sehat
walafiat walau dikelilingi representasi nyata dari netizen julid dan tukang tubir.
Sepanjang durasi Bidadari Mencari Sayap mengalun, isinya hanyalah letupan-letupan amarah, penuh karakter-karakter pendukung bersliweran yang hampir kesemuanya tidak diberi manfaat, dan dialog-dialog kaku (yang tak bisa hamba bayangkan bakal diucapkan oleh
manusia di kehidupan sehari-hari) berisi pesan moral. Dalam setiap langkah
kaki, dalam setiap hembusan nafas, dan dalam setiap kedipan mata, kamu akan
mendengar salah satu karakternya memberikan kritik maupun wejangan
sampai-sampai saya lupa kalau sedang menonton film. Saya mengira sedang
mendengarkan khatib menyampaikan khotbah dalam Sholat Jumat. Sungguh, rasanya
ingin seketika bertaubat karena sudah menyia-nyiakan waktu berharga.
Diri ini tentu paham betul bahwa Bidadari
Mencari Sayap mempunyai tujuan mulia yakni mengajak publik untuk menghargai
perbedaan – apapun itu wujudnya. Mengampanyekan toleransi ditengah iklim yang
kian memecah belah masyarakat Indonesia. Namun, menjejalkan nasihat dalam
setiap dialog yang menjadikannya terdengar amat ceriwis dan menghadirkan
jalinan pengisahan yang sulit diterima oleh logika jelas tidaklah efektif. Apalagi
saat si pembuat film turut menyodorkan konklusi problematis yang membuat saya
kembali mempertanyakan tentang pesan yang sebenarnya ingin disampaikan.
Bisa ditonton di Disney+ Hostar
Indonesia
Poor (2/5)
REVIEW : WARKOP DKI REBORN 4 12 Oct 2020 6:10 AM (4 years ago)

“Lagian mana ada sih orang kaya mukanya kek bemo.”
Saat para karakter inti dalam Warkop DKI Reborn 3 kembali muncul di end credit untuk mendendangkan “ahaaa… filmnya dibagi dua, filmnya dibagi
dua,” saya sama sekali tidak terkejut. Maklum, bukan pertama kalinya
mendapat prank semacam ini dari film
Indonesia. Pun begitu, bukan berarti hamba tidak ingin mengelus dada kala momen
musikal tersebut muncul. Andai saja film yang baru ditonton sanggup menghadirkan
pengalaman penuh kesenangan di sepanjang durasinya, hadirnya bagian kedua tentu
akan disambut dengan penuh suka cita – saya pribadi termasuk golongan yang
tidak keberatan dengan keberadaan Warkop
DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2. Tapi berhubung babak pertamanya lebih
sering membuat saya menertawakan keputusan diri sendiri untuk menonton film
tersebut ketimbang menertawakan humor-humornya, ada kebingungan melanda. Ada
pertanyaan berkecamuk yang dimulai dengan, “mengapa
sih harus dibagi dua? Apa urgensinya?.” Seolah pihak Falcon Pictures sangat
percaya diri instalmen reborn terbaru
ini akan disambut antusias oleh publik. Kenyataannya, hanya sekitar 800 ribu
penonton yang bersedia berbondong-bondong mendatangi bioskop sehingga memaksa
rumah produksi untuk mengganti strategi. Alih-alih mengedarkannya di bioskop,
mereka memilih untuk langsung menerjunkan Warkop
DKI Reborn 4 ke penyedia layanan streaming
film dengan harapan bisa sekalian menghibur masyarakat semasa pandemi di rumah.
Walau kalau boleh berkata jujur, kata “menghibur” untuk mendeskripsikan film
ini terasa terlalu murah hati.
Sekadar mengingatkan lagi
barangkali sudah lupa dengan plot di seri sebelumnya, personil Warkop DKI yang
terdiri atas Dono (Aliando Syarief), Kasino (Adipati Dolken), dan Indro (Randy
Danistha) direkrut oleh Komando Cok (Indro Warkop) untuk menyelidiki tentang aktivitas
pencucian uang dalam perfilman Indonesia. Akan tetapi ditengah berjalannya
proses investigasi, trio ini justru jatuh pingsan ke dalam kotak dan terbangun
di padang gurun Maroko yang tandus. Dalam upaya mencari Inka (Salshabilla
Adriani), lawan main mereka di film yang diketahui ikut terjebak di kotak,
ketiganya mendapat bantuan dari penduduk setempat, Aisyah (Aurora Ribero) dan
Ahmed (Dewa Dayana). Warkop DKI Reborn 4 menyoroti
upaya lima sekawan tersebut untuk menemukan jejak-jejak keberadaan Inka yang
membawa mereka menghadapi penduduk satu kampung yang penuh lelaki hidung belang,
serta mempertemukan mereka dengan seorang bos mafia berbahaya bernama Aminta
Bacem (diperankan oleh Rajkumar Bakhtiani – impersonator Amitabh Bachchan). Seolah
kawanan ini masih belum cukup mempersulit pencarian terhadap Inka yang
menghilang entah kemana, Warkop DKI juga tetap harus memburu Amir Muka
(Ganindra Bimo) yang menjadi tersangka utama dalam kasus money laundry dan konon sedang beredar di Maroko.
Pada dasarnya, tak banyak yang
bisa diceritakan dalam Warkop DKI Reborn
4 yang konfliknya serasa pengulangan dari seri sebelumnya. Masih
berhubungan dengan penduduk suatu kampung yang sekali ini mengincar Aisyah
sebagai bentuk timbal balik untuk bantuan yang mereka berikan. Meski kita
sama-sama tahu bahwa para protagonis akan bisa meloloskan diri dengan mudah,
tapi proses untuk menuju hasil tersebut tak pernah sekalipun mencengkram.
Apalagi mengundang gelak tawa. Mengalun dengan amat lempeng seperti halnya
personil Warkop DKI (dan juga ekspresi wajah hamba) yang menganggap
pertarungan melawan warga-warga terkuat di desa bukan persoalan besar.
Pertaruhan terhadap nasib Aisyah pun tidak tampak sehingga kalaupun dia diserahkan
kepada si pemimpin desa, siapa sih yang akan merasa kehilangan? Seiring
berjalannya durasi, kehadirannya semata-mata diposisikan sebagai damsel in distress demi memberi alasan
bagi Dono dan konco-konco untuk berbuat sesuatu sekaligus menjadi objek fantasi
bagi Kasino. Walau ya, paling tidak karakternya masih lebih berguna daripada
Ahmed yang tak ubahnya tim penggembira saja di seri ini. Tidak ada peran
signifikan baginya, bahkan sesi latihan bersama Kasino-Indro semata-mata untuk
lucu-lucuan saja tanpa ada keterkaitan dengan pertandingan yang berlangsung
sesuka hati atas nama humor. Sedari titik ini pula, film yang penulisan
naskahnya ditangani oleh Anggoro Saronto bersama Rako Prijanto (yang juga
menduduki posisi sutradara) ini mulai mengabaikan adanya sebab-akibat dalam
penceritaan.
Warkop DKI Reborn 4 seringkali tersusun atas kumpulan-kumpulan segmen yang tidak memiliki korelasi antara satu dengan yang lain hanya untuk menunjukkan betapa besarnya biaya produksi yang digelontorkan, atau (lagi-lagi) atas nama humor. Tidak masalah sebetulnya karena toh Jangkrik Boss pun melakukannya. Yang kemudian membedakannya: 1) Babak kedua Jangkrik Boss masih menganggap babak pertamanya ada, tak seperti film ini yang narasinya melenceng sampai-sampai membuat kita lupa dengan jalan cerita dari film terdahulu. 2) Anggy Umbara lebih terampil dalam menangani momen laga yang memiliki excitement atau melontarkan banyolan nyeleneh, sementara Rako cenderung kewalahan. Nyaris tiada tenaga dalam elemen aksi maupun komediknya. Hambar. Beliau memang sudah memperoleh bantuan dari tim tata produksi yang memaksimalkan latar dengan baik dengan menguarkan sisi eksotis dari Maroko. Beliau pun mendapat sokongan dari trio pemain utamanya yang berupaya maksimal, terlebih Randy Danistha yang melebur secara meyakinkan ke dalam karakter Indro dan Aliando Syarief yang cukup menyerupai mendiang Dono. Hanya saja, mereka terkendala oleh materi humor yang lebih banyak melesetnya, bahkan cenderung seksis. Seolah belum cukup bikin penonton istighfar, lawakan di Warkop DKI Reborn 4 mengalami penurunan kualitas secara drastis dari seri sebelumnya yang masih sanggup membekas di ingatan kala memberi penghormatan pada Warkop DKI lawas atau mengaplikasikan Bahasa Arab terbalik yang menggelitik.
Di sini, seperti halnya narasi itu sendiri, sebatas mendaur ulang apa yang sudah-sudah dengan impak yang telah melemah. Kian menambah kebingungan kenapa Reborn teranyar ini mesti dipaksakan buat dipecah jadi dua. Saya ingin sekali tertawa, tapi saya bingung apa yang harus ditertawakan. Apakah saya harus kembali menertawakan keputusan hamba karena memberi kesempatan pada film ini meski sudah dibuat kecewa oleh instalmen terdahulu? Mungkin lebih baik demikian. Gara-gara tak ada yang mengocok perut, durasinya yang hanya 100 menit pun terasa seperti selama-lamanya. Sebuah film yang cocok ditonton oleh kalian yang merasa waktu dalam sehari berjalan terlalu cepat. Syukurlah mereka tidak menyanyi "ahaaa... filmnya dibagi tiga, filmnya dibagi tiga," di ujung cerita.
Note : Ada adegan tambahan di ujung end
credit.
Bisa ditonton di Disney+ Hotstar
Indonesia
Poor (2/5)
REVIEW : RENTANG KISAH 9 Oct 2020 6:26 AM (4 years ago)

“Tuhan menciptakan dunia amat besar. Lalu masa kamu mau diem di rumah
aja?”
Gita Savitri Devi adalah salah
satu vlogger dan influencer berpengaruh di Indonesia. Kontennya berkisar pada
serba-serbi pengalamannya sebagai WNI yang merantau ke negeri orang dan
opini-opini kritisnya terhadap beragam isu sosial politik. Dalam menjalankan
kanal YouTube miliknya, Gita pun tidak berjibaku sendirian. Dia didampingi oleh
teman baiknya yang belakangan menjadi suaminya, Paul Andre Partohap. Kegemaran
keduanya terhadap musik mendorong pasangan ini untuk sesekali memanjakan
telinga para penggemar dengan lantunan tembang-tembang manis. Mereka ingin
sebisa mungkin konten di kanal ini tak saja edukatif dan informatif, tetapi
juga menyenangkan. Tak mengherankan jika kemudian Jeung Gita diikuti oleh lebih
dari 900 ribu penggemar. Sebuah angka yang terhitung masif terlebih si empunya channel bukan berasal dari kalangan
selebriti. Menilik perjalanan sekaligus pencapaian Gita yang impresif tersebut,
rumah produksi Falcon Pictures pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Buku perdana
karya sang vlogger yang laris dibaca
oleh publik, Rentang Kisah, dipinang
untuk diadaptasi ke dalam film panjang. Danial Rifki yang sebelumnya menggarap Haji Backpacker (2014) dan 99 Nama Cinta (2019), ditunjuk mengomandoi
tontonan inspiratif yang menyoroti perjuangan berikut tantangan-tantangan yang
dihadapi oleh Gita saat sedang menimba ilmu di Jerman ini.
Sosok Gita (diperankan oleh Beby
Tsabina) sendiri tidak digambarkan memiliki kehidupan serba sempurna dalam
versi layar lebar Rentang Kisah. Kedua
orang tuanya (Donny Damara dan Cut Mini) memang memberinya kebebasan untuk
menentukan masa depan. Bahkan, mereka mendorong si sulung ini untuk tak berdiam
diri di rumah saja. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat guna mengadu nasib,
sang ayah sempat berpesan agar Gita melanglang buana. Mencari ilmu, mencari
pengalaman, serta mencari teman dengan kebudayaan berbeda. Hanya saja,
protagonis kita ini tak terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Otaknya tak
encer-encer amat dan dia pun masih meraba-raba mengenai minat bakatnya. Apa sih
yang sebenarnya dia cintai? Bermodalkan kenekatan, Gita lantas menjajal peruntungannya
dengan kuliah jurusan Kimia Murni di luar negeri atau lebih persisnya, Jerman. Namun
mengambil studi di negeri orang – terlebih ditambah adanya kendala dalam segi
bahasa serta kultur – tentu bukan perkara mudah. Di tahun-tahun pertamanya, si
karakter utama berulang kali nyaris mengibarkan bendera putih lantaran tertekan
dengan beban kuliah yang diberikan dan rasa sepi yang acapkali merundung. Kala masa
depan sudah tampak buram di mata Gita, Tuhan memberinya solusi dengan
mempertemukannya pada beberapa mahasiswa Indonesia termasuk Paul (Bio One) yang
mengalami “derita” serupa seperti halnya Gita.
Sejujurnya, Rentang Kisah terlihat menggiurkan di titik awal penceritaan. Memberi
kita gambaran mengenai situasi yang dihadapi oleh keluarga si protagonis yang
terdampak Krisis Moneter 1998, serta bagaimana sosok orang tua memberikan pengaruh
besar terhadap cara pandang si anak pada masa mendatang. Mereka adalah sosok
pekerja keras, berpikiran kritis, sekaligus bijaksana. Tak ada tuntutan
macam-macam dibebankan kepada Gita, termasuk soal merealisasikan mimpi maupun
keimanan Satu obrolan yang bagi saya mengena adalah saat Gita mengalami
keraguan untuk berhijab di Jerman dan sang ibu memberinya saran untuk mengikuti
kata hatinya. “Yang penting jangan
berpakaian terlalu terbuka. Urusan pakai hijab, nanti kamu tahu kapan waktunya,”
begitulah kira-kira wejangan sang ibu. Sederhana, mengena, serta paling
penting, tak terkesan menceramahi. Pada titik ini hamba sejatinya masih optimis
kalau Rentang Kisah akan menjadi
sajian inspiratif yang setidak-tidaknya “boleh juga”. Akan tetapi, terhitung
sedari munculnya konflik yang melibatkan kekasih Gita, Roby (Junior Roberts),
film secara perlahan tapi pasti mulai kehilangan arahnya. Ada setumpuk konflik
dijejalkan ke dalam narasi dan ada pula serombongan karakter diperkenalkan
kepada penonton yang datang lalu pergi begitu saja tanpa pernah digali secara
mendalam. Serasa seperti kumpulan-kumpulan episode dari satu webseries yang dipaksakan untuk dijahit
menjadi satu demi menjadi sebuah film panjang. Saya sampai bertanya-tanya, apa
sih poin yang hendak disampaikan oleh film ini?
Sejujurnya, saya bingung dengan
pesan yang terkandung dalam Rentang Kisah
karena saking banyaknya permasalahan yang mencuat tanpa ada kesinambungan
dengan persoalan selanjutnya. Maksud saya, tidak apa-apa kok filmnya minim
konflik (seperti 99 Cahaya di Langit
Eropa) asalkan penonton dapat memahami mengapa si tokoh utama dapat
dijadikan tauladan. Nah, ironisnya, saya bahkan baru bisa memahami sosok Gita –
termasuk motivasinya memilih kuliah di Jerman dan mengambil jurusan Kimia Murni
– setelah membaca tulisannya yang tersebar di internet alih-alih melalui film
ini. Saya tidak pernah melihat sisi kritis dari dirinya yang beberapa kali
didengungkan, saya tidak benar-benar bisa merasakan tantangannya untuk
beradaptasi dengan sistem pengajaran yang jauh berbeda, dan saya pun tidak
melihat adanya ikatan kuat antara dirinya dengan Paul yang notabene bakal
menjadi suaminya. Semuanya muncul sekilas-sekilas saja, termasuk intrik
kompleks perihal percobaan bunuh diri serta mempertanyakan keimanan yang sejatinya
berpotensi untuk kian mengenalkan kita kepada Gita. Heiii... orang tidak secepat itu bangkit dari keterpurukan atau memutuskan pindah agama ya! Alhasil saat film nyaris
berakhir, saya pun masih bingung kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi vlogger dengan topik tertent, bagaimana
sebenarnya kehidupan perkuliahannya yang tampak kabur di film lantaran saru
dengan fase studienkolleg (program
penyetaraan), dan apa yang diperolehnya dari menimba ilmu di Jerman mengingat
pada awal film orang tuanya begitu ngoyo agar dia kuliah ke luar negeri. Sebagai
sebuah film biopik, Rentang Kisah
tidak berhasil membuat saya mengenal sosok Gita, sementara sebagai sebuah film
inspiratif, film ini pun urung memberikan inspirasi lantaran poinnya yang amat
samar.
Satu-satunya yang amat jelas
dalam Rentang Kisah adalah akting Cut
Mini yang layak diberi dua jempol. Darinya, saya masih bisa mendeteksi adanya
emosi dalam film seperti bahagia, sedih, sampai putus asa. Adegan-adegan yang
menampilkan karakternya sedang mengobrol dengan Gita di telepon menjadi
saat-saat terbaik yang dipunyai oleh film ini, khususnya ketika beliau
mengabarkan kepada putri sulungnya bahwa bisnis kateringnya sedang seret dan
tak ada uang yang bisa dikirim. Hamba bisa mendeteksi adanya kepedihan dari seorang
ibu yang merasa sudah mengecewakan anaknya dengan menempatkannya dalam posisi
sulit di negeri orang.
Bisa ditonton di Disney+ Hotstar
Acceptable (2,5/5)
REVIEW : SABAR INI UJIAN 7 Oct 2020 7:02 AM (4 years ago)

“Kebahagiaan akan datang saat kamu sudah bersyukur.”
Apakah kamu familiar dengan
istilah time loop yang beberapa kali
dipergunakan oleh film dari negara-negara yang telah jauh berkembang? Jika belum,
istilah ini secara ringkas merujuk kepada film dengan tokoh utama yang terjebak
dalam putaran waktu. Hari-harinya selalu berulang di satu tanggal,
situasi-situasinya sama persis plek
ketiplek, dan si protagonis harus mencari tahu sabab musababnya agar bisa terbebas
dari siksaan duniawi ini lalu kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Satu
judul paling populer yang menerapkan konsep penceritaan ini adalah Groundhog Day rilisan tahun 1993. Dari era
gawai, kamu bisa menjumpainya dalam Edge
of Tomorrow (2014), Happy Death Day
(2017), maupun Palm Springs yang
baru-baru ini dirilis. Sementara dalam khazanah sinema Indonesia, well, film berkonsep time loop sendiri masih sangat asing
meski hamba pribadi sama sekali tidak terkejut. Apalagi konsep ini terhitung
njelimet untuk dieksekusi dan film beraroma fantasi pun kurang diakrabi oleh
penonton di Indonesia raya. Siapa coba yang cukup nekat untuk mengambil resiko?
Sempat skeptis ranah ini akan benar-benar dijajaki oleh sineas kita, ternyata oh
ternyata Anggy Umbara (Mama Cake, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss) di
bawah payung MD Pictures berani mengambil tantangan tersebut dengan menggarap Sabar Ini Ujian yang dilabeli “film
Indonesia pertama yang mengaplikasikan konsep time loop”. Hasilnya? Sajian komedi drama yang menghibur meski
masih meninggalkan catatan disana sini.
Dalam Sabar Ini Ujian, karakter yang ketiban sial adalah seorang pemuda bernama Sabar (Vino G. Bastian) yang belum
kunjung bisa menerima kenyataan kalau dirinya dan mantan kekasihnya, Astrid
(Estelle Linden), telah bubar jalan. Padahal hubungan mereka kandas empat tahun
lalu dan sang mantan akan menikahi Dimas (Mike Ethan) yang juga teman Sabar
semasa SMA. Saking sulitnya untuk move on,
Sabar sempat berpikir untuk tak menghadiri pesta pernikahan Astrid-Dimas. Tapi
bujukan dari ibunya (Widyawati) beserta sahabatnya, Billy (Ananda Omesh),
membuat si protagonis berubah pikiran. Toh cuma butuh satu hari buat bertahan
menghadapi ujian kehidupan ini, apa sih yang mungkin menyiksa? Tentu saja untuk
seseorang yang belum bisa ikhlas melepaskan, menghadiri acara seperti ini
tetaplah menyiksa lahir batin. Terlebih Sabar juga harus menghadapi
guyonan-guyonan bernada mengejek dari dua temannya, Yoga (Rigen Rakelna) dan
Aldi (Ananta Rispo), yang bikin hati panas. Sabar pun harus bisa bersabar. Yang
tak diketahui oleh tokoh utama kita ini, ujian tidak berhenti sampai disini
saja. Kala dirinya terbangun di kamar kos keesokan harinya, Sabar mendapat
kejutan yang sangat teramat aneh: dia kembali terbangun di hari pernikahan
Astrid. Mulanya, Sabar mengira keanehan tersebut hanyalah bagian dari candaan
yang digagas oleh teman-temannya. Namun ketka dia kembali mengulang hari yang
sama di hari-hari berikutnya, pada saat itulah Sabar harus menemukan akar
masalah yang menyebabkannya terjebak dalam putaran waktu.
Mesti diakui, mudah untuk
menyebut Sabar Ini Ujian sebagai
salah satu karya terbaik yang pernah ditelurkan oleh Anggy Umbara. Paruh awalnya,
terutama saat si karakter utama berusaha untuk memahami dan beradaptasi dengan
apa yang terjadi padanya, menjadi bagian paling mengasyikkan dari film. Sang
sutradara paham betul bahwa film berkonsep time
loop berpotensi terjerembab menjadi sajian menjemukan mengingat sebagian
durasinya diisi pengulangan-pengulangan adegan dan dalam konteks Sabar Ini Ujian, latar penceritaan
banyak dihabiskan di dalam ballroom. Demi
menyiasatinya, Pak Anggy gesit menyelipkan pembeda dalam setiap repetisi sehingga
penonton pun dilingkupi keingintahuan, “apa
nih yang akan dilakukan oleh Sabar selanjutnya?.” Disokong oleh
penyuntingan dinamis dari Cesa David Luckmansyah serta performa santai dari
jajaran pemain, satu jam awal pun diisi banyak kesenangan yang mengundang gelak
tawa. Saya pribadi menyukai tektokan antara Rigen Rakelna dengan Ananta Rispo yang
terasa mengalir begitu saja. Guyonannya receh sih – apalagi soal kepanjangan
CLBK – tapi penyampaian keduanya yang efektif memungkinkan tiap celetukan
memiliki daya tonjok humor yang kuat. Serius, hamba terbahak-bahak tiap mereka
muncul. Vino G. Bastian yang diposisikan sebagai pemain sentral juga lihai
menangkap umpan-umpan yang diberikan oleh duo ini sehingga mereka bisa tampil
meyakinkan sebagai teman baik. Tak hanya dengan Rigen-Ananta, Vino turut
berkesempatan untuk menggila bersama Dwi Sasono (sebagai teman kosnya yang
demen bugil) dimana dia menghadirkan momen emas dengan memarodikan sejumlah
peran dari film-filmnya sebelumnya. Gokil!
Kecakapan Vino dalam menangani momen
komedik ini sejalan dengan kemampuannya dalam melakoni momen dramatik. Dia
mendapat “lawan tanding” kelas kakap seperti Widyawati beserta mendiang Adi
Kurdi yang bahkan sanggup membuat penonton terenyuh hanya dari sentuhan-sentuhan
kecil dalam gestur. Saya menyukai adegan percakapan antara Sabar dengan ibunya
melalui telepon, dan saya amat menyukai obrolan keduanya di meja makan mengenai
mendefinisikan kebahagiaan. Terasa hangat. Berkat akting tiga pelakon ini, Sabar Ini Ujian masih mampu
mengaduk-aduk emosi penonton di menit-menit terakhirnya yang terasa goyah. Ada ketidakwajaran
terdeteksi pada titik ini. Memang, film sudah mulai menunjukkan problematikanya
pada pertengahan durasi yang lajunya cenderung nyeret-nyeret. Tapi setelah dua pengungkapan
besar terjadi (yang tentu tidak akan hamba jabarkan secara detil), Sabar Ini Ujian seperti kehilangan daya
pikatnya. Nada pengisahannya mendadak berubah drastis dari ceria menjadi
depresif, lalu bangunan motivasi yang disematkan untuk dua karakter krusial di
penghujung kisah tidak pula cukup meyakinkan. Haruskah dipertemukan dengan cara
semendadak itu tanpa ada interaksi tipis-tipis sebelumnya? Haruskah diakhiri
dengan senelangsa itu yang menjadikannya kontradiktif dengan semangat di awal? Padahal,
hamba sudah merasa terhubung dengan topik obrolannya perihal mengikhlaskan,
memaafkan, serta berdamai dengan trauma masa lalu. Andai tak ada sisipan twist – atau andai ditangani dengan
lebih meyakinkan – film ini mungkin bisa terhidang dengan lebih memuaskan.
Note : Ada bloopers di sela-sela end credit. Jangan dilewatkan soalnya lucu sekali.
Bisa ditonton di Disney+ Hotstar
Exceeds Expectations (3,5/5)
REVIEW : BUCIN (WHIPPED) 5 Oct 2020 8:23 AM (4 years ago)

“Kesabaran merupakan kunci dari hubungan yang baik.”
Kamu tidak akan menemukan makna
“bucin” di KBBI. Konon, ini adalah akronim dari budak cinta yang dipopulerkan
pertama kali oleh duo Youtuber kondang, Jovial dan Andovi da Lopez. Bahasa
prokem tersebut disematkan oleh keduanya untuk orang-orang yang kelewat tunduk
kepada pasangannya dengan dalih bersikap romantis atau “aku mencintainya sepenuh hati”. Alhasil, mereka pun rela melakukan
apa saja demi sang pasangan sampai-sampai mengesampingkan logika dan hati.
Sungguh menyedihkan. Berhubung istilah ini masih kerap digunakan oleh muda-mudi
masa kini, bahkan sebetulnya sangat relevan dengan problematika percintaan
banyak orang, Jovial pun tercetus satu ide untuk memonetisasinya lebih lanjut.
Bagaimana kalau istilah ini dikembangkan menjadi sebuah cerita panjang?
Lebih-lebih, teman baiknya sesama Youtuber, Chandra Liow, sedang membutuhkan
skrip film untuk debut penyutradaraannya usai mencicipi karir akting yang
tergolong sukses melalui Single
(2015) dan Hit & Run (2019). Dari
sini, dua content creator yang
memutuskan berkolaborasi untuk kesekian kalinya ini lantas menghasilkan film
komedi bertajuk Bucin – atau Whipped
untuk peredaran internasional – yang tadinya direncanakan untuk edar di
bioskop. Tapi setelah dunia diterpa pandemi Covid-19, film produksi Rapi Films
ini pun diserahkan kepada Netflix dan hamba merasa sangat beruntung tidak
menyaksikan Bucin di layar lebar.
Dalam Bucin, Jovial da Lopez dan Chandra Liow yang juga ikut bermain di
garda terdepan bersama Andovi da Lopez beserta Tommy Limmm berperan sebagai
versi fiksi dari diri mereka sendiri. Keempatnya dikisahkan mengikuti kelas
anti bucin asuhan seorang pakar cinta bernama Vania (Susan Sameh). Alasannya,
Jovi kedarung resah melihat adiknya, Andovi, dibuat tak berdaya oleh sang
kekasih, Kirana (Widika Sidmore), yang memanfaatkan ketidaktegasan Andovi untuk
memenuhi keinginannya dalam sekejap. Tak hanya Andovi, Tommy dan Jovi pun
sejatinya mengalami permasalahan kurang lebih senada dengan pasangan-pasangan
mereka. Tommy yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Julia (Karina
Salim) tak diberi kebebasan untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri,
sementara Jovi tak memiliki keberanian untuk berkata jujur kepada Cilla (Kezia
Aletheia) mengenai perasaannya yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan Chandra
yang seorang jomlo? Well, dia hanya
merasa perlu untuk memberi moral support
kepada trio bucin ini dengan mengikuti kelas yang sama sekali tidak ada artinya
bagi dia. Bahkan, kelas anti bucin pun pada dasarnya urung memberikan dampak
signifikan kepada yang lain kecuali memicu konflik diantara empat sekawan ini
dan memberi kesempatan bagi Jovi untuk mendapatkan pengganti Cilla.
Selama menit-menit awal, Bucin sejujurnya tampak menjanjikan
untuk diikuti. Entah dari konsep “kelas anti bucin” yang didesain menyerupai
permainan escape room atau dari
lelucon visual yang coba dikedepankan oleh Chandra Liow. Bahkan, saya pun
mengapresiasi akting Karina Salim sebagai Julia dengan gaya bicaranya yang
kekanak-kanakkan apalagi ketika doi bermanja-manja ria bersama Tommy. Lucu,
menggelikan, sekaligus menggemaskan. Bagi hamba, Karina adalah hal terbaik yang
dipunyai oleh Bucin dan bisa membuat
diri ini bertahan di saat film menjadi semakin sukar dicerna di menit-menit
selanjutnya. Bukan, bukan karena kontennya yang ternyata ndakik-ndakik atau teramat kompleks, melainkan karena gaya
bercandanya yang memang tak sesuai selera. Mungkin masih bisa memantik tawa
buat penggemar berat sang sutradara. Tapi berdasar sepengamatan saya,
guyonannya acapkali meleset dari sasaran yang memungkinkan orkestra jangkrik terdengar
begitu nyaring di telinga. Selain kemunculan Julia, sungguh penuh perjuangan
hanya untuk mengingat momen-momen apa saja yang dapat menyunggingkan senyum
alih-alih bikin manyun. Sebagai sebuah film yang mengatasnamakan dirinya
sebagai komedi, Bucin nyaris tak
memiliki kemampuan untuk mengocok perut. Ditambah lagi, kehadiran barisan
karakternya sulit sekali diberi simpati. Jika sedari awal betul diniatkan untuk
bercerita soal laki-laki lubang pantat yang membuat penontonnya mengelus dada,
paling tidak beri mereka latar belakang yang menggugah selera. Beri mereka
alasan-alasan pasti yang melandasi tindakan ketimbang sebatas berlindung
dibalik dalih “udah ngeselin dari orok.”
Maksud saya, kenapa Andovi
sebegitu tidak inginnya kehilangan Kirana sampai bersedia diperlakukan semena-mena
bak budak? Mengapa Tommy ngotot ingin membeli mobil baru yang mana bukan
kebutuhan primer sedangkan pernikahan sudah di depan mata? Kenapa Jovi tega
menyiksa Cilla dalam hubungan penuh ketidakpastian yang sudah terasa amat
dingin? Dan mengapa Chandra hanya mondar-mandir sambil sesekali melempar punchline menyebalkan tanpa diberi
kontribusi yang jelas pada penceritaan? Why?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkecamuk di benak dan Bucin enggan memberikan jawaban yang memuaskan pada penonton. Padahal
ada perpaduan antara kebodohan, egoisme, serta toxic relationship di sini. Pokoknya, mereka tiba-tiba seperti itu
dan para perempuan lah penyebabnya. Tidak ada yang salah memang dengan
menggunakan sudut pandang lelaki untuk menguliti konflik di film ini. Hanya
saja, apa yang kemudian menjadikan Bucin
problematis, adalah keputusan si pembuat film untuk mengantagonisasi serta
merendahkan martabat para karakter perempuan di sini sedemikian rupa. Momen
pengungkapannya dengan bubuhan twist
yang diharapkan mengejutkan adalah momen dimana hamba butuh mendengarkan suara
hujan demi mencegah munculnya gerutuan-gerutuan non-esensial. Betapa tidak, mereka
menggambarkan si villain yang
notabene adalah korban sebagai sosok psikopat dan film pun enggan memberi penyelesaian
untuk karakter ini. Tiba-tiba lenyap, tiba-tiba kita dihadapkan pada perubahan
drastis dari salah satu tokoh kunci yang merupakan “the real villain” dalam Bucin.
Tanpa melewati proses, sosoknya mendadak memperoleh hidayah yang diterima
begitu saja oleh sang kekasih hanya bermodalkan pernyataan, “cinta itu memaafkan.” Subhanallah, ternyata hamba sedang
menyaksikan versi layar lebar dari FTV Pintu
Berkah.
Ambisi Jovial beserta Chandra
untuk memberi porsi sama rata kepada setiap karakter menjadi salah satu musabab
mengapa film menjadi ruwet di belakang. Terlalu banyak tokoh, terlalu banyak konflik
yang dijejalkan, tapi terlalu sedikit waktu yang dipergunakan untuk
mengentaskan para karakter dari permasalahan masing-masing. Mungkin, hanya
mungkin ya, kadar seksisme dalam Bucin
akan sedikit berkurang apabila fokus pengisahan hanya pada satu karakter
sehingga ada kesempatan untuk mengeksplorasi permasalahan yang diajukan
termasuk memberinya latar belakang dan penyelesaian yang masuk akal. Ya beginilah
Bun pentingnya menetapkan prioritas agar tidak kewalahan sendiri.
Bisa ditonton di Netflix
Poor (2/5)
REVIEW : GURU GURU GOKIL 2 Oct 2020 8:18 AM (4 years ago)

“Di dunia ini, gue paling suka uang.”
Guru Guru Gokil adalah salah satu film Indonesia yang hamba
nanti-nantikan kehadirannya di awal tahun ini. Alasannya sederhana saja, Dian
Sastrowardoyo tidak pernah mengecewakan saat diminta untuk ngebanyol.
Keputusannya untuk turut menduduki kursi produser, kian menguatkan ekspektasi
mengingat Mbak Dian terhitung sebagai aktris yang selektif dalam memilih
konten. Mudahnya, film ini tidak akan main-main secara kualitas penggarapan.
Bahkan saat pandemi Covid-19 kian meluas yang menyebabkan jaringan bioskop di
Indonesia berhenti beroperasi untuk sementara waktu, film garapan Sammaria
Simanjuntak (Demi Ucok, Cin(t)a) ini dipinang oleh raksasa
streaming Netflix dan memperoleh kesempatan untuk diedarkan secara luas ke
seluruh dunia dengan banderol “Netflix
Original”. Itu artinya, ini adalah film Indonesia kedua yang mendapat
kehormatan tersebut usai The Night Comes
for Us (2018). Belum apa-apa, sudah terdengar menggiurkan, to? Terlebih
materi yang diusung sejatinya memang menggiurkan yakni seputar sepak terjang
para pahlawan tanpa tanda jasa yang dihidangkan menggunakan pendekatan komedi.
Sepintas lalu, film ini punya komposisi yang terlihat tidak mungkin salah di
atas kertas. Ditambah kehadiran Gading Marten yang dikenal luwes kala ngelaba
di garda terdepan pemain, Guru Guru Gokil
seolah menjanjikan sajian komedi lucu nan menginspirasi yang ternyata oh
ternyata… tidak pernah terealisasi.
Karakter utama yang menggerakkan poros penceritaan adalah Taat Pribadi (Gading Marten). Seorang pria dari suatu desa yang memilih untuk mengadu nasib di Jakarta lantaran tidak ingin dibayang-bayangi oleh nama besar sang ayah, Pak Purnama (Arswendy Bening Swara). Apalagi, sebagai seseorang yang memproklamirkan dirinya sebagai pecinta uang, kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah pun jauh lebih besar di ibukota. Hanya saja, setelah berjibaku dengan beragam profesi selama bertahun-tahun, kondisi finansial Taat tidak kunjung membaik yang kemudian mendorongnya untuk kembali ke kampung halaman. Di desa, satu-satunya pekerjaan yang tersedia untuknya adalah menjadi guru pengganti di sebuah sekolah tempat ayahnya mengajar. Bagi Taat, menjalani pekerjaan ini bak musibah karena: 1) dia benci guru, dan 2) dia semakin dekat dengan sang ayah yang selama ini dihindarinya. Tapi berhubung tak ada pilihan lain, apa yang bisa dilakukannya? Toh masih ada Bu Rahayu (Faradina Mufti), guru serbabisa yang kerasnya minta ampun, sebagai obat pelipur lara. Di tengah upaya si protagonis dalam mencari uang sekaligus memenangkan cintanya ini, sebuah perampokan terjadi dan menguras habis gaji para guru. Tak ingin uang yang didambakannya menghilang begitu saja, Taat pun merancang misi mengambil alih gaji yang dirampok dari mafia setempat bersama guru-guru lain seperti Pak Manul (Boris Bokir), Bu Nirmala (Dian Sastro), serta tentunya, Bu Rahayu.
Tampak menarik? Ya, jika Guru Guru Gokil mampu meletakkan
fokusnya di salah satu titik tanpa harus bercabang kesana kemari. Masalahnya,
film mempunyai banyak sekali intrik yang telah ditetapkan dari awal seperti
relasi Taat dengan sang ayah yang dingin, Taat yang menjalani pekerjaannya
dengan keterpaksaan, hubungan percintaan Taat bersama Bu Rahayu, sampai kritik
sosial terkait nasib guru di Indonesia yang jauh dari sejahtera. Naskah gubahan
Rahabi Mandra seolah hendak membawa penceritaan mengikuti transformasi si tokoh
utama dari seseorang yang membenci profesi guru menjadi seorang pria yang
menaruh respek tinggi pada pekerjaan mulia ini. Jika saja film bertahan pada
plot ini, saya meyakini Guru Guru Gokil akan
menggoreskan kesan kuat lantaran telah berani menampilkan realita pahit dari
para tenaga pengajar dengan penuh candaan (plus sentilan) disana sini. Akan
tetapi, alih-alih bertahan di ranah komedi satir, Sammaria Simanjuntak justru
membelokkan kemudi ke ranah komedi kriminal yang penuh kehebohan sampai-sampai pesan yang ingin diutarakan mengabur. Selama sisa durasi,
film diisi oleh momen-momen mengatur strategi yang serba mudah, menyergap ke
markas besar si penjahat yang (lagi-lagi) serba mudah, lalu diakhiri dengan
konfrontasi konyol-konyolan. Tidak terlihat ada pertaruhan yang nyata karena
sosok villain-nya sendiri digambarkan
kelewat amatir dan karakter Taat tidak pernah berproses secara meyakinkan
akibat plot yang ramai sesak. Semuanya berlangsung tiba-tiba, termasuk
bagaimana Taat bisa dengan mudah menjalin ikatan kuat dengan murid-muridnya dan
bagaimana dia akhirnya bisa berdamai dengan sang ayah.
Alhasil, Guru Guru Gokil menjadi serba tanggung dalam penyampaian emosinya.
Adegan yang diharapkan mampu memicu gelak tawa berderai-derai maupun tangis
haru pun urung muncul. Padahal potensi-potensinya jelas terlihat dan jajaran
pemain kentara telah mengerahkan kemampuan berlakon secara maksimal. Berkat
kontribusi akting apik inilah yang membuat Guru
Guru Gokil masih bisa untuk setidaknya tampil menghibur. Gading Marten yang
berada di zona nyamannya tampil effortless
sebagai pemuda slengean yang tidak
pernah menganggap serius pekerjaannya karena dia hanya mengincar satu hal:
uang. Bersama dengan Faradina Mufti yang memesona dibalik sikap galaknya,
mereka membentuk chemistry manis yang
memungkinkan interaksi keduanya terasa menyenangkan untuk disimak. Dian Sastro
dalam peran sama sekali berbeda adalah scene
stealer yang memberikan dorongan pada penonton untuk tersenyum melihatnya,
atau malah tertawa. Sementara Asri Welas yang juga diberi kesempatan memainkan
peran bertolak belakang dari biasanya malah agak tersia-siakan. Saya pribadi
tidak merasa nyaman melihatnya menjajal karakter serius dalam film lucu-lucuan
receh seperti ini lantaran dia dengan comic
timing-nya yang juara sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk mengatrol
momen-momen komedik yang acapkali berlangsung hambar. Sangat disayangkan.
Bisa ditonton di Netflix
Acceptable (2,5/5)
REVIEW : MUDIK (2020) 1 Oct 2020 2:25 AM (4 years ago)

“Mau sampai kapan kita kayak gini? Kamu nggak bisa terus-terusan lari
kayak gini.”
Perjalanan pulang kampung saat
libur Lebaran seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi anak rantau.
Bisa melepas rindu dengan tanah kelahiran, bisa memeluk hangat orang tua, dan
bisa bersenda gurau dengan saudara-saudara kandung. Meski obrolan basa-basi
kala halal bi halal seringkali bikin
capek hati, tapi hidangan khas beserta acara kumpul-kumpulnya dengan keluarga
yang mungkin jarang ditemui itu ngangenin.
Tentu dengan catatan, tidak ada perang dingin yang tengah bergelora. Apabila
ada masalah besar yang titik terangnya belum kunjung terlihat, mudik pun serasa
perjalanan menuju neraka. Menyiksa jiwa dan raga. Tengok saja pasangan suami
istri, Firman (Ibnu Jamil) dan Aida (Putri Ayudya), yang selama perjalanan
menuju ke kampung halaman tak pernah sekalipun terlihat cerah ceria
berseri-seri. Mereka enggan untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang
lain karena mereka sama-sama tahu, membuka mulut sama artinya dengan memulai
medan pertempuran. Alhasil, penonton Mudik
atau Homecoming arahan Adriyanto Dewo
(Tabula Rasa) pun ikut menyusuri rute
Jakarta-Jogja dengan perasaan yang tidak mengenakkan lantaran Firman dan Aida
adalah karakter sentral dalam film ini. Alih-alih menunggangi pesawat terbang
atau kereta api yang bisa memangkas waktu tempuh secara signifikan, keduanya justru
memilih untuk mengendarai mobil pribadi yang menjadikan 8 jam seperti
selamanya.
Penonton tidak dibiarkan tahu
begitu saja mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh pasangan ini. Melalui
tukar dialog yang amat minim dan mimik muka para karakternya, kita hanya mendapati
informasi bahwa ada masalah besar dalam rumah tangga mereka yang besar
kemungkinan dipicu oleh Firman. Karakter ini diperlihatkan tampak menyimpan sesuatu
sedari mula. Bahkan, kita mendapatinya berbohong mengenai dering telepon kepada
sang istri kala dirinya dijemput di bandara. Selagi mengikuti perjalanan
keduanya yang acapkali diisi oleh keheningan, dengan sesekali diselingi oleh
adu mulut, pemirsa dibawa menerka-nerka: ada apa sebetulnya? Oleh si pembuat
film, tanya ini tidak lantas dibentuk sebagai misteri besar guna memberikan
daya pikat tersendiri karena narasi Mudik
lebih menekankan pada proses si karakter utama, dalam hal ini Aida, untuk
berdamai. Baik berdamai dengan diri sendiri, keadaan maupun orang lain. Seperti
esensi dari mudik dan Idul Fitri itu sendiri; perjalanan untuk memulai
kehidupan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Demi mencapai tujuan
tersebut, Aida dan Firman mendapat ujian besar di tengah jalan usai mobil
mereka tanpa sengaja menabrak motor dan menewaskan pengemudinya. Merasa bersalah,
Aida memilih untuk bertanggung jawab yang kemudian membawanya ke kediaman
korban dimana dia bertemu dengan istrinya, Santi (Asmara Abigail), yang tidak
terima dengan kematian sang suami.
Selama beberapa hari, Aida dan
Firman pun terjebak di sana lantaran penduduk “Kampung Dajjal” menuntut adanya
permintaan maaf dalam wujud materi. Pada titik ini, Mudik yang telah mencuri perhatian sedari adegan kecelakaan yang diramu
intens pun semakin menggeliat dengan melemparkan kritik sosial berkenaan dengan
masyarakat yang oportunis dan seksis. Alih-alih mengupayakan adanya mediasi
antara dua belah keluarga, beberapa pihak justru memanfaatkannya untuk mengeruk
keuntungan pribadi dengan dalih “kasihan
Santi, sekarang dia harus menghidupi ibu dan anaknya,” sementara Santi
tidak pernah dilibatkan dalam diskusi apapun. Dirinya justru mendapatkan
pengekangan demi pengekangan dari masyarakat karena statusnya sebagai seorang
perempuan dan janda. Ini terasa nyelekit, tetapi juga menampar saking
relevannya dengan keadaan di sekeliling kita. Bukankah kerap dijumpai oknum yang
tega memanfaatkan kemalangan seseorang demi mendapatkan keinginannya? Tidak
hanya masyarakat, tetapi juga mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai
penegak hukum. Mudik sempat
menyorotinya melalui menghilangnya sosok polisi yang mulanya berjanji akan
membantu mengurai silang sengkarut ini. Mendadak lenyap tak berbekas yang serta
merta mengundang tanya sekaligus kecurigaan mengenai keterlibatan mereka dalam
upaya memeras pasangan naas tersebut. Kalaupun tidak, bukankah terasa sama
problematiknya lantaran telah melepas tanggung jawab dan menyerahkannya kepada
warga desa yang buta dasar-dasar penegakan hukum?
Penonton dihadapkan pada rasa
cemas, takut, serta putus asa yang disalurkan secara cemerlang oleh Putri
Ayudya melalui ekspresi serta gestur tubuh. Interaksi serba canggungnya dengan
Ibnu Jamil yang tidak lagi dicintainya dan Asmara Abigail yang tampak begitu
nelangsa, memberi kekuatan tersendiri bagi Mudik
yang sayangnya mulai goyah kala misteri dibalik persoalan rumah tangga Aida-Firman
mulai diungkap. Meski problematika ini memang nyata adanya di masyarakat, tapi
bukankah sudah terlampau jamak dikedepankan sebagai akar permasalahan oleh
film-film Indonesia lain? Maksud hamba, masih ada pemantik-pemantik lain yang
tidak kalah ganasnya yang boleh jadi akan memberi greget maupun pertaruhan
lebih besar bagi hubungan dua karakter ini. Terlebih, konflik batin yang
merundung Aida sejatinya sudah cukup untuk memberi pukulan telak kepada
masyarakat yang kerap merecoki kehidupan pribadi seseorang dengan pertanyaan
basa-basi nyelekit. Adanya momen “pertengkaran besar” di penghujung durasi pun
tidak membantu dengan penggambarannya yang kelewat meledak-ledak, cenderung kontradiktif
dengan pembawaan film yang di sepanjang durasi yang meletakkan fokusnya pada permainan
mimik muka dan gestur yang halus. Di kala Mudik
seperti telah kehilangan daya cengkramnya di menit-menit yang semestinya
menjadi gong, Adriyanto Dewo berhasil mengangkatnya kembali dengan memberi
babak pamungkas yang bukan saja indah ditunjang iringan skoring musik megah
gubahan Lie Indra Perkasa, tetapi juga emosional.
Bisa ditonton di Mola TV
Exceeds Expectations (3,5/5)
REVIEW : TIMMY FAILURE MISTAKES WERE MADE 24 Sep 2020 1:08 AM (4 years ago)

“If you love what you do, you gotta fight for it.”
Diangkat dari buku kanak-kanak
rekaan Stephan Pastis, Timmy Failure:
Mistakes Were Made menyoroti tingkah polah seorang bocah berusia 11 tahun,
Timmy Failure (Winslow Fegley), yang mempunyai imajinasi tanpa batas. Tinggal
bersama sang ibu, Patty (Ophelia Lovibond), di pinggiran kota Portland, Timmy
yang menjalankan agensi detektif swasta bernama Total Failure Inc. ini
menganggap dirinya sebagai detektif kelas wahid. Rekannya pun tidak
tanggung-tanggung, seekor beruang kutub bernama Total yang konon terdampar di
kampung halamannya selepas es di Kutub Utara mulai mencair akibat pemanasan global.
Timmy yang berulang kali menekankan “enggan bekerjasama dengan penegak hukum”
sejatinya hanya mengambil kasus-kasus remeh seperti tas teman sekolahnya yang
menghilang. Itupun bukan berdasar keinginan tulus sang klien, melainkan setelah
si tokoh utama terus mendesaknya. Harapan Timmy untuk mendapatkan kasus yang
benar-benar serius lantas muncul ketika segway milik Patty yang dikendarainya
kemana-mana mendadak raib. Mengingat benda tersebut adalah satu-satunya barang
yang dinilai berharga oleh sang ibu, maka tentu saja duo Timmy-Total harus
bekerja keras untuk menemukannya. Dalam penelusuran, keduanya mencurigai keterlibatan
mafia Rusia yang selama ini mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh Timmy.
Bahkan, ini mungkin ada kaitannya dengan teman sekelasnya yang dijuluki “The Nameless One”.
Sepintas, Timmy Failure: Mistakes Were Made memang terlihat seperti film
untuk seluruh keluarga yang ringan-ringan saja. Tokoh utamanya adalah seorang
bocah tukang bikin onar dengan konflik inti seputar mencari keberadaan segway
milik sang ibu. Oh, plus ada seekor beruang kutub yang tidak pernah sekalipun
berkontribusi pada penyelidikan kecuali terdistraksi dengan hal lain dan membuat
rekannya ngedumel “that’s a demerit”.
Sama sekali bukan hewan yang cerdas. Yang kemudian menjadikan film arahan Tom
McCarthy (The Visitor, Spotlight) ini tidak sekopong itu adalah
fakta bahwa imajinasi liar sang protagonis merupakan produk dari trauma. Semasa
kecil, Timmy ditinggal pergi oleh sang ayah dan semenjak hari menyedihkan
tersebut, Patty jarang hadir dalam kehidupan putranya lantaran harus mengambil
dua pekerjaan demi membayar kontrakan. Guna mengisi kekosongan, Timmy menciptakan
sesosok teman khalayan berwujud beruang kutub yang setia menemaninya kemanapun
dia pergi. Keberadaan Total ini pula yang lantas menciptakan benteng penyekat
antara si tokoh utama dengan karakter lain. Rasa kecewa yang teramat sangat
akibat ditelantarkan oleh orang tuanya secara perlahan tapi pasti membentuk trust issue dalam dirinya sehingga dia
kerap melihat siapapun yang mencoba mendekati dirinya – maupun Patty – sebagai
ancaman. Dia tidak percaya terhadap cinta, dia tidak pula percaya terhadap
bantuan orang lain.
Mekanisme pertahanan dirinya yang
senantiasa bekerja inilah yang membuat karakter Timmy agak sulit untuk disukai
bagi sebagian penonton. Diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai
kondisinya agar bisa mengerti karakteristiknya berikut penolakan demi penolakan
yang ditunjukkannya. Dia enggan mengucap “ya” dan “maaf”, kosa katanya rumit
bak jurnal ilmiah, dan Timmy jelas ogah memperbincangkan permasalahan
pribadinya dengan orang lain. Di saat Patty tak mampu menembus benteng yang
dibangun oleh sang putra, film menghadirkan dua karakter lain yang bersedia
untuk meladeni polah ajaib si bocah. Mereka adalah Crispin (Kyle Bornheimer)
yang merupakan kekasih Patty sekaligus seorang petugas parkir dan Pak Jenkins
(Craig Robinson) yang bekerja sebagai konselor sekolah. Kepada dua karakter
tersebut, Timmy bersedia untuk berbagi mengenai misi yang tengah dilakoninya
seperti menghadapi mafia Rusia yang berupaya menyabotase bisnisnya dengan
mencuri segway milik Patty. Apakah subteks ini terdengar, errr… berat nan
kompleks? Buat penonton cilik yang sudah kedarung cocok dengan produk-produk
hiburan yang penuh gegap gempita dengan tempo bergegas, bisa jadi demikian. Timmy Failure: Mistakes Were Made tak
ubahnya “film kecil” minim momen bombastis yang menghimpun sketsa-sketsa guna memvisualisasikan
imajinasi Timmy yang mesti diakui merupakan daya tarik utama film ini.
Seringkali nyeleneh dan tak terbayangkan, tapi jelas menggelitik.
Ya, imajinasi si karakter kunci
yang infinity and beyond lah yang
menghadirkan gelak tawa di film ini. Dari bagaimana dia membayangkan
kecerobohan Total yang betul-betul total, bagaimana dia mengartikan sejumlah
istilah secara harfiah, dan bagaimana dia memandang permasalahan yang tengah
dihadapinya. Terlihat penuh halang rintangan bak film laga yang mendebarkan,
meski kenyataannya ya lempeng-lempeng saja. Timmy
Failure: Mistakes Were Made yang unggul dalam perkara meramu elemen komedik
ini turut terbantu oleh performa mengagumkan jajaran pelakonnya. Perhatikan deh
ekspresi Winslow Fegley yang angkuh seolah dia punya kemampuan bak Sherlock
Holmes, kamu mungkin akan sebal bukan kepalang jika berada dalam posisi musuh
bebuyutannya, Pak Frederick (Wallace Shawn), yang juga gurunya. Rasanya minta
digiles. Tapi Wallace Shawn sendiri tidak jauh berbeda karena karakternya
dideskripsikan sebagai villain berapi-api
yang berniat mengenyahkan Timmy. Interaksi benci-tapi-sayang diantara keduanya menjadi
salah satu sumber kesenangan dari film ini terlebih kala mereka kucing-kucingan
di Bonneville Dam. Asyik sekali. Sementara duo tersebut bertugas menjaga garda
komedi, Ophelia Lovibond dan Craig Robinson mempunyai peranan dalam
menghidupkan elemen dramatik. Lovibond tampak tulus menyayangi putranya
sekalipun dia kerap kewalahan menanganinya, lalu Robinson memberi kesempatan
bagi film untuk menyuarakan pesannya sekaligus menghadirkan momen menghangatkan
hati. Dari wejangan-wejangan Pak Jenkins, kita bukan saja belajar untuk
memahami dan bersimpati kepada Timmy. Tapi juga belajar untuk memahami diri
sendiri, mencintai diri sendiri, serta menghargai orang lain.
Bisa ditonton di Disney+ Hostar Indonesia
Outstanding (4/5)
25 FILM HOROR PALING MENYERAMKAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR VERSI CINETARIZ 18 Sep 2020 2:30 AM (4 years ago)

Saat berniat mengerjakan senarai “25 Film Horor Paling Menyeramkan Dalam 10 Tahun Terakhir”, saya sempat skeptis. Menurut daya ingat hamba yang pendek, tak banyak sajian seram yang membekas di hati. Tapi usai mencoba mengompilasinya dan memanfaatkan ingatan secara maksimal, ternyata oh ternyata… bergelimangan, euy. Pilihannya pun beragam, dari blockbuster, indie, sampai arthouse, dimana rata-rata memperoleh resepsi memuaskan baik dari penonton maupun kritikus. Total jendral, ada lebih dari 50 judul yang berhasil saya kantongi dan putuskan untuk diseleksi kembali menjadi 25 besar. Syarat beserta ketentuannya pun tidak neko-neko – plus sangat subjektif – yakni seberapa kuat film-film tersebut membuat saya terhibur, terngiang-ngiang di benak sampai beberapa hari ke depan, serta tentu saja, bergidik ngeri. Oh, plus dirilis pada tahun 2010-2019.
Berhubung selalu ada perasaan “dibuang
sayang”, maka senarai ini pun dimulai dengan…
Honorable Mentions
# Crawl
Terjebak di dalam rumah saat
banjir besar saja sudah ngeri, apalagi ditambah ditemani buaya.
# Gonjiam Haunted Asylum
Uji nyali di bekas rumah sakit
yang dikenal angker itu namanya cari penyakit.
# Housebound
Ada yang lebih mengerikan
dibanding gangguan gaib, orang tua yang ceriwis dan suka ikut campur.
# Last Shift
Jaga malam sendirian di kantor
polisi jelas bukan tugas yang diinginkan oleh siapapun.
# Lights Out
Jangan pernah matikan lampu karena kamu tidak pernah tahu apa yang bersembunyi di balik kegelapan.
# Midsommar
Perjalanan spiritual seorang
perempuan dalam mengenyahkan duka ternyata bisa sangat berbahaya.
# Pee Mak
Saat horor dan komedi bisa melebur dengan mulus, hasilnya adalah tontonan yang pecah.
# Ready Or Not
Jangan pernah anggap remeh permainan petak umpet apalagi saat melibatkan senjata berbahaya.
# Us
Bagaimana jadinya kalau ternyata
punya “kembaran” yang amat sangat jahat?
# You're Next
Reuni keluarga yang canggung berubah menjadi medan pertempuran penuh pertumpahan darah hanya dalam seketika.
Lalu, inilah saatnya berlanjut ke
para penghuni 25 besar…
#25 As Above So Below
Siapa menyangka di bawah gemerlap
kota Paris tersembunyi sebuah “dunia” misterius yang dipenuhi jebakan dan ilusi
mengerikan? As Above So Below adalah
bukti bahwa konsep found footage
masih belum kehilangan pesonanya terlebih saat dipadukan dengan materi mumpuni,
sekaligus bukti bahwa kamu masih akan mendapati pengalaman menonton yang
mendebarkan dari konsep ini.
#24 We Are Still Here
Pada mulanya, We Are Still Here tampak seperti
tontonan seram bertemakan haunted house
biasa. Satu pasangan yang baru saja kehilangan anak mereka, pindah ke sebuah
rumah tua reyot dan seketika mendapati hal-hal gaib mulai terjadi. Teror
hantu-hantuan di paruh awal memang cukup membuat bulu kuduk berdiri, tapi
keistimewaan film ini terletak pada babak pamungkasnya yang menggila.
#23 Sinister
Sejatinya, Sinister adalah horor klasik yang bermain-main di ranah rumah
berhantu dengan trik penampakan usang. Yang kemudian menjadikannya sebagai
tontonan pemberi mimpi buruk adalah atmosfernya yang benar-benar mengusik
sedari menit pembuka. Saya masih belum bisa melupakan isi video rumahan yang
menampilkan beberapa keluarga kala hendak dieksekusi. Bikin merinding.
#22 The Invitation
Diundang ke rumah mantan istri
dimana peristiwa traumatis pernah terjadi saja jelas tidak terdengar
menyenangkan. Betul saja, si protagonis utama mulai mengendus adanya motif
terselubung yang menjadikan setiap menit film ini menjadi semakin misterius,
mencengkram, serta mencekam. Penonton dibuat bertanya-tanya, apakah
kekhawatiran si protagonis ini masuk akal atau sebatas produk trauma?
#21 Terrified
Di pinggiran kota Buenos Aires,
rentetan kejadian gaib menghinggapi beberapa rumah dan menciptakan kengerian
yang menambat atensi sejak awal. Trik menakut-nakutinya dibangun secara
efektif, terlebih saat melibatkan sesosok mayat yang duduk manis di meja makan.
Bukan saja meninggalkan bayangan yang sulit dilupakan, tetapi juga rasa was-was
lantaran kita tidak tahu apa yang mungkin diperbuatnya.
#20 Sebelum Iblis Menjemput
Timo Tjahjanto kembali dengan
ciri khasnya melalui Sebelum Iblis
Menjemput yang level kebrutalannya terbilang tinggi. Tanpa ampun, dia terus
menerus menghajar penonton dengan teror sedari mula sampai penghujung durasi
yang menjadikan kegiatan “menghembuskan nafas lega” mustahil untuk dilakukan.
Lagipula, kapan lagi kita bisa melihat Pevita Pearce yang dikenal kalem berubah
jadi zombie ganas?
#19 Green Room
Green Room menghantarkan kita menuju sebuah bar di desa terpencil
yang dipunyai kelompok militan neo-nazi. Belum apa-apa, sudah terdengar seperti
sebuah tempat yang seharusnya dihindari. Saat satu band diundang tampil di sana
dan mereka menjadi saksi pembunuhan, sisa durasi diisi permainan
kucing-kucingan yang membuat diri ini pengap karena intensitasnya sanggup
terjaga stabil.
#18 Hush
Hush memanfaatkan set dengan ruang gerak terbatas dan karakter inti
yang hanya dua orang secara maksimal. Hasilnya, ketegangan tak berkesudahan
yang membuat hamba kesulitan untuk memalingkan muka dari layar barang sejenak.
Kita bersimpati pada sang target pembunuhan – seorang perempuan tuli yang hidup
sendirian di tengah hutan – dan kita berharap dirinya dapat menaklukkan si
pembunuh gila yang menyebalkan.
#17 Let Me In
Tidak banyak remake yang memiliki kualitas setara dengan materi sumbernya. Let Me In yang disadur dari film Swedia
bertajuk Let the Right One In adalah
salah satu yang nggak malu-maluin. Sajian horor yang mengedepankan narasi
mengenai persahabatan manusia dengan vampir ini bukan hanya tampak cantik
secara presentasi visual, tapi juga mempunyai sederet momen meneror yang
memunculkan sensasi bergidik. Jangan-jangan, salah satu sahabatmu ternyata
makhluk penghisap darah. Hiii…
#16 Munafik
Saat pertama menonton Munafik, hamba sama sekali tidak
menyangka akan dibuat meringkuk. Disamping jump
scares yang ditempatkan secara efektif, narasinya yang terasa dekat adalah
alasan lain mengapa film ini bisa sedemikian mencekam. Tentang bagaimana
orang-orang saleh menjauhi Tuhan dengan caranya masing-masing, dan tentang cara
sang sutradara memvisualisasikan adegan kesurupan dimana iblis kebal terhadap
lantunan ayat-ayat suci.
#15 The Autopsy of Jane Doe
Sesosok mayat tanpa identitas
ditemukan dan penonton dibawa memasuki ruang otopsi yang berada di bawah tanah.
Nuansa klaustrofobiknya terasa mencekat sementara kehadiran si mayat jelas sama
sekali tidak membantu. The Autopsy of
Jane Doe telah membuat penontonnya was-was hanya dari suasana, lalu si
pembuat film menambahkannya dengan unsur supranatural yang menjadikan menit
demi menitnya kian mencekam.
#14 The Cabin in the Woods
Duo Drew Goddard dan Joss Whedon
berhasil menampilkan teror klasik yang mencekam dengan balutan dialog berselera
humor tinggi, sindiran-sindiran atas ramuan klise film horor, dan narasi yang
tak mudah ditebak kemana akan bermuara di sini. 20 menit terakhir The Cabin in the Woods membuktikan
betapa cerdasnya sang sutradara dalam membingkai sebuah kado istimewa untuk
para penikmat tontonan seram.
#13 The Babadook
Idenya menarik, mengenai memedi
yang mencuat dari buku kanak-kanak dan meneror bocah yang membacanya. Desain si
monster pun bikin bergidik ngeri dengan giginya yang runcing dan jari-jari
tangannya yang panjang. Namun sumber kengerian utama The Babadook bukan berasal dari si monster, melainkan dari tokoh
ibu yang belum bisa menerima kehilangan. Lukanya secara perlahan tapi pasti
mendorong dia bertransformasi menjadi sosok beringas yang tak lagi dikenal oleh
sang anak.
#12 Get Out
Mengunjungi rumah calon mertua
boleh jadi memberi pengalaman menegangkan bagi beberapa orang. Oleh Jordan
Peele, pengalaman ini dielaborasinya menjadi sajian horor menggigit dengan
sentuhan komedi dan kritik sosial dimana istilah “too good to be true” berlaku. Melalui kacamata si tokoh utama,
kita bisa merasakan adanya kejanggalan dari sikap pelayan, tamu, sampai si
pemilik rumah yang tampak terlalu kaku maupun terlalu sempurna. Rasanya diri
ini ingin teriak kepadanya, “cepat keluar
dari sana!”
#11 It: Chapter One
Jika saya adalah Stephen King,
saya akan bangga sekali terhadap interpretasi termutakhir dari It ini. Bukan saja cakap dalam
menggambarkan ikatan persahabatan para karakternya, It: Chapter One pun luwes dalam menggeber momen-momen menyeramkan
yang menciutkan nyali. Sensasi yang diberikannya seperti tengah menjelajahi
wahana rumah hantu; seru, menegangkan, sekaligus menyeramkan. Kita bisa
berteriak-teriak, lalu ketawa-ketawa setelahnya. Plus, Pennywise bangke sekali
di sini!
#10 A Quiet Place
Hidup tanpa boleh bersuara saja
sudah menyiksa, apalagi ditambah adanya monster yang selalu siap siaga untuk
menerkam setiap kali kamu bersuara. Bisa dibayangkan dong seperti apa
tekanannya? Premis high concept ini
berhasil diejawantahkan oleh John Krasinski melalui karya perdananya yang amat
mencekam. Saking mencekamnya, A Quiet
Place memungkinkan bagi penonton untuk ikut merasakan bagaimana sumpeknya hidup
para keluarga di film ini termasuk merasakan sakitnya tertusuk paku yang
merupakan salah satu villain terbaik
dalam khasanah tontonan horor.
#9 Doctor Sleep
Meski Doctor Sleep memiliki muatan laga cukup kental bak tontonan superhero dengan tampilan visual cukup
imajinatif nan membangkitkan selera, film tetaplah menghembuskan kengerian yang
bersumber dari nada pengisahan yang suram, tindakan sang villain dalam menyedot “uap” dari para pemilik kekuatan khusus yang
didahului dengan siksaan keji, sampai referensi ke film pertama (The Shining) yang acapkali menyeramkan.
Bagaimanapun juga, apapun yang melibatkan Hotel Overlook tidak akan pernah bisa
menggoreskan imaji yang indah.
#8 Pengabdi Setan
Jawaban dari tanya, “apakah Pengabdi Setan versi Joko Anwar ini
lebih mencekam dibanding pendahulunya?,” memang akan sangat relatif. Namun bagi
hamba secara pribadi, Pengabdi Setan
versi anyar ini sanggup menimbulkan mimpi buruk. Salah satu film horor
Indonesia paling menyeramkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perjalanan
mengarungi wahana rumah berhantu ini, saya beberapa kali dibuat terperanjat
seperti pada adegan lempar selimut, mendengarkan drama radio, pipis di tengah
malam, sampai tiap kali terdengar suara gemerincing lonceng Ibu.
#7 Don’t Breathe
Don’t Breathe mempunyai setumpuk adegan yang memungkinkanmu
berkeringat dingin, mengeluarkan sumpah serapah, dan kesulitan menghembuskan
nafas lega lantaran daya cekamnya yang tidak main-main. Tanpa perlu diberi
peringatan untuk “jangan bernafas”, hamba sudah terlebih dahulu menahan nafas
karena bagaimana mau bisa bernafas lha
wong film ini sedemikian mencekamnya. Saya hanya ingin tiga berandalan di
sini bisa terbebas dari cengkraman si pria buta yang rupa-rupanya jauh lebih
berbahaya dari yang diperkirakan.
#6 The Wailing
Bagaimana seandainya seorang
misterius tiba-tiba datang ke desamu dan sejurus kemudian, wabah sulit
terjelaskan melanda seantero desa? Pertanyaan berbau pengandaian tersebut jelas
mengerikan saat betul terjadi, bahkan ketika sebatas kisah fiktif dalam The Wailing pun telah sanggup memberikan
efek ngeri. Pemicunya adalah permainan atmosfer yang memicu kegelisahan,
jalinan pengisahan sarat misteri yang memantik diskusi, serta faktor kedekatan.
Tidak bisa disangkal, aktivitas berbau klenik mudah dijumpai di sekitar kita.
#5 Train to Busan
Kita bisa berteriak-teriak, “ayo lekas lari, lekas,” saat gerombolan
zombie bersiap memangsa para karakter dalam Train
to Busan. Kita ikut diliputi amarah membara tatkala salah seorang karakter
egois bersama gerombolan hasutannya mengisolasi karakter-karakter yang tak
sejalan pemikiran dengan mereka. Lalu, kita pun merasakan ketidakrelaan teramat
sangat ketika satu persatu tokoh baik mulai terinfeksi. Kemampuan untuk
melibatkan emosi secara penuh inilah yang membuat atensi penonton sanggup
terpancang di sepanjang durasi yang berlangsung amat menegangkan.
#4 Hereditary
Nada pengisahan yang depresif
disertai imaji-imaji yang mengganggu (halo, kepala buntung!) adalah jalan yang
ditempuh oleh Hereditary untuk menggoreskan
trauma kepada penonton. Coba bayangkan kamu dibawa memasuki rumah minim
penerangan, lalu dipertemukan dengan satu keluarga disfungsional yang tingkah
polahnya senantiasa membuat gelisah, dan kita diperangkap di sana. Tentu, ini
definisi sesungguhnya dari mimpi buruk apalagi jika kemudian kamu melihat ada
yang terbakar dan merayap di dinding.
#3 Under the Shadow
Seringkali, saat kita bisa
merasakan ada sesuatu yang salah tapi kita tidak dapat melihatnya, itu terasa
lebih meneror lantaran ketidaktahuan mengenai apa yang sejatinya sedang
dihadapi. Under the Shadow
mempermainkan ketakutan dan imajinasi penonton dengan cara tersebut dimana
keganjilan-keganjilan kerap dijumpai tanpa sumber yang pasti. Benarkah ada
makhlus halus yang mengganggu si pemilik rumah? Kalaupun tak ada, film memiliki
sumber teror lain yang ancamannya lebih nyata yakni bermukim di tengah zona
perang dan pemerintah yang opresif.
#2 The Conjuring / The Conjuring 2
Sulit untuk memilih salah satu
karena dwilogi The Conjuring
mempunyai kualitas setara dalam hal bercerita maupun menakut-nakuti. Saat diri
ini mengira momen hide and clap dari
jilid awal telah menetapkan standar tinggi dalam perkara meneror, babak kedua
mempersembahkan sosok biarawati ikonik dan “menggubah ulang” satu dua tembang
klasik menjadi lagu pengundang memedi. Alhasil, terlonjak, berteriak diikuti
tawa gemas guna melepas cemas, sampai meringkuk manis di balik jaket atau
bantal adalah reaksi yang sangat mungkin kamu alami kala menyaksikan dwilogi
ini.
#1 Insidious
Hal terbaik dari Insidious adalah saya tidak pernah
memprediksi film garapan James Wan ini akan membuat hamba lemas tanpa daya di
dalam bioskop. Terornya gila tidak main-main, Bung! Di kala kepercayaan
terhadap sajian horor dari Negeri Paman Sam telah merosot drastis, film ini
mengembalikannya dengan mempersembahkan tontonan seram yang memakai formula
klasik: rumah berhantu. Kepiawaian sang sutradara dalam mengatur waktu dan trik
penampakan adalah alasan utama mengapa setiap jump scares yang kamu jumpai di sini terasa tepat guna. Tak ada
yang mubazir, semuanya efektif dalam merontokkan bulu kuduk apalagi ditambah sokongan iringan musik biadab dari Joseph Bishara. Perlu diingat, film inilah yang menciptakan tren berwisata ke dunia astral dalam banyak tontonan horor setelahnya.
Apakah kamu mempunyai film favorit yang tidak tercantum dalam daftar di atas? Mari dibagi lewat komen.